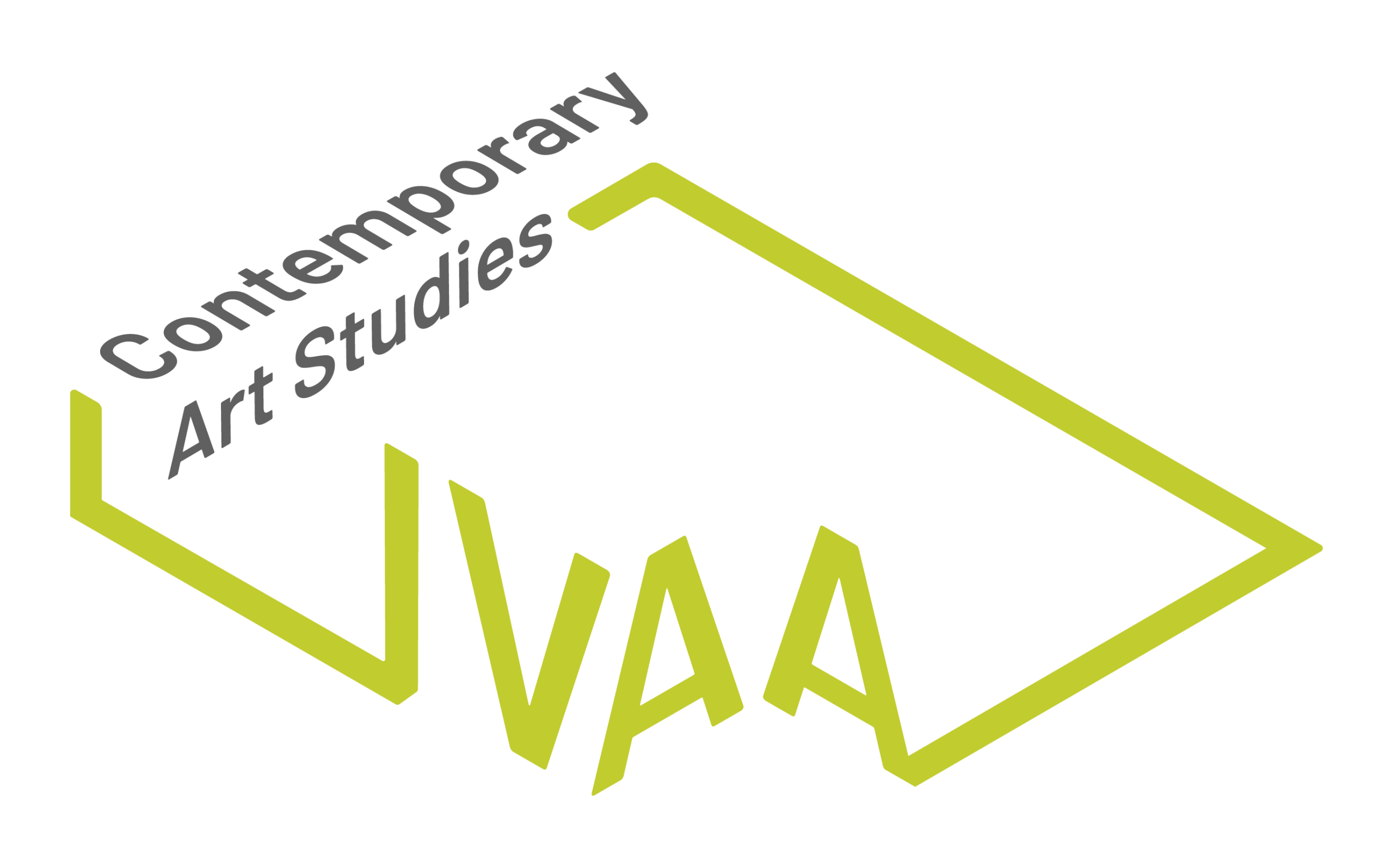Semiotika dan Hipersemiotika Kode Gaya dan Matinya Makna
Penulis : Yasraf Amir Piliang
Tahun : 2019
Editor : Alfatri Adin & Taufiqurrahman
Penyelaras Akhir : Marlina Kuspawestri
Perancang Sampul : Miftah Farid
Penerbit : Cantrik Pustaka
 Buku ini dimulai dengan definisi semiotika yang mencengangkan dari Umberto Eco. Secara tandas ia mewedarkan bahwa semiotika pada prinsipnya adalah “sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).” Definisi Eco ini secara eksplisit menegaskan betapa sentral konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi prinsip utama semiotika itu sendiri. Eco lalu melanjutkan: “Bila sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengungkap dusta, maka sebaliknya ia tidak dapat pula digunakan untuk mengungkap kebenaran (truth)—ia pada kenyataannya, bahkan tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan apa-apa”.
Buku ini dimulai dengan definisi semiotika yang mencengangkan dari Umberto Eco. Secara tandas ia mewedarkan bahwa semiotika pada prinsipnya adalah “sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).” Definisi Eco ini secara eksplisit menegaskan betapa sentral konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi prinsip utama semiotika itu sendiri. Eco lalu melanjutkan: “Bila sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengungkap dusta, maka sebaliknya ia tidak dapat pula digunakan untuk mengungkap kebenaran (truth)—ia pada kenyataannya, bahkan tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan apa-apa”.
Bertolak dari definisi tersebut, Yasraf Amir Piliang mengembangkan secara kreatif apa yang ia sebut sebagai hipersemiotika. Hipersemiotika, dengan demikian, adalah teori tentang dusta—tetapi juga dimaksudkan sebagai ikhtiar pelampauan atas selubung dusta demi merengkuh secara penuh (atau mungkin tak sepenuhnya utuh) tentang kebenaran yang terserak di dalam relasi-relasi sublim tanda, gaya, kode, makna, iklan, seni, agama, dan hal-hal yang menyehari di sekitar kita.
Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni Sejarah Lekra 1950-1965
Penulis : Keith Foulcher
Tahun : 2020
Penerjemah : Rima Febriani
Penyunting : Kelana Wisnu Sapta Nugraha
Perancang grafis : Sidney Islam
Ilustrasi sampul : Cukil Kayu oleh Arifin, 1964
Penerbit : Pustaka Pias
 Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni Sejarah Lekra 1950-1965. Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni menghadirkan gambaran perjuangan realistis Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), tidak saja perihal perdebatan mengenai arah kebudayaan nasional dan internasional, tetapi juga mengenai perbedaan pendapat dan pendirian dalam tubuh Lekra di pusat dan daerah. Keberagaman pandangan dan pendapat dalam Lekra tidak terbatas pada asas ideologi dan rumusan gagasan, melainkan juga soal langkah praktis dalam segala bidang kesenian untuk mewujudkan kebudayaan nasional berdasar kebenaran yang mereka yakini. Gambaran ini sekaligus membuktikan secara terbalik predikat yang selama ini disematkan terhadap Lekra, yang dicap sebagai tukang onar kebudayaan. Jika tidak terjadi pembunuhan massal menyusul peristiwa G30S yang juga menghancurkan Lekra, organisasi kebudayaan terbesar pada masanya ini genap berumur tujuh puluh tahun.
Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni Sejarah Lekra 1950-1965. Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni menghadirkan gambaran perjuangan realistis Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), tidak saja perihal perdebatan mengenai arah kebudayaan nasional dan internasional, tetapi juga mengenai perbedaan pendapat dan pendirian dalam tubuh Lekra di pusat dan daerah. Keberagaman pandangan dan pendapat dalam Lekra tidak terbatas pada asas ideologi dan rumusan gagasan, melainkan juga soal langkah praktis dalam segala bidang kesenian untuk mewujudkan kebudayaan nasional berdasar kebenaran yang mereka yakini. Gambaran ini sekaligus membuktikan secara terbalik predikat yang selama ini disematkan terhadap Lekra, yang dicap sebagai tukang onar kebudayaan. Jika tidak terjadi pembunuhan massal menyusul peristiwa G30S yang juga menghancurkan Lekra, organisasi kebudayaan terbesar pada masanya ini genap berumur tujuh puluh tahun.
DARI DALAM KUBUR
Penulis : Soe Tjen Marching
Tahun : 2020
Penerbit : Marjin Kiri
 Sejak kecil, Karla merasa diperlakukan tidak adil oleh ibunya yang ia anggap misterius. Namun tak ada seorang pun dalam keluarga yang membelanya. Inilah yang membuat Karla tak mempunyai pilihan selain menjauh dari keluarganya. Berpuluh tahun sesudahnya, barulah satu demi satu rahasia itu mulai terkuak baginya—bukan hanya rahasia yang menggelayuti keluarganya, tetapi juga banyak manusia lainnya.
Sejak kecil, Karla merasa diperlakukan tidak adil oleh ibunya yang ia anggap misterius. Namun tak ada seorang pun dalam keluarga yang membelanya. Inilah yang membuat Karla tak mempunyai pilihan selain menjauh dari keluarganya. Berpuluh tahun sesudahnya, barulah satu demi satu rahasia itu mulai terkuak baginya—bukan hanya rahasia yang menggelayuti keluarganya, tetapi juga banyak manusia lainnya.
“Soe Tjen menceritakan kisah keluarga, terutama hubungan anak perempuan dan ibunya yang misterius, sekaligus membuka kisah yang lebih luas. Kita bisa melacak jejak tragedi negeri ini melalui kisah mereka yang tersembunyi, menguak kompleksitas dan kepahitan rasialisme, agama, bahkan kasta dalam masyarakat. Namun tak seperti novel-novel politik yang sibuk berteriak-teriak, ia tetap kisah manusia-manusia yang dipertalikan satu sama lain oleh kemanusiaan mereka—yang baik maupun biadab. Terakhir, saya menemukan sesuatu yang tak mungkin bisa dilakukan para penulis lelaki: kisah tentang rahim. Saya merasa dibawa untuk melihat, atau merasakan, sesuatu yang sangat perempuan.” — Eka Kurniawan, novelis, penulis Cantik Itu Luka
“Novel Soe Tjen Marching merupakan salah satu narasi penting tentang bagaimana perempuan, begitu juga gerakannya, dihancurkan dengan keji oleh militerisme di Indonesia. Berlatar sejarah, dengan detail yang belum pernah diungkap selama ini.” — Martin Aleida, sastrawan, penulis Tanah Air yang Hilang
“Novel ini adalah catatan tentang penindasan dan ketidakadilan yang tak terelakkan akibat identitas rasial, pilihan akan Tuhan, dan kepentingan politik. Pada akhirnya, kisah dalam novel ini kembali mengingatkan bahwa cara terbaik menghadapi segala luka dan trauma adalah mengingat dan mengisahkannya kembali dengan sepenuh kesadaran.” — Okky Madasari, novelis, penulis Entrok
Seni, Konteks, Kampung dan Kota
Penyunting : Adin
Tata Letak & Sampul : Yuswinardi
Foto : Tim Dokumentasi Hysteria
Desain Sampul : Irwan Gatot
Tim Riset Pekakota : Nilam Cahya Sukma, Adin, Iqbal Alma Ghosan Altofani, Oktav Bagus
Penerbit : Hysteria
 Bagaimana seni dalam konteks masyarakat hari ini? apa peranannya dan apa ia juga berfungsi mengubah masyarakat atau hanya mengayakan perspektif saja? debat seni untuk seni dan seni untuk masyarakat bukan hal baru.
Bagaimana seni dalam konteks masyarakat hari ini? apa peranannya dan apa ia juga berfungsi mengubah masyarakat atau hanya mengayakan perspektif saja? debat seni untuk seni dan seni untuk masyarakat bukan hal baru.
Buku ini mencoba mendedah pengalaman Kolektif Hysteria dalam laku kebudayaanya mengarungi gagasan peran seni dalam konteks di mana kelompok ini tumbuh dan berkembang dengan mengambil kasus Penta KLabs II yang diadakan di Nongkosawit, Gunungpati, Semarang 2018 lalu. Penta KLabs sendiri adalah biennale a la Hysteria sebagai pengembangan proyek seni yang dirintis berbasis situs spesifik sejak 2013 yang pertama kali diinisiasi di Tugu dan Bustaman. Eksperimen ini dilanjutkan tahun 2016 di Kemijen dan selalu berpindah-pindah tempat tiap dua tahun sekali dengan isu yang beragam.
Sebagai generasi yang tumbuh dalam gegap gempita revolusi 4.0, digital native, problem dan peluang otonomi daerah, serta ketimpangan ekosistem seni di Indonesia Hysteria menempuh jalannya sendiri mencipta biennale, mengakali teknologi, dan bernegosiasi dengan banyak pihak. Melalui biennale sederhana inilah Hysteria tahun 2019 memenangkan Grand Prize YouFab Award di Jepang yang pameran dan penghargaanya dilaksanakan akhir Februari 2020 di Tokyo. Menariknya YouFab Award fokus pada inovasi teknologi dan masyarakat dan seperti diketahui Hysteria tidak mengembangkan teknologi advance seperti dibayang-bayangkan orang kebanyakan.
Harapannya buku ini mengayakan praktik-praktik seni dengan masyarakat di era generasi milenial, yang bisa jadi berbeda dengan komunal sisa-sisa perlawanan orde baru yang mempunyai dinamikanya sendiri.
Keindonesiaan, Kerakyatan dan Modernisme dalam Kritik Seni Lukis di Indonesia
Penulis : Sanento Yuliman
Tahun : 2020
Penyunting dan esai penutup : Hendro Wiyanto
Esai Pengantar : Aminudin T.H. Siregar
Penyelaras bahasa : Alpha Hambally & Annayu Maharani
Perancang buku : Andang Kelana
Penerbit : Gang Kabel
 Sanento Yuliman mengkaji dengan cermat kritik seni lukis di Indonesia, antara masa 1930-an hingga akhir 1960-an. Ia mengamati isu-isu di dalam kritik, bentuk, sifat, dan cara menulis para kritikus. Penelitian semacam itu baginya berguna untuk mendorong pandangan baru di dalam kritik, menyingkirkan prasangka dan menghindari lingkaran masalah yang “begitu-begitu juga”. Pendeknya ia menghendaki perbaikan dalam menulis kritik.
Sanento Yuliman mengkaji dengan cermat kritik seni lukis di Indonesia, antara masa 1930-an hingga akhir 1960-an. Ia mengamati isu-isu di dalam kritik, bentuk, sifat, dan cara menulis para kritikus. Penelitian semacam itu baginya berguna untuk mendorong pandangan baru di dalam kritik, menyingkirkan prasangka dan menghindari lingkaran masalah yang “begitu-begitu juga”. Pendeknya ia menghendaki perbaikan dalam menulis kritik.
Tiga isu besar yang diperdebatkan dalam kritik seni lukis adalah soal keindonesiaan, kerakyatan dan modernisme. Paham keindonesiaan tidak cuma satu, tapi beberapa. Akan tetapi, semua pandangan itu cenderung normatif. Isu kerakyatan timbul ketika fungsi sosial seni dipertanyakan, demi kepentingan sosio-politis. Adapun modernisme— dilandasi kebebasan, kreatifitas serta nilai perorangan—dalam kenyataan segera berhadapan dengan berbagai kritik, yakni kritik kultural, kritik sosial, kritik politis, dan kritik sosiologis.
Selain itu, ada masalah mengenai penyebutan aliran-aliran seni lukis akibat persentuhan dengan seni lukis Barat. Survei Sanento di buku ini membuktikan bahwa penetapan aliran umumnya dilakukan kritikus sambil lalu, tanpa penelitian dan pembandingan, tidak jarang sekadar “impresionisme impulsif” dari para kritikus subjektivis. Bagi Sanento, pengindonesiaan istilah untuk isme-isme yang sesuai dengan konteks perkembangan seni lukis kita amat penting. Pemecahan masalah-masalah ini dapat membentuk pengetahuan kita tentang seni lukis Indonesia, melalui klasifikasi dan sistematisasi.
Survei ke dalam penulisan kritik inilah yang kemudian ‘melahirkan’ Sanento Yuliman sendiri sebagai kritikus seni rupa terkemuka di Indonesia.
Buku ini merupakan seri ketiga dari serangkaian karya lengkap Sanento Yuliman setelah Estetika yang Merabunkan: Bunga Rampai Esai dan Kritik Seni Rupa (1969-1992) dan Pasfoto Sang Iblis: Bunga Rampai Esai Kebudayaan, Puisi, Karikatur, dan lain-lain (1966-1990).
SENI RUPA SENYAP
Penulis : Agus Koecink
Tahun : 2020
Editor : Rusdi Zaki
Perancang sampul : Alek Subairi
Gambar sampul : Agus Koecink
Penerbit : Pagan Press
 Kalau saya perhatikan, dari berbagai sepak terjang dan tulisan-tulisannya, antara Agus Koecink dan kucing, memiliki beberapa kesamaan sifat. Kalau setiap kucing mempunyai teritori, maka Agus Koecink juga punya teritori, yaitu Surabaya dan Jawa Timur itu tadi. Teritori inilah yang terus ia jaga sepenuh hati. Ia intai dari waktu ke waktu. Kalau ketemu “mangsa” (hal menarik), kemudian ia “terkam” (baca : ditulis). Bahkan saat ia “terkam”, ia kunyah-kunyah dulu hingga lumat; tidak untuk dimakan sendiri, justru kemudian dibagi-bagi kepada yang lain, dalam hal ini pembaca. Itulah cara dia “mengeong”, menjaga seni rupa Surabaya, Jawa Timur termasuk di dalamnya Madura. -Yusuf Susilo Hartono-
Kalau saya perhatikan, dari berbagai sepak terjang dan tulisan-tulisannya, antara Agus Koecink dan kucing, memiliki beberapa kesamaan sifat. Kalau setiap kucing mempunyai teritori, maka Agus Koecink juga punya teritori, yaitu Surabaya dan Jawa Timur itu tadi. Teritori inilah yang terus ia jaga sepenuh hati. Ia intai dari waktu ke waktu. Kalau ketemu “mangsa” (hal menarik), kemudian ia “terkam” (baca : ditulis). Bahkan saat ia “terkam”, ia kunyah-kunyah dulu hingga lumat; tidak untuk dimakan sendiri, justru kemudian dibagi-bagi kepada yang lain, dalam hal ini pembaca. Itulah cara dia “mengeong”, menjaga seni rupa Surabaya, Jawa Timur termasuk di dalamnya Madura. -Yusuf Susilo Hartono-
ROSA LUXEMBURG BUKU 1: SOSIALISME DAN DEMOKRASI
Penulis : Dede Mulyanto
Tahun : 2019
Pengantar : Ted Sprague
Penerbit : Marjin Kiri
 Menggabungkan metode penulisan riwayat diri dengan telaah pemikiran, buku ini menyajikan Rosa Luxemburg sebagai pejuang Demokrasi Sosial dalam gaya naratif yang mudah dicerna dan dinikmati.
Menggabungkan metode penulisan riwayat diri dengan telaah pemikiran, buku ini menyajikan Rosa Luxemburg sebagai pejuang Demokrasi Sosial dalam gaya naratif yang mudah dicerna dan dinikmati.
Buku pertama dari rencana dua jilid buku ini mengkhususkan diri pada pembahasan isu-isu seputar demokrasi dan sosialisme yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini, saat ide-ide sosialisme kembali dipeluk anak-anak muda sedunia di tengah kebangkrutan tatanan yang ada.
Akan kita temukan pemikiran Rosa Luxemburg mengenai Demokrasi Sosial sebagai leburan antara sosialisme dengan gerakan kelas pekerja, termasuk uraiannya tentang kapan persisnya aksi-aksi demonstrasi dan pemogokan bisa digunakan secara tepat; bagaimana seharusnya sosialisme menyikapi agama, baik umat maupun pemukanya; sikapnya yang anti terorisme politik; beserta kecenderungan internasionalnya dalam perjuangan demokrasi. Tak heran bila sejak jauh-jauh hari Sutan Sjahrir, Kasman Singodimedjo, maupun Tan Malaka menyuruh kita agar mempelajari dan bertauladan kepada Rosa Luxemburg.
Amrus Natalsya: Mutiara dari Bumi Tarung
Penulis : EZ Halim
Tahun : 2020
Editor : Candra Gautama
Fotografer Karya : Lim Hui Yung
Perancang Sampul & Penata Letak : Wendie Artswenda
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
 Buku ini membawa Anda dalam jiwa dan pikiran Amrus Natalsya -seorang pematung dan perupa terkemuka, pendiri Sanggar Bumi Tarung bersama Misbach Tamrin- lewat karya-karyanya yang tersimpan dalam Museum Ezham milik kolektor EZ Halim. Amrus dikenal sebagai seniman dengan peran vital yang luar biasa, bahkan ketika hidupnya dihempaskan ke lubang penderitaan oleh penguasa politik setelah pecah Peristiwa G30S pada 1965. “Ia sudah terbiasa dengan gelora hidup. Yang sangat menyenangkan diterima dengan senyum biasa. Yang merisaukan dan menyakitkan juga diterimanya dengan biasa,” kata sejumlah rekannya sesama perupa.
Buku ini membawa Anda dalam jiwa dan pikiran Amrus Natalsya -seorang pematung dan perupa terkemuka, pendiri Sanggar Bumi Tarung bersama Misbach Tamrin- lewat karya-karyanya yang tersimpan dalam Museum Ezham milik kolektor EZ Halim. Amrus dikenal sebagai seniman dengan peran vital yang luar biasa, bahkan ketika hidupnya dihempaskan ke lubang penderitaan oleh penguasa politik setelah pecah Peristiwa G30S pada 1965. “Ia sudah terbiasa dengan gelora hidup. Yang sangat menyenangkan diterima dengan senyum biasa. Yang merisaukan dan menyakitkan juga diterimanya dengan biasa,” kata sejumlah rekannya sesama perupa.
Membaca Praktik Negosiasi Seniman Perempuan dan Politik Gender Orde Baru
Penulis : Alia Swastika
Tahun : 2019
Penyunting : Intan Nurjannah
Desain dan Tata Letak : Lelaki Budiman, Edwin Prasetyo
Penerbit : Ford Foundation
 Saya kira 1970an akhir dan 1980an menjadi sebuah periode yang menarik terutama karena kekuatan Orde Baru yang sangat kuat dalam hal stabilitas politik dan ekonomi. Melalui Garis Besar Haluan Negara, sebuah visi politik ekonomi diciptakan, dan diorganisir secara masif melalui berbagai jenis propaganda. Secara umum, gerakan sipil dijauhkan dari politik, termasuk gerakan perempuan. Dari gerakan yang progresif seperti Gerwani pada 1960an, pemikiran perempuan dijinakkan dan dimasukkan dalam sangkar domestik melalui Dharma Wanita dan PKK. Di sisi yang lain, melihat bagaimana propaganda dan ideologi developmentalisme Orde Baru mempengaruhi dinamika seni (rupa), terutama dalam konteks gender.
Saya kira 1970an akhir dan 1980an menjadi sebuah periode yang menarik terutama karena kekuatan Orde Baru yang sangat kuat dalam hal stabilitas politik dan ekonomi. Melalui Garis Besar Haluan Negara, sebuah visi politik ekonomi diciptakan, dan diorganisir secara masif melalui berbagai jenis propaganda. Secara umum, gerakan sipil dijauhkan dari politik, termasuk gerakan perempuan. Dari gerakan yang progresif seperti Gerwani pada 1960an, pemikiran perempuan dijinakkan dan dimasukkan dalam sangkar domestik melalui Dharma Wanita dan PKK. Di sisi yang lain, melihat bagaimana propaganda dan ideologi developmentalisme Orde Baru mempengaruhi dinamika seni (rupa), terutama dalam konteks gender.
Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Maret 2021