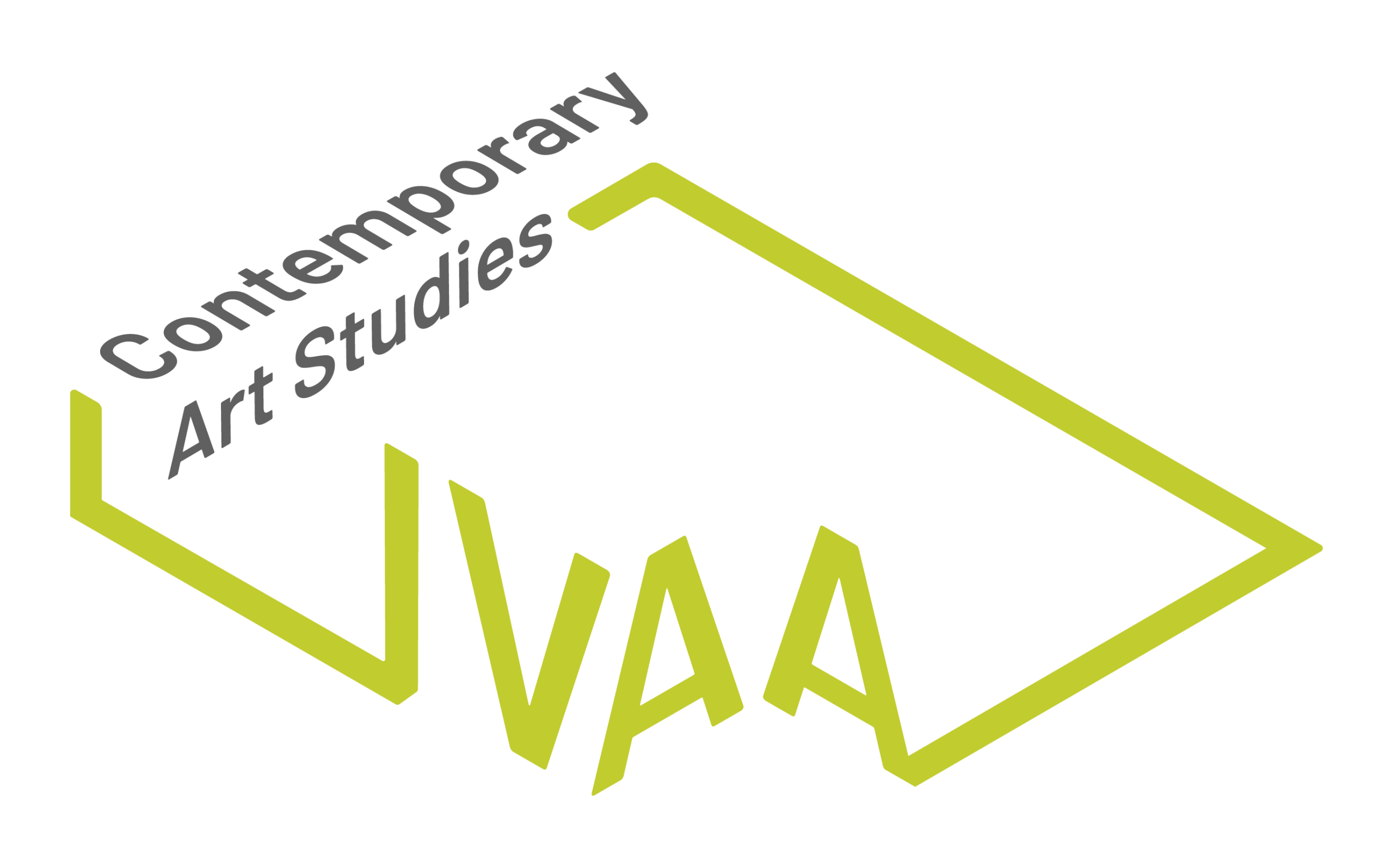Oleh: Tiatira Saputri
Belakangan ini, kami banyak menerima undangan seminar, diskusi, fgd hingga perhelatan seni yang menggunakan istilah riset sebagai bagian dari metode kerjanya. Baik yang dilakukan oleh institusi, kolektif, komunitas dan ruang seni. Sebagian contohnya ialah seminar internasional yang diselenggarakan oleh program pascasarjana ISI Surakarta. Sekira kurang dalam satu semester ini terdapat beberapa acara yang berkaitan dengan riset artistik. Belum lagi ketika mengingat beberapa proyek seni berbasis komunitas dan dengan model kerja kolaborasi. Banyak yang memposisikan riset sebagai bagian dari kerja kolaboratif, yang dilakukan baik oleh seniman, bersama dengan kurator dan penelitinya, di suatu lokasi, isu atau tema tertentu. Pameran atau proyek seni berbasis riset, tentu tidak hanya satu dua tahun ini kita dengar gemuruhnya. Beberapa perhelatan, baik itu proyek seni komunitas maupun helat sebesar Biennale dan proyek seni berbasis kota lainnya saya jadikan contoh dalam membahas kecenderungan model kerja yang berbasis pada riset atau melibatkan riset sebagai bagian dari runutan kerjanya.
Ada dua forum yang baru-baru ini diselenggarakan yang kami jadikan sampel, yang pertama ialah penyelenggaraan fgd Rumah Seni Cemeti yang digagas oleh Arham Rahman terkait proyek seni “Kolektif Kolegial”, dan yang kedua ialah forum berjudul Seminar Internasional Artistic Research, yang diselenggarakan oleh program pasca sarjana ISI Surakarta. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa riset artistik seakan baru muncul ke permukaan baru-baru ini? Jika dilihat dari sudut pandang institusi yang menginisiasi forum, tentu kita tidak bisa menemukan alasan yang sama persis. Tapi ada satu hal yang meresahkan terlihat pada kedua diskusi tersebut, yaitu penggunaan istilah baru: ‘riset artistik’.
Selain dari dua model forum yang berbeda tersebut, kita juga bisa melihat kecenderungan-kecenderungan ini dari beberapa platform seni. Ambil contoh saja Biennale Jogja Equator XIII 2015. Dengan gagasan produksi kolaboratifnya platform ini membawa kita melihat bagaimana cita-cita Biennale Equator mengembangkan perspektif yang diwujudkan melalui ke ragaman interaksi. Biennale Equator mensyaratkan adanya kerja-kerja penelitian agar para seniman bisa menerjemahkan elaborasi gagasan mereka dalam bahasa karya. Tulisan kurator rekanan dari Afrika, Jude Anogwih pada naskah kuratorialnya menyebutkan secara gamblang “Enam dari daftar seniman ini (Aderemi Adegbite, Ndidi Dike, Victor Ehikhamenor, Amarachi Okafor, Olarenwaju Tejuosho dan Emeka Udemba) menjalankan terlebih dahulu residensi selama sebulan di Yogyakarta untuk melakukan penelitian, menganalisis, berinteraksi, dan terlibat dalam proses artistik dalam mengolah pertemuan mereka”. Dalam hal ini Biennale Equator terbuka pada metode kerja yang melibatkan riset. Di sini yang perlu kita waspadai ialah bahwa pembahasan soal riset artistik baik di Cemeti, ISI Surakarta, dan juga pada tulisan ini, tidak memiliki kepentingan dengan pengkotak-kotakan karya menjadi berbasis atau tidak berbasis riset.
Platform seni yang mewadahi keterlibatan publik secara langsung bisa dilihat dari model kerjanya yang mempertemukan seniman dan masyarakat. Atau dengan menggunakan cara lain yakni dengan meletakkan proses penciptaan di tengah masyarakat. Jakarta Biennale 2015 secara khusus mempraktikkan gagasan ini untuk merespon permasalahan di sekitar warga Jakarta, dengan metode intervensi artistik di ruang kota. Praktik artistik di ruang publik menjadi salah satu cara Jakarta Biennale 2015 mengupayakan lahirnya gagasan-gagasan kritis dari para agen artistik, baik warga maupun seniman. Selain itu ada juga perhelatan yang secara khusus membuat program workshop riset artistik, seperti yang dilakukan oleh Indonesian Dance Festival. Melalui workshop ini para koreografer diharapkan dapat memperkaya persepektif serta semakin kritis.
Kembali lagi pada Jakarta Biennale 2015. Selaku penyelenggara, mereka mengejar praktik-praktik riset dan kolaborasi untuk mewadahi pengalaman artistik warga, ekspresi baru seniman, serta pengetahuan-pengetahuan yang dipertukarkan dalam ruang kota, seperti paparan Ade Darmawan selaku direktur eksekutif Jakarta Biennale 2015, “Di tataran selanjutnya, sangat penting untuk melihat praktik-praktik seni rupa yang melibatkan diri dengan persoalan sosial masyarakat ini sebagai bagian dari pergumulan sehari-hari, agar tak cuma dirayakan tapi juga dipertanyakan, dikritisi, dan dioptimalkan. Oleh karena itu Jakarta Biennale kali ini memfokuskan diri pada karya-karya berbasis proyek riset, kerja lintas disiplin, maupun kerja bersama komunitas yang melibatkan partisipasi warga”. Kerja-kerja Jakarta Biennale seperti itu, oleh ruangrupa disebut sebagai mediasi publik.
Selama ini medasi publik sendiri menjadi strategi sosial sekaligus visi artistik ruangrupa. Dan menghasilkan proyek-proyeknya yang banyak diselenggarakan dalam format festival atau setidaknya pada situasi yang tidak berjarak dan mengundang banyak orang dari berbagai layer. Tetapi untuk bisa berada pada posisi tidak berjarak dengan masyarakat, dibutuhkan pembacaan-pembacaan aktual pada lingkungannya. Seperti pada salah satu programnya, “Apartement Project” (2003), ruangrupa memfasilitasi penelitian berbasis residensi dengan apartement sebagai isu, obyek, sekaligus lokasi seniman beresidensi, seperti yang dituturkan Tomoko Take pada c atatan p enelitian Apartement Project-nya “Tiba-tiba saya berada di dunia lain. Tinggal di Jakarta bersama lima orang yang belum saya kenal. Di sini segalanya berbeda, sehingga saya tidak begitu merasa nyaman pada awalnya. Karena itu saya tertarik untuk menemukan persamaan yang kami miliki. Jika saya lebih dapat menemukannya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Kami melakukan penelitian dari wawancara yang menitikberatkan pada Apartemen Rasuna dan daerah kumuh sekitarnya, serta Rumah Susun sebagai hunian kelas menengah kebawah”. Pada proyek ini seniman berkarya melalui beberapa metode, yaitu penelitian dan residensi. Serta melibatkan kerja observasional dengan pengalaman bermukim sementara di wilayah yang sedang dipelajari.
Proyek serupa di tahun 2006 juga diselenggarakan oleh Yayasan Seni Cemeti, dan dalam catatan kuratorial “Shortwave”, Pius Sigit menuliskan “Pproyek ini adalah proyek yang melibatkan seniman untuk diterjunkan ke Sindang, Indramayu, Jawa Barat, untuk melakukan proyek tamu tinggal berbaur dengan masyarakat selama kurang lebih 14 hari. Di lokasi tersebut seniman akan melakukan riset singkat di mana hasilnya akan mereka tuangkan dalam karya-karya visual”. Jelas bahwa riset digunakan sebagai dasar, pendekatan, pengenalan dan proses pengolahan dalam penciptaan karya. Selain itu juga ada program residensi ‘Landing Soon’, yang menempatkan riset sebagai salah satu modal seniman untuk bisa mendekati dan menyentuh satu kebudayaan baru yang ditemuinya. Seperti yang diungkapkan Michiel Morel selaku rekan penyelenggara, pada buku 25 tahun Cemeti “Bagi Heden program seniman residensi penting untuk mempersatukan para seniman dengan suatu budaya non Barat dan memberi mereka peluang mengeksplorasi berbagai praktik seni di Indonesia. Refleksi mendalam, riset, dan eksplorasi praktik seni dalam lingkungan yang beragam merupakan bagian dari tujuan yang hendak dicapai”.
Dari kumpulan pernyataan di atas, kita bisa melihat bagaimana di periode 2000-an wacana seni kita ramai dengan praktik-praktik berbasis riset. Tapi pertanyaannya kemudian, apa yang hendak kita kembangkan dari penggunaan istilah baru ini, ‘riset artistik’ Menilik dari terminologinya sebagai produksi pengetahuan, apakah yang bisa disumbangkan ‘riset artistik’ di luar wilayahnya? Apakah penggunaan nama ‘riset artistik’ menandai bahwa dalam praktiknya ia benar-benar dijalankan sebagai satu tawaran segar untuk disiplin ilmu yang lain, atau semata-mata hanya untuk mempercanggih praktik seni itu sendiri? Karena jika ia berhenti pada percanggihan praktik seni, kecenderungannya praktik ‘riset artistik’ ini hanya akan menjadi satu genre baru.
Bahan :
1. Transkrip Seminar Internasional “Artistic Research”
2. Transkrip Diskusi Kolektif Kolegial