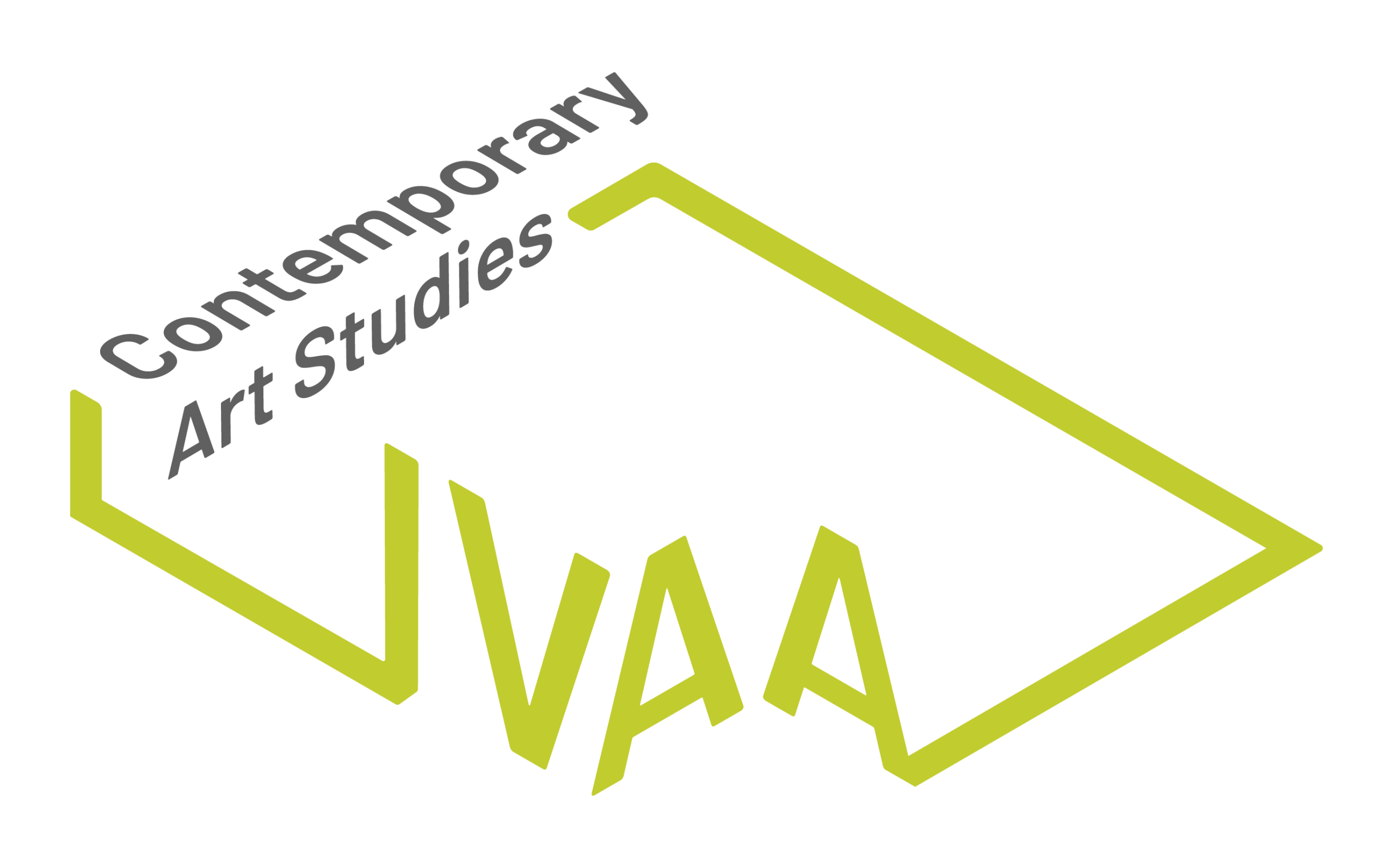oleh Hardiwan Prayoga
Melihat bagaimana peristiwa seni sebagai fenomena penting atau menjadi preseden terbentuknya sebuah peristiwa yang lebih besar, “Sejarah Senyap” dipilih sebagai tema dari program Tuhfah yang diselenggarakan pada edisi 2005/2006. Tuhfah adalah program pemberian hibah untuk penulisan penelitian seni visual yang dilaksanakan oleh Yayasan Seni Cemeti/ YSC (sekarang Indonesian Visual Art Archive/ IVAA) dan telah memasuki edisi yang ketiga. Pada dua edisi sebelumnya, tahun 2003 dan 2004, hibah ini pernah mendanai dua penelitian. Pertama mengangkat persoalan hubungan antara seni rupa dan Lekra yang kemudian menjadi buku Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa – Lekra 1950-1965, dengan penerima hibah kala itu adalah Antariksa. Berikutnya yang kedua, membicarakan seputar sejarah pengkoleksian seni rupa di Indonesia, kala itu Primanto Nugroho menjadi peneliti yang berkesempatan mendapat hibah. Proyek-proyek penelitian ini mendapat hibah setelah mengajukan proposal yang bersaing dengan beberapa peserta. Mekanisme yang sama juga diterapkan pada edisi 2005/2006.
Masih satu benang merah dengan dua penelitian terdahulu, edisi ketiga Tuhfah tidak jauh dari wacana seputar seni dan kekuasaan. I Ngurah Suryawan adalah peneliti yang mendapat kesempatan menerima hibah penelitian. Dalam beberapa tulisannya, Suryawan terlihat memang memiliki fokus pada tema-tema seputar dekolonisasi dan kekuasaan pada praktik seni rupa. Tulisan Suryawan berjudul Mempertanyakan Konstruksi Pengaruh Ekspatriat, menanggapi opini Agus Dermawan T (ADT) yang menurutnya meromantisasi dan mengglorifikasi kehadiran pelukis-pelukis asing di Bali.
Tanpa pretensi menjadi primordial atau xenophobia, Suryawan ingin melihat dengan posisi lebih kritis terhadap pelukis asing di Bali. Segala perspektif yang memposisikan mereka secara agung, pastilah telah melalui konstruksi, pertarungan, dan saling klaim pengaruh. Ini merupakan dampak dari kenyataan bahwa catatan sejarah memang ditulis oleh pemenang dan penguasa. Menurut Suryawan, catatan sejarah seni rupa Bali yang hari ini eksis tidak lebih dari konstruksi dari pelukis asing yang berkongsi dengan elit pribumi, dalam kasus ini adalah pendirian Pita Maha yang melibatkan Walter Spies dan Rudolf Bonnet dengan Raja Tjok Raka Sukawati. Sejarah seni rupa Bali seharusnya juga disandingkan dengan catatan dari pihak yang disebut Suryawan “kalah”, seperti lukis wayang Nagasepaha, Kerambitan, Sanur, Pelukis Lekra, dan sebagainya. Berkebalikan dengan ADT yang berhadap pada kembalinya pelukis asing seperti dulu, Suryawan berpendapat bahwa diri kitalah yang seharusnya mengkonstruksi diri kita sendiri, yang kemudian diakui kualitas, visual dan integritasnya oleh masyarakat seni dunia.
Dengan judul Dari Mooi Indie ke Mendobrak Hegemoni: Pergulatan Seni dan Rezim Kekuasaan 1930-2005 di Bali, Suryawan masih berada dalam perbincangan soal kesenian di Bali. Meski sudah banyak tulisan yang mengulas tentang sejarah seni di Bali, namun belum mengurai lebih detail pada relasi kekuasaan yang beroperasi antara sejarah seni, kuasa, politik kebudayaan, dan peranan agensi-agensi yang memainkannya. Sejarah dalan tulisan Suryawan ini bukan dimaknai sebagai masa lalu yang berjalan linier, tetapi sebuah ruang hidup yang bisa diberi makna dalam berbagai bentuk pertarungan representasi. Wacana ini dibedah dengan melihat bahwa relasi kuasa melekat dan menubuh pada praktik-praktik kehidupan manusia. Tidak terkecuali seni, yang tidak dapat dilepaskan dari denyut nadi politik kebudayaan yang berkembang.
Suryawan melihat bahwa setiap penguasa atau rezim melahirkan jargon kekuasaannya masing-masing. Rezim kolonial menciptakan ideologi “Balinisasi/ Baliseering”, Orde Baru menciptakan “Pariwisata Budaya”, dan Era Reformasi memunculkan gerakan politik kebudayaan “Ajeg Bali”. Lintasan waktu ini yang menjadi benang merah periodisasi penelitian Suryawan, yaitu dari zaman Mooi Indie awal abad 20 hingga peristiwa Mendobrak Hegemoni awal abad 21. Kehadiran pelukis-pelukis barat seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet, dan Arie Smith dalam rentang waktu 1927-1956, secara tidak sadar memberi pengaruh paling dasar dalam perubahan tematik, cara, hingga paradigma seni di Bali. para pelukis barat yang berkongsi dengan Raja Ubud Tjokorda Gde Raka Sukawati ini telah merubah tema-tema lukisan Bali yang tadinya bercorak tradisi-religius dari epos-epos Mahabarata dan Ramayana.
Situasi ini berjalan bersama dengan ramainya promosi wisata Bali dan kelahiran Pita Maha. Menurut Suryawan, upaya untuk menjaga tradisi berasal dari kolonial yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dan kuasa untuk memelihara Bali sebagai “museum hidup” dan surga eksotika untuk kebutuhan pariwisata rezim kolonial. Proyek pentradisian ini dikenal sebagai Baliseering. Ideologi ini yang juga kemudian merembes pada praktik kesenian. Maka masyarakat membajak sawah, tubuh perempuan telanjang dada, ritual agama, sabung ayam, mendominasi citra lukisan kala itu. Ada “generasi seniman politik” tahun 1960-an, berupaya melawan representasi tersebut, hanya saja mereka “menghilang” pasca peristiwa 65.
Setelah berjalan cukup panjang semenjak masa kolonial hingga orde baru yang semakin mengukuhkan posisi seni dan budaya sebagai stempel “pariwisata yang berbudaya”, 23-24 Februari 2001 digelar sebuah acara bertajuk Mendobrak Hegemoni yang digagas Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (Kamasra) STSI/ ISI Denpasar. Apa yang ikonik dalam gelaran tersebut adalah tema dan lukisan yang berani menghujat dan menyerang Sanggar Dewata Indonesia (SDI), Nyoman Erawan, Nyoman Gunarsa, Made Wianta, Putu Wirata Dwikora, hingga institusi dan media yang memperpanjang relasi hegemonik. Puncaknya menurut Suryawan, terjadi ketika Kamasra mengadakan Pesta Kapitalisme Bali tahun 2001 sebagai kritik dari Pekan Kesenian Bali (PKB). PKB dinilai semakin membosankan dan hanya melanggengkan “Pemerintah Kolonial Bali”. Narasi yang demikian eksplisit mengundang reaksi keras dari Rektor STSI kalai itu yaitu Wayan Dibia hingga memerintahkan pameran dibongkar secara paksa.
Melanjutkan semangat gugatan pada praktik-praktik kekuasaan tersebut, pasca rangkaian peristiwa Mendobrak Hegemoni, berdiri Komunitas Pojok dan Klinik Seni Taxu. Kegiatan kedua kelompok ini adalah diskusi, pameran, hingga menerbitkan buletin. Aktivitas mereka berada dalam benang merah kritik dan desakralisasi seni-budaya Bali. Salah satunya adalah Pameran Memasak & Sejarah, di Cemeti Art House (sekarang Cemeti Institute for Art & Society), 9 Juni – 4 Juli 2004. Pameran ini ingin mengurai jerat-jerat kekuasaan hegemonik yang membuat banyak suara dibungkam, manusia dipaksa kalah, ingatan yang dipendam dan dokumen tak terungkap.
Bali, sebagai wilayah yang selalu dikesankan unik dan menjadi tujuan wisata, nyatanya tidak bisa menghindar dari tragedi yang sama. Sekitar seratus ribu nyawa melayang selagi terjadi kekerasan 1965-1966. Karena berhubungan dengan perasaan sanak-keluarga korban, Klinik Seni Taxu berhadapan dengan persoalan etik jika ingin mengangkat tema tersebut. Maka dari itu, kemudian pameran ini menggunakan pendekatan humanisme agar tidak terjebak dalam gambaran kekerasan yang vulgar dan jargon politik yang dangkal. Esai pengantar pameran ini ditulis oleh I Ngurah Suryawan, Seriyoga Parta, dan Hendra.
Dalam penelitian yang didukung oleh program Tuhfah kali ini, Suryawan banyak mengumpulkan kliping dari berbagai media yang memuat liputan dan opini tentang peristiwa Mendobrak Hegemoni dan terbitan dari kelompok-kelompok alternatif semacam Klinik Seni Taxu. Beberapa di antara artikel tersebut bisa diakses di online archive IVAA dan dibaca langsung di perpustakaan IVAA:
- Menuju Gerakan Seni Rupa Baru Bali: Membongkar Hegemoni Moral dan Kultural Seni Rupa
- Cermin Ketidakharmonisan, Reputasi STSI Capai Titik Nol
- Dibia Sudah Minta Maaf, Kelompok ‘Terhujat’ Masih Emosi
- Dobrakan Ragu-Ragu Kamasra
- Kamasra dan Dobrakan Eksistensial
- Dukung Kamasra, Mahasiswa Unud Demo sambil Bakar Lukisan
- Kamasra Persiapkan Dialog Terbuka
- Kritik Seni dan Penghujatan terhadap Seniman
- Mendobrak dengan Apa?
- Mendobrak Hegemoni, Mengapa Hanya Mengejek?
- Referensi Saya adalah Diri Saya Sendiri
- Sanggar Dewata Tantang Kamasra Tunjukan Karya
- Seni Melawan Seni
- Seni Rupa Bali Rusak karena Kapitalisme
- Wacana Hegemoni Seni Rupa Bali Perlu Diteruskan
Sedangkan hasil penelitian Suryawan sepanjang 123 halaman dalam program Tuhfah 2005/2006 dan beberapa edisi buletin Kitsch dari Klinik Seni Taxu yang mewadahi berbagai pemikiran alternatif seni rupa khususnya di Bali, dapat diakses di perpustakaan IVAA.