

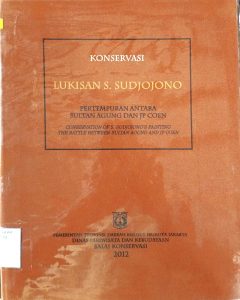 Judul : Konservasi Lukisan S. Sudjojono
Judul : Konservasi Lukisan S. Sudjojono
Penyusun : Agi Ginanjar, Tri Praptiani Maruto, dan Hasanudin
Penanggung Jawab : Candrian Attahiyyat
ISBN : –
Jumlah halaman : 120
Bahasa : Indonesia – Inggris
Tahun terbit : 2012
Dimensi : 26,5 x 32 cm
Ulasan oleh : Ardhias Nauvaly
Menciptakan mahakarya adalah satu soal. Mempertahankannya untuk mendekati abadi adalah soal lain yang tidak kalah rumitnya. Setidaknya, itulah yang terjadi juga pada lukisan gigantik “Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen” karya pelukis legendaris S. Sudjojono.
Lukisan cat minyak pada kanvas berukuran 10 x 3 meter ini mulai mengalami kerusakan setelah 30 tahun dipajang di Museum Nasional Jakarta. Padahal, sang pelukis membayangkan lukisannya bisa awet paling tidak 300 tahun. Permasalahan inilah yang coba dipecahkan lewat serangkaian konservasi lukisan yang didokumentasikan dalam buku Konservasi Lukisan S. Sudjojono.
Buku ini berformat laporan kegiatan institusi resmi. Terlihat dari sampulnya yang polos, hanya mencetak judul dan penulis/penerbit yaitu Balai Konservasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Ukurannya yang besar, 26,5 x 32 cm, membuatnya tidak bisa fleksibel dibawa kesana kemari. Meskipun begitu, 120 halaman tergolong tipis bagi buku dwibahasa dengan gambar ilustrasi yang bertebaran.
Fitur fisik dan visualnya membuat buku ini bukan untuk dibaca santai, ia sepertinya lebih tepat dibaca sebagai acuan referensi kegiatan konservasi. Maka dari itu, nyaris mustahil buku ini jatuh ke tangan pembaca iseng yang mencari bacaan di waktu luang. Gambar-gambar yang ada bukan hiburan macam komik, tetapi lebih kepada ilustrasi yang memperjelas langkah-langkah konservasinya.
Kesan “melaporkan” juga kuat bila meninjau struktur penyajian bukunya. Bab pertama mengetengahkan proses konservasi lukisan. Ia meninjau perkara teknis konservasi, terutama lukisan. Namun sepertinya buku ini asyik juga untuk pemula seperti saya atau yang sudah berpengalaman. Bagi pemula, gambaran dasar tahapan konservasi lukisan dapat terbayangkan. Saya yang memang sedang belajar konservasi dari dasar jadi mengetahui perbedaan konservasi secara umum dengan restorasi yang merupakan tahap perbaikan atau pengembalian kondisi koleksi sebagaimana “aslinya”.
Sementara bagi ahli, detail teknis dan bahan konservasi bisa diperoleh pada poin restorasi. Di sana, kegiatan restorasi dibagi menjadi konsolidasi dan penambalan (inlay). Bahan-bahannya pun dibedakan, misal pada konsolidasi menggunakan perekat Lascaux 375, pada penambalan menggunakan Paraloid B.72. Teknis penambalan juga dijelaskan terperinci seperti kain linen yang direnggangkan lalu diolesi perekat dan penggunaan stabilitex dari kain organdi dan Beeva Film pada bagian belakang tambalan.
Sebenarnya, buku ini menghendaki dirinya lebih dari sekadar laporan. Setelah bab awal, buku ini menjelaskan juga mengenai peristiwa sejarah yang ditangkap dalam lukisannya, profil dan sepak terjang pelukisnya, serta proses produksi lukisannya sendiri. Bagi pembaca awam, pendalaman konteks semacam ini dapat menjelaskan urgensi konservasinya. Hanya, bagi saya, informasi tentang profil seniman serta sejarah peristiwa pertempuran Mataram dengan VOC bukan sajian utama yang patut dikutip. Masih ada buku-buku lain yang memang mengkhususkan diri kepada itu.
Bila memang ada hal-hal di luar konservasi lukisan yang patut dicermati, itu adalah proses riset dan produksi karyanya. Bila konservator yang membacanya, dia akan mengetahui nilai-nilai penting yang patut dilestarikan seperti kenampakan ragam busana dari prajurit-prajurit Sultan Agung sebab Sudjojono memang melakukan riset dan akhirnya mengetahui bahwa pasukan penyerbuan ke Batavia banyak diambil dari daerah tundukan atau sekutu Mataram Islam.
Sementara bagi awam, dia akan langsung merasakan betapa Sudjojono tidak (pernah) main-main dengan karya lukisnya. Dia sampai melawat ke Belanda untuk mengakses literatur dan arsip. Saat proses sketsa, dia menggunakan praktik teatrikal dengan model. Dia meminta rekan-rekannya di Belanda untuk berpose mengikuti bayangannya tentang pertempuran tersebut. Ini diniatkannya untuk melihat guratan wajah yang otentik dari orang-orang Belanda yang marah dan meregang nyawa.
Memang, ada kekurangan seperti pembahasan yang tidak runut. Bila memang hendak menyajikan ide secara utuh, beberapa bab di awal seharusnya memperbincangkan tentang konteks lukisan (karya dan seniman), diikuti dengan proses produksi, barulah masuk kepada tahapan konservasi. Meskipun kekurangan sistematika yang demikian, buku ini tetap nyaman dibaca–teknisnya jelas dan urgensi konservasi juga dipaparkan secara mendalam (seniman hebat dan lukisannya, namun mulai rusak), dan, ya, bonus proses produksi “belakang kanvas” yang tidak kalah menarik untuk disimak.

Judul : Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis
Editor : Widiantoro
Penulis : Haryatmoko
Tahun terbit : 2016
Penerbit : PT Kanisius Yogyakarta
ISBN : 978-979-21-4561-8
Ulasan oleh : M. Yusuf Habibulloh
Haryatmoko menyajikan tulisan-tulisan yang mencoba membongkar rezim kepastian dengan mencoba mengulas pemikiran enam filsuf pascastrukturalis. Keenam filsuf tersebut di antaranya Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze, dan Jacques Derrida. Akan lebih menarik jika kita ulas satu persatu pemikiran dari keenam filsuf pascastrukturalis ini.
Dimulai dari pemikirannya Michel Foucault yang menghubungkan relasi pengetahuan – kekuasaan. Pengetahuan difungsikan sebagai komponen penting dalam mencapai kekuasaan itu sendiri. Kemudian dari Pierre Bourdieu yang membagi kelas sosial berdasarkan kepemilikan kapitalnya. Muncul mekanisme kekuasaan atas kepemilikan kapital seperti kapital ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Filsuf bernama Jean Baudrillard mengangkat tema perilaku masyarakat konsumeris melalui manipulasi tanda dan hiperrealitas. Sikap konsumeris muncul karena adanya pembentukan nilai suatu barang.
Selanjutnya adalah Paul Ricoeur. Pemikirannya berusaha mengembangkan metode penafsiran teks dengan metode hermeneutika. Menurutnya, tafsiran lebih baik jika mampu membuat penafsirnya lebih memahami diri. Kemudian Gilles Deleuze, ia mencoba mengkritik tiga pemahaman, yaitu psikoanalisis, fenomenologi, dan strukturalisme. Terakhir dari Jacques Derrida, ia memaparkan perlawanannya pada pemaknaan semiotika melalui analisis dekonstruksi, yaitu mencoba membongkar dan menemukan kata kunci yang selalu dianggap benar dan mencoba menganalisis unsur-unsur yang hilang di dalam teks.
Pemikiran keenam filsuf tersebut cukup menarik untuk dipelajari, terlebih mampu mengajak pembaca untuk mempertajam pikiran kritisnya berkaitan dengan fenomena yang ada. Melalui penggambarannya, buku ini mencoba membongkar rezim kepastian melalui analisis tajam mengenai kepastian yang dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dan tak boleh diganggu gugat.
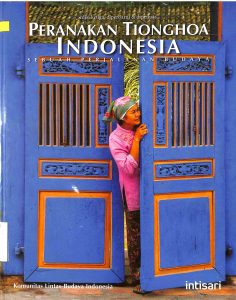
Judul : Peranakan Tionghoa Indonesia (Sebuah Perjalanan Budaya)
Editor naskah : Lily Wibisono, Rusdi Tjahyadi
Bahasa : Indonesia
ISBN : 979-23-5846-3
Jumlah halaman : 482 halaman
Edisi : Ketiga
Tahun terbit : 2018
Penerbit : Komunitas Lintas Budaya Indonesia dan Majalah Intisari
Ulasan oleh : Diah Ayu Meiliniasari
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat berdamai dengan dirinya sendiri.”
Keberagaman identitas di Indonesia menunjukkan betapa kayanya warisan budaya bangsa yang beraneka ragam. Kisah tentang peranakan Tionghoa, identitas, kehidupan, dan budayanya, bukanlah sekadar tinjauan tentang benda koleksi atau karya seni langka dari masa yang sudah berlalu, namun kisah tentang manusia yang masih berlangsung dan menjadi bagian dari cerita besar proses nation-building bangsa Indonesia.
Perjalanan budaya komunitas Tionghoa peranakan di Indonesia turut memperkaya bangsa ini. Pada awal tahun 2009, buku ini terbit dan diluncurkan bersamaan dengan pembukaan dan penyelenggaraan Pameran Warisan Budaya Tionghoa Peranakan Indonesia yang didukung Bentara Budaya Jakarta (BBJ), sebuah lembaga budaya di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Akulturasi yang unik dan amat kaya manifestasinya menunjukkan bahwa entitas keturunan Tionghoa mewarnai kebudayaan Indonesia.
Buku “Peranakan Tionghoa Indonesia” berisikan pengetahuan tentang berbagai aspek budaya Tionghoa Peranakan di Indonesia, mulai dari sejarah dan budaya peranakan secara umum, kuliner, arsitektur, busana, seni pertunjukan, pers dan sastra, hingga perabotan dan segala aksesoris rumah tangga. Buku ini terus mengalami pembaharuan hingga saat ini telah terbit sebanyak tiga edisi. Edisi pertama menggunakan bahasa Indonesia terbit pada tahun 2009, kemudian edisi kedua menggunakan bahasa Inggris. Edisi kedua (2012) diperluas, Indonesian Chinese Peranakan, A Cultural Journey, terdapat empat bab baru, yaitu keramik asal Tionghoa, kain sulaman Peranakan Tionghoa, sistem kekerabatan warga Tionghoa, serta masalah Tionghoa Peranakan yang lebih ditentukan oleh budaya ketimbang faktor genetis. Pada tahun 2018, edisi ketiga terbit membawa warna baru dengan adanya tambahan empat buah tulisan, Prof. Ariel Heryanto yang berjudul “Peranakan: yang Punah, yang Mengglobal”; ulasan berjudul “Evolusi Batik Peranakan Tionghoa di Pulau Jawa” oleh pakar batik William Kwan Hwie Long; penuturan Musa Jonatan tentang “Yin Hoa: Lembaga Seniman Indonesia Tionghoa”; dan kisah “Nyonya Rumah Legenda Kuliner dari Lasem” oleh Lily Wibisono.
Buku ini berkontribusi dalam memberikan sumbangan informasi tentang indahnya keanekaragaman budaya di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Tionghoa. Dikemas menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana, pembaca akan mampu mengenali dan memahami kebudayaan Tionghoa dengan mudah. Selain itu, ilustrasi penggambaran Tionghoa dengan warna cerah dan tajam mampu memanjakan visual pembaca dan mengurangi rasa bosan. Dengan jumlah halaman 482 lembar dan berat lebih dari 1 kg, buku ini sulit dibawa ke mana-mana. Isi buku ini cukup lengkap untuk pemula yang ingin belajar kebudayaan Tionghoa. Namun dengan harga yang terbilang mahal, buku ini tidak banyak orang yang mampu memiliki buku ininya. Oleh karena itu, jika ingin membaca buku ini silakan mengunjungi perpustakaan IVAA yang berada di Gang Hiperkes 188 A-B Jalan Ireda, Dipowinatan Keparakan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan reviewer untuk kedepannya, buku “Peranakan Tionghoa Indonesia” dapat diterbitkan ke dalam seri-seri lebih ringkas lagi.

Judul : Yang Hilang Ditelan Kuasa
Editor Naskah : Anwar Jimpe Rachman
Bahasa : Indonesia
ISBN : 978-623-90129-3-9
Jumlah halaman : 191
Tahun terbit : 2022
Penerbit : Yayasan Makassar Biennale
Ulasan oleh : Dhiyah Istina
Pandemi yang terjadi di tahun 2019 berdampak besar pada dunia kesenian, hal tersebut tidak luput menimpa Makassar Biennale yang akhirnya terus melakukan pergerakan dengan berbagai adaptasi untuk menjaga lintas jaringan antar komunitas-komunitas yang baru dibangun. Adaptasi tersebut terus berlanjut hingga Makassar Biennale tahun 2021, bentuk dan kemasan kegiatan tetap disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Lokasi pertemuan antar akademisi, praktisi dan warga biasa dilakukan di kawasan batu gamping terbesar di dunia. Pemilihan lokasi tersebut diharapkan mampu memunculkan perhatian yang lebih dari semua kalangan yang diakibatkan oleh penambangan dan beragamnya bentuk eksploitasi di kawasan batu tersebut.
Hal menarik dalam kata pengantar dari Direktur Makassar Biennale (Anwar Jimpe Rachman) adalah bahwa dalam proses kegiatan ini, pengarsipan secara daring maupun luring merupakan hal yang sangat penting. Isi buku ini memperlihatkan proses seniman membaca Pegunungan Karst Maros-Pangkep dan dialog-dialog yang tercipta di antara seniman yang diabadikan dalam pengarsipan berbentuk transkrip. Seniman yang terlibat di dalam penelitian ini adalah Nurhady Sirimorok, Maharani Budi, Louie Buana, dan Nirwan Ahmad Arsuka.
Buku ini dituliskan menjadi beberapa subbab yang dimulai dari “Penelusuran dan penemuan jejak kreativitas di Sulawesi Selatan” oleh Nurhady Sirimorok, “Proses reinterpretasi sejarah melalui visual storytelling” oleh Lontara Project, “Narasi mengenai Tanah Suci Bentangan Kala” oleh Nirwan Ahmad Arsuka, dan dialog-dialog yang dibagi menjadi subbab “Menjawab teka-teki lukisan purba di Belae”, “Maris waktu peradaban manusia dan gambar purba”, “Tentang gambar gua dan hal-hal setelahnya”, “Pembacaan praktik penyebarluasan dan pengarsipan materi sejarah”, dan “Peluncuran “Tiga Batu dan Asap””. Bentuk transkrip dialog dimulai dari subbab “Pembukaan” antara Wilda Yanti Salam sebagai pemandu acara, F. Daus AR sebagai koordinator Makassar Biennale di Pangkep, Nurhady Sirimorok, Nirwan Ahmad Arsuka, Halim HD, dan Anwar Jimpe Rachman. Pembukaan Makassar Biennale yang dilakukan dengan konsep semi perkemahan ini ditutup dengan menonton video dokumenter yang dikumpulkan oleh para peneliti selama proses penelitian di gua-gua karst.
Buku Yang Hilang Ditelan Kuasa adalah buku yang menceritakan serangkaian kegiatan Makassar Biennale yang diakhiri dengan peluncuran film “Tiga Batu dan Asap”. Dialog yang hadir dalam buku ini mampu membawa pembaca menelusuri lebih dalam mengenai kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan. Pendapat dan temuan menjadi lebih hidup seiring dengan diskusi-diskusi yang telah ditranskrip dengan rapi. Menurut saya, buku ini memudahkan berbagai kalangan umum untuk memahami sebuah penelitian karya seni dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Proses membaca juga menjadi lebih asik seolah para pembaca juga ikut duduk mendengarkan di dalam forum tersebut. Penulisan transkrip yang dibuat apa adanya memberikan kesan yang tidak berjarak, sehingga membuat pembaca akan merasa bahwa pengetahuan itu milik bersama.