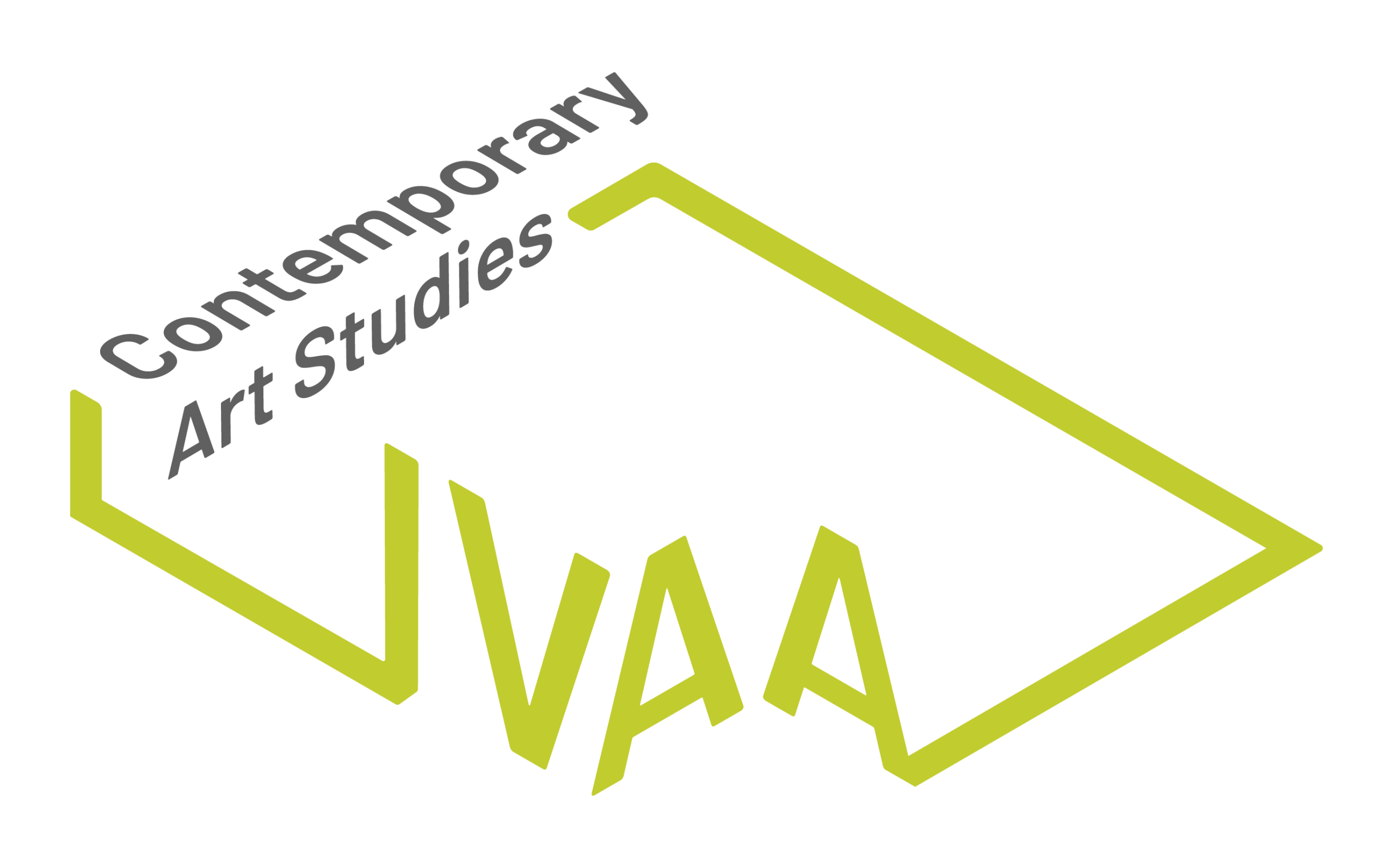oleh Hardiwan Prayogo
Pada sekitar 2007, Raihul Fadjri, melalui harian Tempo, mengulas tiga pameran bertajuk One Month Stop dan New Cock on the Block di Kedai Kebun Forum, dan Fibre Face Yogya 2007 di Rumah Budaya Babaran Segaragunung. Ketiga artikel ini yang menjadi pemicu awal pemilihan terhadap tema newsletter September-Oktober. Narasi yang kemudian dapat disarikan dari pameran-pameran tersebut adalah soal upaya menuangkan gagasan dan keterampilan artistik dalam produk konsumsi sehari-hari. Seniman yang telah berubah dari pencipta mahakarya menjadi seorang pekerja seni normal tanpa pretensi membuat mahakarya.
Menjelang boom seni lukis 2008, isu penghasilan alternatif, industri kreatif, dan basis ekonomi alternatif bagi pekerja seni visual juga coba diketengahkan. Selain itu juga terdapat usaha meretas gengsi antar medium, seperti seni serat atau media batik. Medium-medium demikian coba dihayati sebagai media dengan jangkauan tertentu agar bisa menampung gagasan ekspresif sebagaimana media cat dan kanvas. Satu ciri khas dari seni serat adalah sentuhan crafting yang tekun dan detail. Sebuah ironi jika praktik budaya massa merubahnya menjadi ringan dan instan.
Penelusuran lebih jauh, ditemukan nama-nama pelaku seni yang terlibat dalam pameran tersebut, seperti Agung Kurniawan, Uji Handoko, Iyok Prayogo, Krisne Widhiathama, Iwan Effendi, Wedhar Riyadi, dan Irene Agrivina Widyaningrum. Uji Handoko dan Irene Agrivina Widyaningrum akhirnya kami perdalam melalui sub-rubrik Sorotan Dokumentasi. Sedangkan lainnya, membawa kami lebih lanjut pada penelusuran arsip koleksi IVAA.
Sebuah artikel dengan judul Wacana Bangkrut, Kurator Gendut ditulis oleh Agung Kurniawan dan dimuat di Koran Tempo tertanggal 31 Desember 2008. Agung membicarakan situasi di mana pameran kerap bermimpi merangkum, mencatat, dan menahbiskan wacana baru. Meski sebenarnya yang terjadi hanya menyalin skala ruang, bukan ideologinya. Seluruhnya memang ditujukan untuk membangun strategi bagaimana menjual dan menjual karya. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Sanento Yuliman, bahwa kehadiran pasar berpotensi melahirkan keseragaman gaya. Maka pada 2008, Agung menilai skena seni rupa didominasi oleh 2 arus besar. Pertama gaya Juxtapoz dan kedua new painting Eropa. Diawali dari logika pasar yang selalu menuntut “barang baru”, permintaan pasar karya seniman-seniman yang disebut di awal tulisan mulai menggila. Banyaknya pameran dalam kurun waktu yang singkat melahirkan kemandekan wacana karena situasi kejar tayang ini. Dari sini, kami kemudian mencoba mencari kata kunci berikutnya, bukan lagi nama pelaku seni, tetapi diksi-diksi yang beredar dalam wacana ini.
Melalui kata “elitis” dan “seni sehari-hari”, kami menemukan dua artikel. Pertama Menduniawikan Nilai Estetika yang Sakral, kedua Seni Rupa Sehari-hari: Menentang Elitism. Kedua artikel yang ditulis pada 1987 ini merupakan bagian dari Katalog Seni Rupa Baru Proyek 1 Pasaraya Dunia Fantasi. Artikel pertama ditulis oleh Arief Budiman. Tulisan ini diawali dengan pertanyaan tentang nilai mana yang harus diikuti: nilai universal atau kontekstual. Kesenian akhirnya melahirkan dua jenis dikotomis: yang sah-elitis dan seni di kalangan sehari-hari rakyat jelata. Tarikannya kemudian menuju pemaknaan atas pengalaman estetik. Dalam logika nilai universal, pengalaman estetik akan diaktivasi ketika subjek manusia bertemu dengan objek seni. Jika sensasinya tidak muncul, maka ketidakpekaan ada pada manusianya.
Gagasan ini diafirmasi oleh tulisan kedua, yang mempermasalahkan bahwa ada “kesenian kelas wahid” dan “kesenian kelas kambing”. Lebih konkrit, bila ada seni murni, maka ada seni tidak murni. Kategorisasi ini yang menjadi pangkal dari segregasi citra kesenian. Ini akhirnya mempengaruhi kerja kesenimanan menjadi lebih transendental, ketika seniman membutuhkan kontemplasi dan mengasingkan diri dari lingkungannya demi menciptakan karya yang sensasional. Dengan kata lain otoritas menjadi nilai yang mutlak dan murni dimiliki oleh seniman.
Paradigma universal ini kemudian melahirkan respon reaksioner, yakni paradigma estetika kontekstual. Ini adalah nilai estetika yang berproses antara manusia. Singkatnya bukan lagi nilai transendental. Estetika universal perlu dilawan dengan nilai-nilai yang lebih demokratis. Tahun 70-an, Soedjoko pernah mencanangkan anti “seni rupa elitis” yang berakar pada paham Yunani dan Renaissance. Secara radikal, Sudjoko kembali pada konsep seni dalam Bahasa Indonesia, yaitu seni yang menyenangkan dan berfaedah bagi orang banyak. Ketika kesenian terpenjara dalam kaidah-kaidah estetik, maka pandangan akan masalah sosial akan selalu dianaktirikan dalam proses penciptaan karya.
“Pasaraya Dunia Fantasi” berangkat dari kegelisahan ini. Maka yang dipamerkan adalah benda sehari-hari, atau simbol-simbol rupa urban. Kemudian medium yang digunakan dalam praktik semacam ini disebut sebagai found object, atau readymade. Diksi-diksi ini memang belum dikenal pada tahun tersebut. Namun dua artikel ini cukup memberikan gambaran perkembangan wacananya.
Kami kemudian melanjutkan penelusuran arsip berdasarkan kata kunci lain, yaitu ‘terapan’. Dari kata ini, ditemukan dua peristiwa seni, yakni Pameran Seni Rupa “Eksodus Barang” dan Pameran Seni Terapan 1993-1994: Seni Kriya dalam Budaya Masa Kini. Arsip pertama adalah pengantar yang ditulis oleh Hendro Wiyanto selaku kurator pameran “Eksodus Barang”. Pameran yang diselenggarakan pada 2005 di Nadi Gallery ini memulai dengan pertanyaan reflektif tentang bagaimana mengidentifikasi sesuatu sebagai seni dan bukan seni.
Semenjak ‘70-an, aneka barang jadi (readymade) maupun objek temuan (found object) gencar memasuki lapangan penciptaan para perupa kita. Pendekatan readymade dan found object tentu menggarisbawahi pergeseran strategi berkarya dan perhatian para seniman. Filosofi medium di masa modern yang memilah objek fisik dan ihwal material diterobos. Seniman merespon objek-objek fisik dan ihwal yang material dengan kepekaan yang lebih, lebih dalam artian secara fungsi, hingga filosofis. Ini adalah filosofi medium di masa modern, ketika seniman bekerja “dengan” mediumnya, bertumpu “pada” alat-alatnya.
Cukup bertolak belakang dengan anggapan Adorno bahwa “The function of art is its lack of function”. Seni jelas tidak bersifat sehari-hari, sebab jika demikian dengan mudah kita akan melupakannya seperti hari ini melampaui dan meninggalkan yang kemarin. Salah satu paham yang kuat tentang seni adalah paham intensi. Namun kemudian kenyataan bahwa intensi semacam itu sebenarnya juga bisa datang dari luar (pengamat, kritikus, kurator, publik), atau institusi tertentu, menjadi keniscayaan. Setelah Duchamp memajang urinoir di ruang pamer, para seniman seakan justru menemukan intensinya melalui kehadiran dan susunan barang sehari-hari. Lantas pekerjaan utamanya adalah membaptis barang-barang itu sebagai “seni”. “Seni Merayakan Barang” menjadi judul dari esai pengantar pameran ini. Dari judul itu kita dapat berasumsi bahwa memang pada tahun-tahun tersebut, wacana seni rupa berkembang untuk kembali mempertanyakan dan melampaui jarak yang terbentang antara “seni” dan “bukan seni”.
Sekitar 11 tahun sebelum pameran “Eksodus Barang”, digelar pameran bertajuk “Seni Kriya dalam Budaya Masa Kini”. Dengan isu yang kurang lebih sama, kita bisa melacak bagaimana perkembangan diksinya. Memang, pada 1993-1994 belum dikenal frasa-frasa seperti found object atau readymade. Periode ini lebih mengenal istilah murni-terapan untuk membicarakan karya-karya semacam ini, yang praktiknya didominasi oleh karya seni kriya. Praktik ini juga berangkat dari kegelisahan atas gengsi seni kriya yang belum mendapat ekspos dan perhatian seramai seni rupa seperti lukis dan patung.
Tarikan atas persoalan ini memang cukup jauh dan panjang. Problem dari karya kriya adalah bahwa ia selalu dibicarakan sebagai seni yang diproduksi secara massal dalam waktu yang singkat. Ini menjadi asumsi dasar bahwa kualitas ekspresi benda pakai (terapan) akan selalu berada di bawah seni murni. Berawal dari usaha mendongkrak kualitas ekspresi dan apresiasi, pameran yang diprakarsai oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan ini diselenggarakan. Barangkali jika dilihat dari konteks masa kini, niat demikian dinilai pragmatis. Namun tentu saja ini tidak dapat dilepaskan dari jangkauan dan produksi pengetahuan wacana seni yang pada masa tersebut berbeda dengan jaman sekarang.
Melalui penelusuran atas arsip IVAA dengan beberapa kata kunci di atas, setidaknya kita dapat menandai beberapa asumsi. Pertama, pergeseran frasa seni tinggi-rendah, murni-terapan/ fungsional, bisa jadi disebabkan oleh kecenderungan bahwa segala hal di dunia memang mengalami komodifikasi, terlebih seni yang bermain dalam arena komoditas. Kedua, bersamaan dengan transaksi yang ikut beriringan dengan nilai-nilai ekonomis, entah disadari atau tidak, setiap pelaku dalam ekosistem seni membutuhkan bukan hanya pertukaran barang dan uang, namun juga wacana dan rujukan (reference). Harus diakui bahwa perbincangan atas tema ini bisa dijamah dari beragam perspektif. Arsip-arsip yang dimiliki IVAA atas tema ini bisa memperkaya sudut pandang sekaligus memperumit bahasan, karena wacana intelektual yang senantiasa dibangun akan selalu beriringan dengan kebutuhan-kebutuhan transaksional. Belum lagi gengsi institusional dan material-materialnya. Perkara seni rupa memang bisa jadi selalu berkutat dalam diskusi seputar wacana, komersial dan gengsi yang melekat.
Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2019.