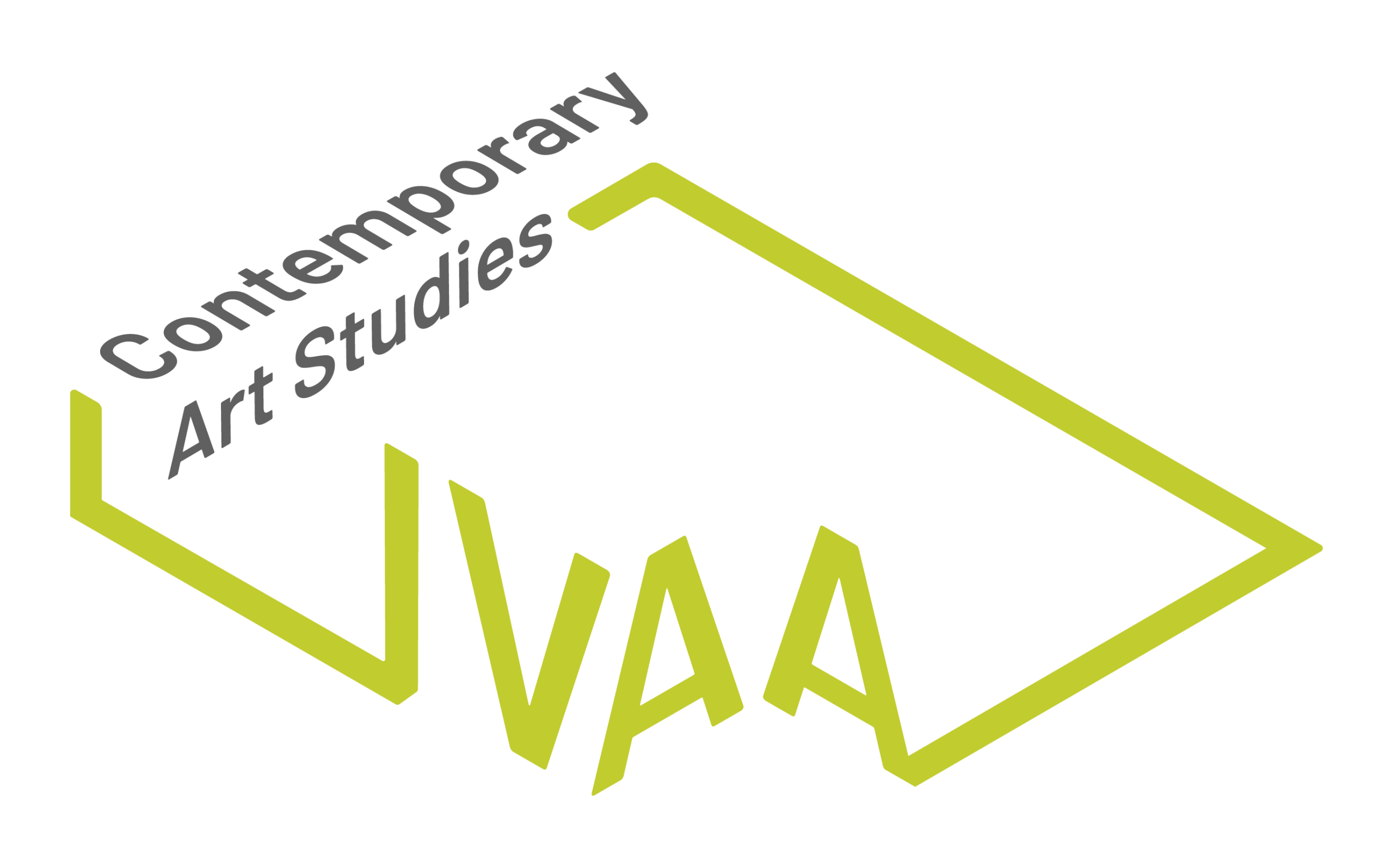Oleh Mega Nur Anggraeni Simanjuntak
Zaman bergerak, manusianya berarak mengorbit pada lini masa yang bisa jadi benar-benar baru. Perubahan menjadi mahar yang tertunaikan di setiap geliat zaman, menandakan bahwa kondisi sosial masyarakat begitu dinamis. Para penulis kemudian menjadi garda depan dalam proses pencatatan narasi sejarah dari satu generasi ke generasi berikutnya—yang objektivitasnya tentu saja dapat dipertanyakan kembali. Dan hari ini, belum terlambat kiranya untuk mengucapkan selamat datang di era digital, era di mana perkembangan teknologi informasi menawarkan ragam kemudahan dan fantasi sekaligus menimbulkan patologi sebagai konsekuensi.
Tersebutlah internet sebagai salah satu penemuan paling mutakhir abad 20. Kehadirannya di Indonesia awal 90-an, di mana Soeharto masih memegang tampuk kekuasaan, mampu menjadi jalan tikus untuk mengabarkan perlawanan. Sebab di internet, pengawasan yang dilakukan pemerintah sebelumnya melalui tayangan televisi, media cetak, atau radio, dirasa tidak terlalu ketat. Diskusi politik dilakukan melalui mailing list (milis), di mana hal tersebut kurang memungkinkan jika dilakukan melalui media arus utama atau bahkan digelar di ruang publik. Meski bukan satu-satunya jalan mengantarkan Soeharto pada senjakala kekuasaannya, internet—meminjam Geert Lovink—melalui jejaringnya tidak hanya mampu mengakhiri sejarah, melainkan memproduksi sesuatu sesuai jalur politiknya.[1]
Berkaca pada realitas hari ini, di mana internet menyaru sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi melalui ragam platform berjejaring yang tersedia, menarik kemudian menyoal kembali bentuk ‘perlawanan’ terhadap arus utama—baik secara langsung maupun tidak. Belum pudar di ingatan tentang munculnya idola-idola baru yang tenar melalui ragam platform tersebut. Di tahun 2016 misalnya, santer terdengar adagium “Youtube lebih dari Tv, boom!” yang dilontarkan para youtuber. Atau di Instagram, para idola ini lebih dikenal sebagai selebgram di mana jumlah pengikut (follower) mencapai puluhan ribu. Para mikro-seleb ini semacam memiliki jalan pintas untuk menjadi tenar tanpa melalui agensi—seperti yang dilakukan kebanyakan selebritas papan atas. Mengacu Lovink, kehadiran mikro-seleb ini menunjukkan perlawanan tersendiri yang diakomodir oleh jejaring dunia maya. Dalam artian, perlawanan tidak melulu mengenai menumbangkan orde, melainkan mencari jalan baru untuk mendapatkan posisi juga merupakan bentuk resistensi. Sebab, mereka mampu menghimpun massa dan menyebarkan pengaruhnya.
Lantas, apa hubungannya paparan demikian dengan seni rupa? Alih-alih sifat internet yang demokratis, di mana siapa pun dapat menjadi apa pun, pola tersebut di atas terjadi pula pada laku perupa muda hari ini. Melalui Instagram, platform berjejaring berbasis visual ini cukup digandrungi untuk mendistribusikan karyanya. Banyak bermunculan kemudian nama-nama yang cukup asing di medan sosial seni rupa Yogyakarta namun gemanya sudah sampai ke belahan lain dunia. Fenomena ini seakan menggoyahkan status quo medan seni rupa kurang lebih tiga dekade ke belakang. Lebih jauh, geliat perupa muda di jejaring Instagram seolah membongkar patronase yang terjadi. Katakanlah, berpameran di ruang-ruang berlabel ‘angker’ seperti Cemeti, Kedai Kebun Forum, diliput oleh Tempo, dan sebagainya, bukan lagi menjadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk ‘diakui’ sebagai seniman. Tentu saja, asumsi demikian perlu diteliti lebih dalam agar tidak menimbulkan kerancuan dan berhenti pada sinisme belaka atau simplifikasi terhadap fenomena. Lantas, bagaimana proses pentahbisan sebagai seorang seniman di Instagram? Menggunakan pendekatan milik Pierre Bourdieu, tulisan ini mencoba mendedah singgungan yang terjadi antara internet dengan medan seni rupa di Yogyakarta kaitannya dengan pentahbisan.
Penahbisan: Identitas dan Posisi
St. Sunardi dalam tulisannya bertajuk Strategi Identifikasi Lewat Seni memaparkan setidaknya ada empat macam identitas yang bisa dipakai sebagai pintu masuk untuk berbicara seni di Indonesia: identitas seniman (identitas yang muncul sebagai hasil negosiasi antara seniman dengan image tentang seniman dalam masyarakat), identitas politis (identitas yang muncul sebagai hasil tarik ulur antar seniman baik secara pribadi maupun kelompok dan kekuatan politik atau negara), identitas etnik atau kultural (identitas seni dalam menghadapi tradisi), dan identitas profesional (identitas seniman yang diciptakan oleh sistem pembagian kerja kapitalis).[2] Dalam artikel tersebut, ia lebih menjelaskan mengenai identitas seniman, di mana menurutnya identitas tersebut merupakan konsesi yang muncul di masyarakat berdasar laku hidup dan kecenderungan dari penampilan. Ia juga memberikan gambaran bahwa identitas seniman menyimpan paradoksnya sendiri: seniman sebagai Tuhan sekaligus pariah. Dalam artian, seniman dapat mengekspresikan daya serapnya terhadap dinamika masyarakat melalui bungkusan estetis. Namun, di sisi lain ia terasing dari masyarakat karena menjalankan nilainya sendiri yang kerap kali berbeda dari nilai-nilai umum.
Berpijak pada pemaparan St. Sunardi mengenai identitas melalui empat kategori tersebut, menarik kemudian untuk menjabarkan identitas profesional di era digital ini. Sementara itu, Agung Hujatnikajennong melalui Kurasi dan Kuasa: Kekuratoran dalam Medan Seni Rupa Kontemporer di Indonesia menyebutkan bahwa dekade 1990-an merupakan era penting bagi medan seni rupa kontemporer di Indonesia. Identitas kurator mulai marak digunakan; ia terpampang dalam setiap poster publikasi pameran dan sebagainya—di mana sebelumnya masih sangat jarang. Seiring perkembangannya, identitas tersebut menyaru sebagai profesi. Adalah globalisasi sebagai tegangan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam proses globalisasi, apa yang terjadi di medan seni rupa lokal selalu bertaut dengan yang terjadi di luar lokal, dan sebaliknya.[3] Ia juga tidak menampik kalau internet sebagai riak globalisasi, kemudian, memiliki sumbangsih terhadap medan seni rupa. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap seniman kaitannya dengan identitas profesional?
Menyitir Farah Wardhani dalam artikelnya di majalah seni rupa Visual Arts, infrastruktur seni mencakup pendidikan seni, praktik seni, kesempatan pameran, wacana kritis, sektor komersial—jual-beli, dukungan komunitas independen, dan dukungan sektor publik serta institusional.[4] Enam elemen ini secara tersurat menunjukkan jalan yang seyogianya ditempuh oleh seseorang untuk dapat ditahbiskan sebagai seniman. Berpameran di galeri seni, misalnya, menjadi salah satu pintu yang sebaiknya dijelajahi untuk menambah modal seniman. Sebab karya seni, meminjam Bourdieu, merupakan karya yang dianggap sebagai aset simbolis (dan bukan sebagai aset ekonomi, yang bisa jadi juga ada).[5] Selain itu, ketika sebuah karya mampu hadir di ruang-ruang yang sebelumnya telah dimistifikasi atau karya tersebut dibeli oleh kolektor ternama, secara otomatis akan menambah modal simbolik bagi si seniman. Proses demikian adalah kultur yang terus direproduksi untuk menginstitusionalisasikan seni. Lebih lanjut menurut Bourdieu, ikhwal tersebut merupakan doxa atau aturan main tidak tertulis yang direproduksi terus menerus kemudian diamini secara begitu saja oleh agen-agen di dalamnya. Aturan tersebut diproduksi oleh agen-agen yang menempati posisi tertentu. Sehingga, praktik yang terjadi merupakan hasil dari subjektivitas objektif individu terhadap lingkungannya. Bahwa ketika seseorang telah ditahbiskan atau mendapatkan legitimasi, dengan serta merta ia menduduki posisi tertentu dalam sebuah struktur—dalam hal ini medan seni rupa. Semakin dekat posisi agen dengan sumber kekuasaan atau legitimasi, semakin besar peluangnya untuk mengakumulasikan modal-modal yang dimilikinya.
Instagram: Jalan Tikus bagi Perupa Muda dari Arus Utama
Tersebutlah lema perupa muda yang kembali populer di beberapa poster pameran atau diskusi seni rupa sepuluh tahun belakangan. Demikian itu dapat ditemukan dalam beberapa gelaran seperti Pameran Perupa Muda (Paperu) yang diselenggarakan tahunan oleh Festival Kesenian Yogyakarta, Pameran Perupa Muda oleh Sangkring Art Space, atau sebuah acara bertajuk Young Artist Who’s Talking About Young Artist yang digagas Ace House Collective. Dari sekian definisi mengenai siapa itu perupa muda, menarasikan perupa muda masih sebatas usia. Sementara membaca pemuda merupakan ihwal yang rumit (tricky). Daripadanya, menggunakan pendekatan Karl Mannheim mengenai generasi untuk menarasikan siapa itu perupa muda berdasarkan generasi dapat menjadi jalan tengahnya.
Konsep mengenai generasi pertama kali digaungkan Mannheim, sosiolog asal Jerman, dalam esainya bertajuk The Problem of Generation pada 1923. Mannheim mengejawantahkan generasi sebagai sekumpulan individu-individu yang hidup dalam satu era serta mengalami kejadian bersejarah—di mana kejadian itu menjadi arus utama peradaban. Pula, ikhwal demikian mampu membentuk kesadaran umum hanya jika mereka yang hidup di era tersebut berusia muda, memiliki kesadaran sosial, dan terlibat di dalamnya. Sebagai penegasan, sebuah generasi terlahir tidak hanya semata-mata berdasarkan rentang tahun kehadirannya di bumi, melainkan terbentuk pula karena pengaruh sosio-historisnya. Selain itu, Mannheim menggarisbawahi terdapat konflik antar generasi yang bisa jadi sangat sublim dan menjadi faktor mengapa sebuah generasi baru terlahir.
Dalam sejarah seni rupa Indonesia, situasi sosial-politik kerap kali mempengaruhi dinamikanya, di mana kemudian mampu menjadi tonggak perubahan dalam setiap generasi. Hari ini, tonggak tersebut adalah pengaruh dari perkembangan teknologi. Pada sub-bab sebelumnya, telah dipaparkan mengenai masifnya penggunaan Instagram oleh kalangan muda menengah perkotaan sebagai bahasa visual atas kesehariannya. Sedang bagi perupa muda, Instagram mampu menjadi jalan tikus dari dominasi aturan main dalam medan seni rupa. Jika tujuan dari menggelar pameran adalah mempertemukan seniman dengan publik, maka hari ini ihwal demikian tidak terbatas pada ruang fisik. ‘Kebebasan’ dalam mengkurasi, menyematkan narasi, perjumpaan dengan sektor komersial, juga berinteraksi dengan publik, terfasilitasi di Instagram. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ryan Ady Putra (@ryanadyputra) dan Alberto Piliang (@albertopiliang), dua perupa muda berbasis di Yogyakarta yang namanya jarang muncul dalam peta medan seni rupa Yogyakarta namun sudah cukup dikenal publik yang tidak terbatas pada teritori.
Ryan Ady Putra sebenarnya sudah memulai geliatnya di seni rupa pada 2008 ketika ia berkuliah di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Ia pun pernah menjadi artisan salah satu seniman di Yogyakarta. Persinggungannya dengan generasi sebelumnya, memberikan kesadaran untuk memilih beredar di luar patron yakni melalui internet. Sebelumnya, ia menggunakan platform berjejaring lainnya seperti Facebook dan Tumblr, sedang pada 2013 ia secara intensif menggunakan Instagram. Karyanya banyak menyoal keseharian anak muda dengan kemasan “fun”. Kedekatannya dengan dunia skateboard, memberikan kemungkinan lain bagi karir kesenimanannya. Geliatnya mengunggah karya di Tumblr, membuahkan undangan baginya untuk berpameran di California dengan basis karya skate-graphic. Selain itu, konsistensinya mengunggah karya membuatnya menarik perhatian brand-brand kenamaan seperti Volcom dan Hurley, sehingga ia diminta untuk menjadi commission artist. Tidak hanya itu, ia pernah diliput oleh Juxtapoz Magazine online pada 2014 ketika berpameran “Permanent Vacation” di Deus Ex Machina, Bali. Bagai efek domino, tawaran lainnya mengalir dengan sendirinya. Terlebih, ketika ia membuat brand sendiri dengan nama: domestik.
Sedikit berbeda, Alberto Piliang baru menggunakan Instagram pada 2015. Sejak saat itu, ia dapat dikatakan sangat jarang berpameran di ruang-ruang fisik. Persinggungan dengan generasi sebelumnya memberikan kesadaran serupa dengan Ryan. Ia lebih sering menggunakan Instagram untuk mendistribusikan karyanya yang bergaya surealis dan kerap kali menyoal hiruk-pikuk eksistensi. Paling tidak, rata-rata ada empat karya terjual berupa drawing maupun digital print. Kedekatannya dengan musik alternatif, kerap mendatangkan tawaran baginya untuk membuat sampul album dari band-band tersebut atau menjadi commission artist pada majalah serupa.
Menariknya, kedua seniman muda ini dapat dikatakan tidak melewati ruang-ruang yang telah dimistifikasi di Yogyakarta: mereka memilih jalan tikus melalui Instagram. Di sana, laku yang dijalankan sebenarnya sama; untuk dikenali oleh publik di media sosial tersebut, menjadi sebuah keharusan untuk tekun mengunggah karyanya. Sebab dari situlah proses identifikasi oleh publik berlangsung.
Ada pun bentuk penahbisan yang terjadi, dapat dikategorikan ke dalam tiga babak, di mana proses legitimasi di internet menjadi bentuk yang cair. Babak pertama, dilakukan oleh diri seniman sendiri. Bentuk legitimasi seperti ini merupakan jalan keluar dari perdebatan identitas seniman di kalangan elit. Serta, difasilitasi pula oleh Instagram di mana setiap akun berhak memilih predikatnya sendiri dalam profil, tidak terkecuali predikat sebagai seniman. Babak kedua terletak pada infrastruktur seni yang mengalami pergeseran: ruang pamer bukan lagi galeri fisik, melainkan akun di Instagram; publik seni menjadi lebih luas, pasar bisa diciptakan di depan layar, wacana kritis menjadi pilihan—di mana caption merupakan narasi pendukung. Babak ketiga, merupakan penangguhan di luar agen-agen sebelumnya yakni media massa, baik alternatif maupun arus utama. Melalui media, setidaknya terdapat mata ketiga yang cukup objektif—terlepas dari kepentingannya—untuk memberitakan seniman kepada publik. Bentuk legitimasi ini biasanya dimulai dari lingkup-lingkup terdekat. Seperti misalnya, gaya surealis dan kegelapan Alberto Piliang diulas dalam majalah online yang juga dekat dengan isu-isu tersebut atau di kalangan skena musik alternatif. Sedangkan Ryan yang dekat dengan imaji-imaji skate-board dibungkus nuansa gembira, diberitakan dalam majalah online seperti Juxtapoz Magz.
Potret serupa itu sangat mungkin terjadi, mengingat arena merupakan ruang artikulasi kelindan habitus dan modal untuk memperebutkan legitimasi. Ketika agen tidak mendapatkan posisi tertentu atau mengalami dominasi oleh agen atau struktur di dalamnya, ia cenderung resisten terhadap struktur yang ada. Adalah rahasia umum ketika seniman muda tidak dengan mudahnya mendapatkan posisi dalam medan seni rupa. Maka dari itu, ketika para seniman muda ini memiliki kesadaran akan hal tersebut, mereka memilih untuk beredar di luar medan yang telah dilalui oleh generasi sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, laku yang dijalankan oleh seniman muda ini melalui internet mengantarkan mereka pada pemaknaan baru atas identitas seniman.
Sementara itu, identitas yang terkonstruksi kemudian merupakan ulang-alik antara identitas seniman dan identitas profesional. Ketika perjumpaan fisik digantikan oleh layar, maka laku identitas seniman menjadi kurang dapat terbaca. Dalam artian, karyanya berbicara, namun kepribadian si seniman bisa jadi tidak begitu tampak. Muncul kemudian penilaian berupa, “Dia bukan seniman, melainkan ilustrator”. Sebab, yang lebih tampak ialah identitas profesional, di mana seniman muda ini lebih banyak bergerak di sektor komersil. Ulang-alik karena kedua hal tersebut saling beririsan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa doxa dalam medan seni rupa Yogyakarta mulai mengalami pergeseran dengan adanya internet melalui ragam platform khususnya Instagram sebagai heterodoxa. Bentuk penahbisan yang terjadi setidaknya mengalami pergeseran, yakni perbedaan ruang dan bentuk legitimasi itu sendiri menjadi lebih cair di dunia maya. Terlebih, mengingat keduanya merupakan generasi yang tumbuh kembangnya diasuh oleh kemajuan zaman berupa teknologi, narasi besar akan kanonisasi atau mistifikasi ruang-ruang di Yogyakarta bisa jadi tidak lagi penting. Sebab mereka dapat mengakses apa pun dan berjejaring dengan siapa pun. Namun, bagaimana jadinya ketika usaha yang sedang dilakukan tersebut kemudian terputus jika platform-platform internet tersebut ditutup?
***
Kalimat “Bertukar Tangkap Dengan Lepas” merupakan penggalan puisi dari Amir Hamzah berjudul “Padamu Jua”. Juga pernah digunakan oleh Teater Garasi sebagai judul kumpulan esai 20 tahun Teater Garasi.
DAFTAR PUSTAKA
Becker, Howard Saul. 1982. Art Worlds. London: University of California Press.
Bourdieu, Pierre. 2010. Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Bourdieu, Pierre., Wacquant, Loic J. D. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press.
Grenfell, Michael. 2008. Pierre Bourdieu Key Concepts. Stocksfield: Acumen Publishing.
Hujatnikajennong, Agung. 2015. Kurasi dan Kuasa: Kekuratoran dalam Medan Seni Rupa Kontemporer di Indonesia. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Lovink, Geert. 2005. The Principle of Notworking: Concepts in Critical Internet Culture. Hogeschool van Amsterdam: HVA Publiciaties.
Palfrey, John., Grasser, Urs.. 2008. Born Digital: Understanding The First Generation of Digital Natives. New York: Basic Book.
Majalah Seni Rupa Visual Art Vol. 4, No. 24, April-Mei 2008
Vincent, Alice. 2014. How Has The Internet Changed Art terarsip dalam http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/11130492/How-has-the-internet-changed-art.html diakses pada 18 Januari 2018
http://ucca.org.cn/wp-content/uploads/2014/07/PAI_booklet_en.pdf diakses pada 18 Januari 2018
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/11130492/How-has-the-internet-changed-art.html diakses pada 18 Januari 2018
[1] Dr. Geert Lovink. 2005. The Principle of Notworking: Concepts in Critical Internet Culture. Hogeschool van Amsterdam: HVA Publiciaties. Hal. 9
[2]St. Sunardi. ‘Strategi Identifikasi Lewat Seni’ dalam ‘Sorak-Sorai Identitas’. Hlm 66
[3] Agung Hujatnikajennong. 2015. Kurasi dan Kuasa: Kekuratoran dalam Medan Seni Rupa Kontemporer di Indonesia. Tangerang Selatan: Marjin Kiri. (Hlm. 4)
[4] Farah Wardani. Urgently Needed: Art Managers: Ketika Seni Rupa Jadi Industri terarsip dalam majalah seni rupa Visual Art Vol. 4, No. 24, April-Mei 2008. Hlm. 66
[5] Pierre Bourdieu. 2010. Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hlm. 166
Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2019.