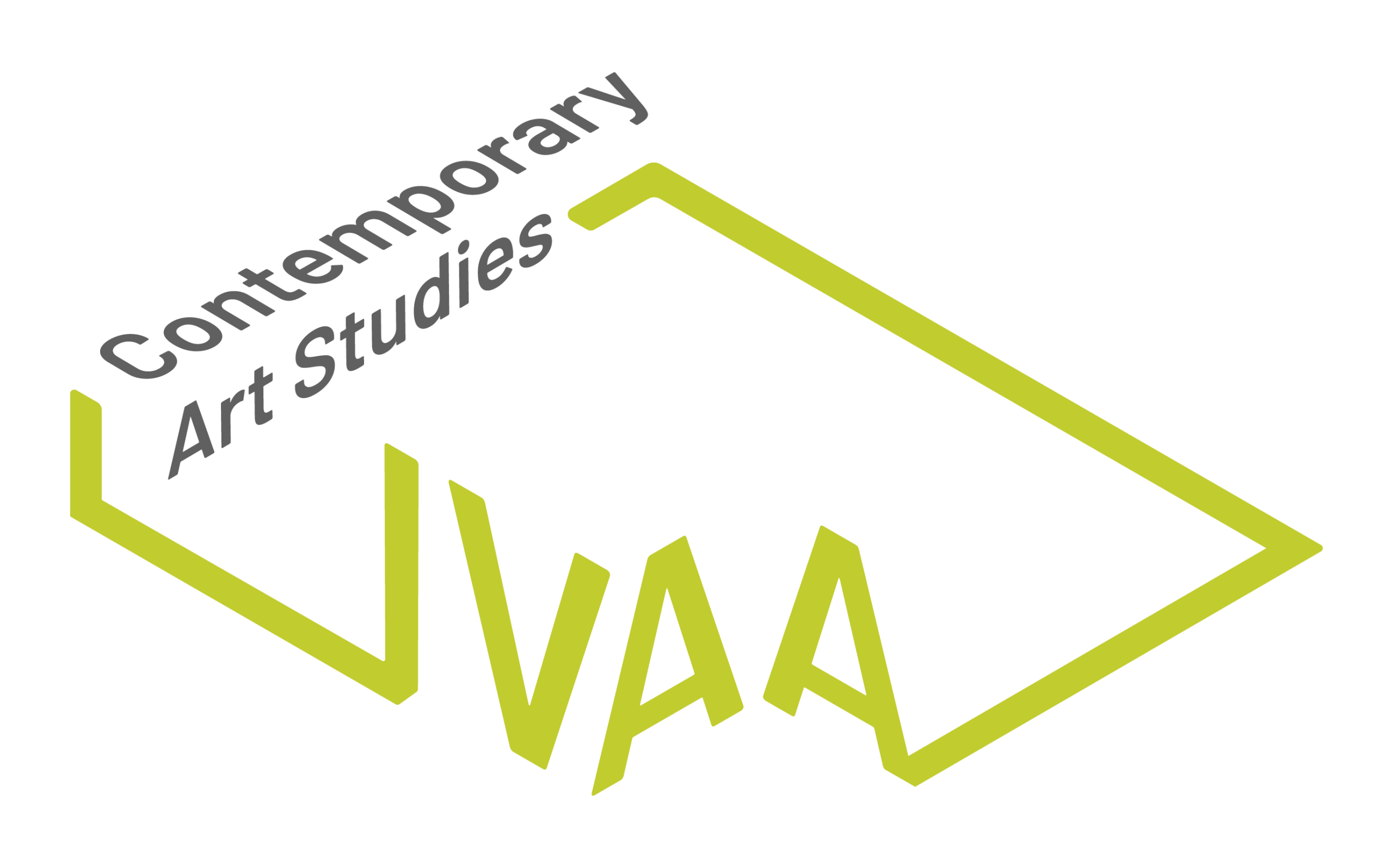Judul Buku: Arts Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi
Judul Buku: Arts Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi
Penulis : Joost Smiers, Umi Haryati (penerjemah), Fitri Indra Harjanti (penyunting)
No. Panggil : 701 Smi a
ISBN/ISSN : 979-98499-97-0
Bahasa : Indonesia
Penerbit : Insist Press
Tahun Terbit : 2009
Tempat Terbit : Yogyakarta
Resensi oleh Hardiwan Prayoga
Arts Under Pressure, memiliki total 12 BAB yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu pertama “Ekspresi Artistik Dalam Dunia Korporasi”, dan kedua “Kebebasan dan Perlindungan”. Bagian 1 terdiri dari BAB I: “Seni dan Dunia”, BAB II: “Kuasa Untuk Memutuskan”, BAB III: “Orisinalitas yang Meragukan, BAB IV: Kehidupan Artistik Lokal”, dan BAB V: “Budaya yang Digerakkan Korporasi”. Sedangkan Bagian 2 memiliki BAB VI dengan judul “Menyeimbangkan Perdagangan dengan Budaya”, BAB VII: “Regulasi Mendukung Keanekaragaman Budaya”, BAB VIII: “Kebijakan-Kebijakan Budaya”, BAB IX: “Membayangkan Dunia Tanpa Hak Cipta”, BAB X: “Warisan Kebudayaan Kita”, dan BAB XI: “Kebebasan Berpendapat Versus Tanggung Jawab”. Buku ini ditutup dengan BAB yang berjudul “Semua yang Berharga Tidak Mampu Bertahan”.
Buku ini dimulai dengan pernyataan bahwa seni merupakan arena pergulatan batin, konflik-konflik sosial, dan persoalan-persoalan status di dalam diri manusia, yang saling tarik menarik secara lebih padat dibandingkan ranah komunikasi sehari-hari. Lebih lanjut, Joost Smiers mengaitkan seni sebagai medan tempur simbolik, ekonomi, dan demokrasi kebudayaan. Medan tempur simbolik dicontohkannya dengan situasi Taliban di Afganistan, dan Idi Amin di Uganda yang merusak alat-alat musik tradisional karena dianggap tidak Islami. Kondisi ini berkelindan bersamaan dengan persepsi orang atas kebebasan, atau pandangan demokratis atas kebudayaan. Selalu terjadi friksi antara kebebasan dalam koridor nilai artistik, dengan nilai kolektif. Wali kota New York pada 1999, Rudolfo Giuliani, pernah mengancam untuk menarik subsidi kota pada Museum Seni Brooklyn karena memamerkan lukisan Bunda Maria yang payudaranya dihiasi dengan apa yang secara halus digambarkan sebagai kotoran gajah. Kasus lain ketika penyanyi dan penulis lagu kenamaan asal Lebanon yang terkenal di jazirah Arab, Marcel Khalife, didakwa melakukan kejahatan terhadap agama Islam karena musikalisasi puisinya ditutup dengan satu ayat Al-Qur’an, meski akhirnya majelis hakim memvonis Marcel Khalife tidak bersalah.
Satu yang perlu dicatat, bahwa konflik demikian akan terus bermunculan dalam seni, meski bisa dibilang hanya meledak sesekali saja. Ini sedikit banyak menggambarkan kenapa orang menggandrungi bentuk dan narasi kesenian yang berbeda-beda, berjalan dengan jalurnya sendiri. Bahwa bentuk karya macam apa yang dikesankan lebih “tinggi” adalah perkara relasi kuasa.
Kasus yang dicontohkan Smiers dalam buku ini salah satunya adalah pertentangan pendapat soal Cannes Film Festival 1999. Kritikus film-film Hollywood menyebut film yang beredar dalam festival ini seolah berfungsi sebagai pujian berlebihan terhadap omong kosong, tidak relasional dengan kehidupan nyata, dan gagasan estetik yang hanya cinema-verite yang dipahami segelintir orang. Fenomena ini barangkali masih terlihat hingga kini. Seperti ada dua kutub yang berbeda dalam semesta perfilman, dengan gengsi dan atensi yang sama-sama tinggi.
Meletakkan kata kunci relasi kuasa dalam kesenian, sekaligus akan menampilkan wajah permasalahan hubungan kompleks antara seni, komoditas, dan cita rasa. Konteks makro dari fenomena ini adalah globalisasi, di mana dunia dirancang sebagai satu jahitan tanpa putus dan batas. Lebih jauh, globalisasi ekonomi neoliberal mengesampingkan nilai-nilai “lokal” dengan menundukkan dan mendisiplinkan melalui korporasi-korporasi internasional yang kokoh, atau diistilahkan sebagai konglomerasi.
Secara spesifik, pada ranah pasar seni visual, seniman kini menjadi pekerja upahan yang tidak memiliki akses langsung pada milyaran pembeli/ konsumen. Situasi ini juga berhadapan dengan kenyataan bahwa penaksiran atas nilai-nilai komersial karya seni sulit menemukan indikator-indikator yang pasti. Kemudian lahirlah ilusi-ilusi orisinalitas dari situasi demikian, di mana karakter dan ciri khusus adalah citra yang ingin ditonjolkan dalam pasar yang sebenarnya monopolistik dan terstruktur. Pasar yang monopolistik ini sekaligus mengkonsentrasikan perputaran kapital pada segelintir seniman saja. Meski seniman tetap pihak yang dianggap paling memahami seni, aktor-aktor dalam pasar inilah yang paling memiliki kendali atas pengetahuan dan akses informasi terhadap karya seni tertentu. Mereka memiliki kapasitas untuk menetapkan harga melalui “aura” yang disematkan pada reputasi seniman hingga melihat tren isu yang beredar di masyarakat. Persaingan pemain-pemain arus utama inilah, yang oleh Smiers sebut seni menjadi medan tempur ekonomi.
Pada BAB 2, Smiers membedakan skema kerja konglomerasi pasar seni visual dengan film, sastra, dan musik. Wilayah seni visual mempermainkan harga layaknya pasar saham, yang bisa sekonyong-konyong menetapkan nilai berharga atau tidak berharganya suatu karya. Pada ranah film, konglomerasi terlihat dari layar bioskop di Indonesia yang dimonopoli oleh jaringan XXI. Secara perlahan kehadirannya menyingkirkan jaringan bioskop-bioskop lokal. Meski belakangan telah muncul jaringan baru seperti CGV, Cinemaxx, atau Platinum Cineplex, jumlah perbandingan layar yang dimiliki tetap belum seimbang. Terlebih jika dilihat dari seragamnya jenis film yang beredar. Ini memperkuat argumen bahwa pasar yang monopolistik hanya mengedarkan seniman dan karya seni yang seragam. Konstruksi kerja industri yang mendisiplinkan standar-standar karya seni dalam satu muara, yaitu pasar, menjadi sebab dari fenomena tersebut.
Buku dengan terbitan Bahasa Indonesia tahun 2009 ini meletakkan persinggungan seni dengan berbagai studi kasus. Smiers menyandingkan pembacaan atas seni dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi, imperialisme, hingga pembangunan infrastruktur yang dirancang dalam logika korporasi kebudayaan. Buku ini diakhiri dengan rekomendasi dari Smiers soal perkara tersebut. Dalam judul BAB penutup yang terdengar pesimistis, “Semua Yang Berharga Tidak Mampu Bertahan”, Smiers menegaskan lagi garis-garis pertahanan yang harus dibangun dari gempuran neoliberalisme demi keanekaragaman budaya.
Upaya menuju ke sana bukannya tidak pernah dilakukan. Pada 1970 hingga awal 1980 negara-negara non-barat pernah mendesak UNESCO untuk membuat NWICO (New World Information and Communication Order). Juga, muncul desakan untuk membuat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menuntut terbukanya akses komunikasi bagi sebanyak mungkin ekspresi artistik dan partisipasi yang lebih luas dari komunitas-komunitas kebudayaan. Smiers secara tegas menyatakan bahwa gagasan semacam ini tidak disukai negara barat, khususnya segelintir CEO konglomerasi budaya.
Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, pada Oktober 2005, UNESCO menyetujui Konvensi tentang Perlindungan dan Pengenbangan Keanekaragaman Ekspresi Budaya. Konvensi atas keanekaragaman ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah, karena tidak ada jaminan bahwa pemerintah bebas pengaruh kekuatan pasar global. Harus ada gerakan-gerakan strategis mulai dari ranah teori hingga praktis dengan satu prinsip, yaitu keanekaragaman dan demokrasi kebudayaan yang perlu dipertahankan.
Diakui, bahwa ini adalah kondisi yang abstrak, tidak seperti persoalan lingkungan yang akan terdeteksi ketika udara mulai tercemar, makanan kehilangan rasa alaminya, pohon-pohon mulai tandus dan tumbang, dan lain-lain. Kebudayaan, sebagaimana ranah lingkungan, sama-sama memiliki dampak jangka panjang. Kondisi di mana kita menghadapi permasalahan global yang berkonsekuensi lokal, Smiers merekomendasikan bahwa harus ada sebuah gerakan global, misal sebuah lembaga non pemerintah yang berkoordinasi secara global. Tugas pokoknya adalah memantau kebijakan dan langkah UNESCO beserta negara-negara Eropa, Jepang, Rusia, dunia Arab, Amerika, dan Amerika Latin yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya.
Sistem hak cipta yang sekarang telah menjadi alat untuk mempertahankan kuasa konglomerasi budaya arus utama yang dampaknya mengekang keanekaragaman budaya dapat menjadi kesadaran pertama yang harus dimiliki dan disikapi. Kedua adalah mengidentifikasi aktor-aktor potensial pendukung keanekaragaman budaya. Smiers berpendapat bahwa aktor-aktor ini adalah mereka yang dapat meyakinkan tetangga, teman, rekan sejawat, bahwa keanekaragaman budaya menjanjikan kesenangan dan kepuasan yang lebih besar ketimbang pilihan seragam yang selama ini sudah dinikmati. Ketiga, dengan meyakini seni sebagai salah satu alat komunikasi yang spesifik, regulasi yang dibuat pemerintah perlu menjamin semua orang untuk dapat mengakses perangkat komunikasi dan berpartisipasi sebagai bagian dari kebudayaan yang demokratis. Keempat, merumuskan sendiri regulasi yang menjamin perlindungan dan perkembangan keanekaragaman budaya. Regulasi yang memastikan bahwa tidak ada pilihan preferensi kebudayaan yang direnggut. Kelima, setelah langkah-langkah identifikasi dan membangun argumen, tugas berikutnya adalah membuat keputusan strategis dengan menentukan target utama. Smiers dalam tulisannya masih meyakini bahwa pemerintah nasional dan pejabat publik menjadi kunci menuju pasar kebudayaan. Lebih luas, UNESCO hingga WTO didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan pada pasar monopolistik yang tidak mengakomodir keanekaragaman budaya. Argumen ini bisa diperdebatkan, mengingat sekarang akses teknologi dan informasi berada dalam genggaman perangkat personal. Dalam kenyataan ini, apakah sekarang pemerintah melalui regulasinya bertugas untuk mengatur atau melindungi? Keenam adalah memetakan hambatan dan peluang dalam memenuhi tugas-tugas sebelumnya. Ketujuh adalah membangun koalisi; pelibatan massa untuk secara kritis membicarakan keanekaragaman budaya, ekspresi dan hak asasi manusia, relasi ekonomi dengan budaya, hingga kaitannya dengan kekuasaan industri global. Kedelapan, adalah untuk menjangkau, kampanye, dengan fungsi menyita perhatian publik atas isu-isu keanekaragaman budaya. Tugas kesembilan dan sepuluh adalah memantau, mendidik, dan melatih pada tataran teoritis hingga praktis.
Kesimpulan dan sepuluh rekomendasi yang diberikan Smiers bisa seolah hanya terdengar seperti retorika belaka. Atau bisa jadi, seluruh langkah-langkah ini sudah dilakukan namun masih belum dapat diukur dampak konkritnya bagi demokratisasi kebudayaan. Jika gagasan ini didaratkan pada konteks di Indonesia, belakangan kita kerap mendengar revolusi industri 4.0 yang menggantikan frasa globalisasi. Biasanya frasa ini berjalan seiring dengan glorifikasi atas pembangunan infrastruktur. Tarikan dalam konteks ini bisa merangsang pertanyaan dan pandangan lain tentang kesenian.
Buku ini bisa menjadi awalan untuk membuka peta mengenai di mana posisi kesenian di hadapan wacana-wacana aktual. Terutama dalam melihat banyaknya proyek infrastruktur di sekitar kita. Apakah rekomendasi Smiers pada akhir tulisan cukup mencerahkan untuk menumbuhkan harapan? Atau masih mungkinkah dalam skema ini ada versi lain dari seni yang bebas dari tekanan dan mengakomodir keanekaragaman ekspresi?
Artikel ini merupakan rubrik Review by Staff dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2019.