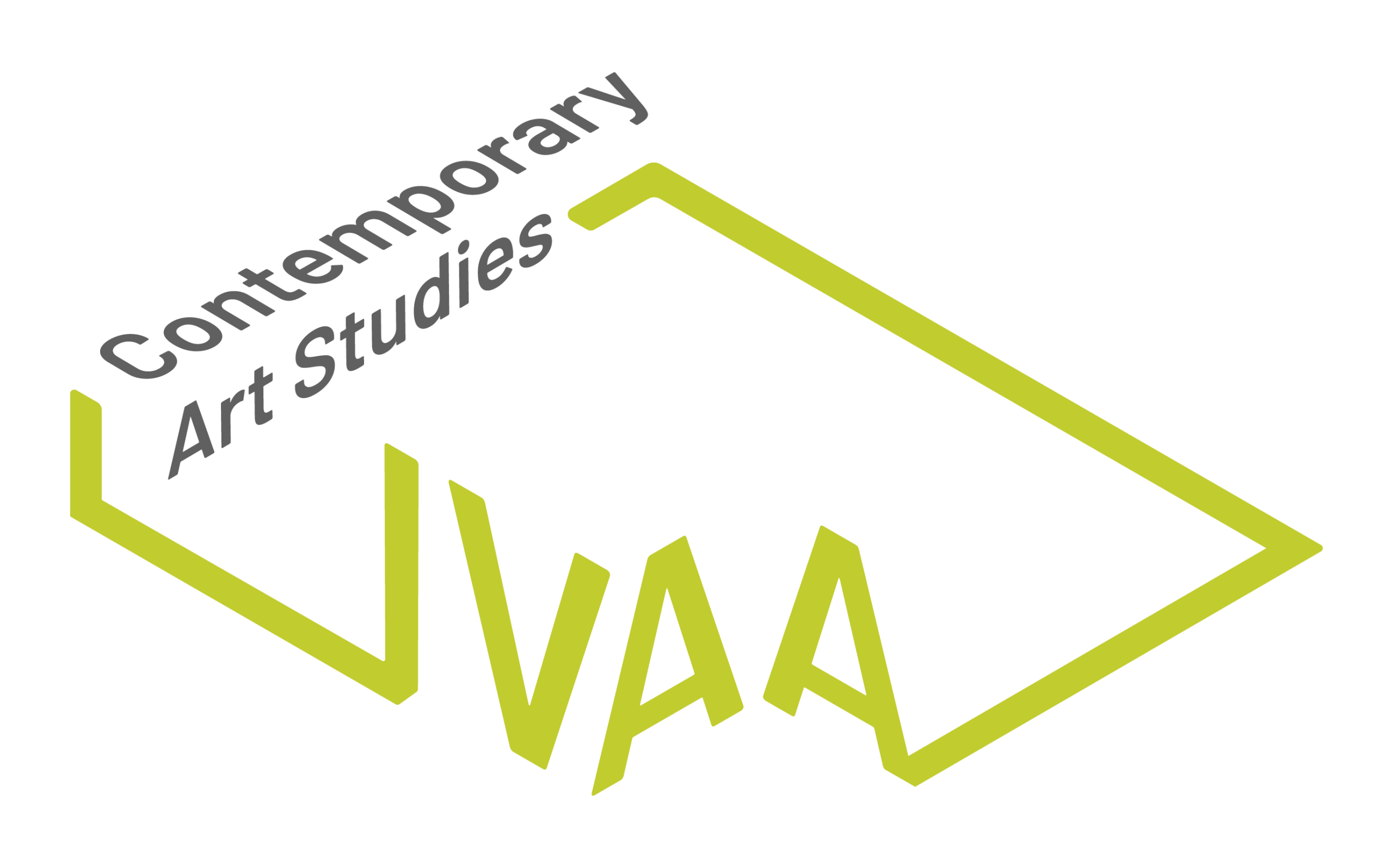oleh Krisnawan Wisnu Adi
Pada suatu pagi, ada seorang anak yang ikut pembantunya pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Anak ini adalah putra dari seorang wanita Kanada dan pria Jawa. Sewaktu di pasar, anak itu melihat balon dan seketika menginginkannya. Tentu saja waktu itu harga balon tidaklah murah, tapi toh sebenarnya keluarga ini tergolong mampu untuk membelinya. Namun, karena sudah menjadi aturan dari si ibu bahwa si pembantu hanya boleh membeli barang sesuai daftar belanjaan, tak sampailah keinginan anak itu.
Ketika di sanggar, Pak Guru memberi tugas untuk menggambar dengan tema “Keramaian di Pasar”. Bukan gambar orang berjualan, keranjang rotan berisi sayur-mayur, dan pernak-pernik lain seperti yang kita maklumi, anak itu justru menggambar sebuah telur. Ibunya, karena mungkin terlalu rasional, marah kepada si anak karena hasil gambarnya yang demikian. Tetapi setelah ditanyai Pak Guru, barulah anak itu menceritakan alasannya. Karena tadi pagi tidak bisa memperoleh balon, ia mengamuk dan membanting dagangan telur di depannya. Semua telur pecah, dan terjadilah keramaian di pasar.
———-
Cerita di atas bukanlah cerita fiktif. Itu merupakan salah satu kisah yang dialami oleh Hadjar Pamadhi ketika bergelut sebagai guru di Sanggar Karta Pustaka pada 1974. Dan tentu saja, anak yang mengamuk itu adalah salah satu muridnya. Sebuah memori yang menjadi pembuka untuk ulasan singkat seputar sanggar lukis anak di Yogyakarta, yang berjalan beriringan bersama gesekan antara pendidikan, komersialitas, dan perkembangan jaman.
Sanggar lukis anak, atau secara umum sanggar seni anak, mungkin terdengar kurang seksi untuk dibicarakan. Entah karena para agen diskursus kesenian kita yang terlalu menganggap diri dewasa, persaingan menjadi aktor seni kontemporer yang unggul, atau polarisasi social clique untuk akumulasi modal sosial, saya tidak tahu. Tetapi praktik seni anak tetap berjalan. Eko Nugroho Art Class, sanggar menggambar Taman Tino Sidin, Jembatan Edukasi Siluk, pameran lukisan anak Jogja-Kyoto, pelajaran kesenian di bangku sekolah, hingga praktik mencoret-coret dinding rumah masih eksis. Oleh karena itu persoalan seni dan anak sebenarnya akan selalu menjadi bagian penting dalam diskursus kesenian, bahkan kehidupan pribadi maupun sosial. Mereka pulalah yang akan melanjutkan dinamika kesenian esok hari.
Untuk sedikit mengorek persoalan seni dan anak, khususnya dalam hal Pendidikan Seni, tim redaksi IVAA berbincang dengan Hadjar Pamadhi, seorang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai aktor yang ikut memulai dinamika sanggar sejak 1974, beliau menyimpan banyak memori dan persoalan Pendidikan Seni anak, khususnya di Yogyakarta, yang belum tuntas hingga sekarang.
Konsep Pendidikan Seni Kita yang Itu-itu Saja
“Pendidikan Seni di Indonesia itu renaisans pada tahun 1975. Sebelumnya apakah kita punya Pendidikan Seni? Secara informal ada, …. dilaksanakan namun tidak terkonsep dalam Pendidikan Seni seluruh dunia. … yaitu ketika Ki Hadjar Dewantara memulai konsep Pendidikan Seni namun di dalam pelaksanaannya Pendidikan Seni itu terpisah. Bunyinya adalah menggambar, menyanyi, dan menari. Itu 1975 ke bawah. Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa terlalu kuat pada waktu itu lalu menggunakan istilah itu. Namun itu tidak terkait dengan Pendidikan Seni secara internasional”, ungkap Hadjar Pamadhi.
Pendidikan Seni sebenarnya sudah ada sejak sebelum 1975, yakni ketika Ki Hadjar Dewantara bersama Taman Siswa merumuskan pendidikan seni yang dibagi ke dalam tiga bentuk: menggambar, menyanyi, dan menari. Mungkin rumusan tersebut relevan pada masa itu. Namun, menjadi masalah ketika tidak ada kontekstualisasi seiring jaman yang terus berubah. Bagi Hadjar Pamadhi ini adalah awal masalah Pendidikan Seni di Indonesia.
Kita bisa melihat bentuk pelajaran kesenian di bangku sekolah yang masih terkategorikan ke dalam tiga bentuk itu. Kalau tidak menggambar, menganyam, menyanyi, ya bermain alat musik. Posisi pelajaran kesenian pun seolah menjadi pelajaran yang dianaktirikan, tidak sepenting Matematika, IPA, IPS, atau pelajaran yang sering dijadikan subjek bimbingan belajar. Belum lagi kualitas tenaga pengajar yang barangkali hanya mengutamakan kemampuan teknis dari pada pemahaman psikologis, sosiologis, serta filosofis tentang hubungan antara seni dan pola pikir anak.
Pendidikan Seni sebenarnya bukan hanya terpatok pada tiga bentuk di atas. Bentuk seni, seperti menggambar, menyanyi, dan menari, sebenarnya hanya sebagai media ekspresi yang seharusnya dikontekstualisasi terus-menerus. Perubahan situasi telah melahirkan ragam bentuk seni lain seperti drama, film, bahkan artificial intelligence yang seharusnya diakomodasi dalam konsep Pendidikan Seni kita. Hal yang seharusnya menjadi pokok perhatian adalah ungkapan perasaan estetis seperti apa yang dimunculkan oleh anak.
Sanggar yang Sempat Menjamur dan Akhirnya Jenuh
Situasi Pendidikan Seni yang bermasalah pada waktu itu akhirnya melahirkan ide perubahan atau kontekstualisasi konsep Pendidikan Seni yang mengikuti perkembangan internasional dari orang-orang seperti Hadjar Pamadhi, Soedarso SP, dan Soeharjo dari Malang. Namun, orang-orang dari IKIP malah menolak gagasan perubahan tersebut. Orang-orang di luar IKIP seperti Arya Sucitra dan Yuswantoro Adi justru memberi dukungan lebih lanjut.
Selanjutnya, pada 1974, Hadjar bersama yang lain bekerja sama dengan perpustakaan milik Belanda, Karta Pustaka, mendirikan sebuah sanggar sebagai bentuk alternatif dari Pendidikan Seni di jalur formal. Sanggar itu bernama Sanggar Karta Pustaka atau Sanggar Seni Rupa Karta Pustaka. Dorongan dari 10 IKIP se-Indonesia untuk meminta IKIP Yogyakarta memberi contoh menjadi faktor penguat mengapa mereka mendirikan Sanggar Karta Pustaka.
“Ketika konsep Pendidikan Seni itu tidak dilaksanakan, lalu kami menggunakan Karta Pustaka sebagai konsep Pendidikan Seni. Bahwa seni ini untuk mendidik anak. Education through art. Jadi kita mendidik anak lewat seni. Apa yang kita didik? Kreativitas, sensitivitas, skill”, ungkap Hadjar Pamadhi.
Kebanyakan murid yang ada di sanggar adalah anak orang asing, anak dosen, dan anak juragan di Malioboro. Guru pertama saat itu adalah Hadjar Pamadhi dan almarhum Gudaryono. Gudaryono merupakan dosen ISI B5, semacam jurusan guru seni. Kursus menggambar hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Praktik pengajarannya didasarkan atas dua buku mengenai pendidikan seni, yakni “Creative and Mental Growth” karangan Viktor Lowenfeld dan W. Lambert Brittain dan “Education through Art” karangan Herbert Read.
Fungsi Sanggar Karta Pustaka pada waktu itu adalah untuk merespon suasana kaku dari perpustakaan Karta Pustaka yang dikelola dengan cara Belanda. Jadi ketika anak-anak bosan membaca buku, sanggar menjadi ruang yang menyenangkan bagi mereka untuk melepas kejenuhan dengan menggambar. Tidak jarang pula anak-anak diajak untuk berpameran keliling. Pada 1980-an, bersama Karta Pustaka, lukisan-lukisan para murid dikirimkan untuk mengikuti kontes sanggar di India, lalu Brazil, dan Kyoto. Di Kyoto, Sanggar Karta Pustaka memenangkan kontes tersebut. Sampai sekarang, hubungan dengan Kyoto melalui lukisan anak masih berlangsung.
Bentuk Pendidikan Seni informal semacam itu akhirnya membuat beberapa orang tertarik untuk menginisiasi sanggar baru. Salah satunya adalah Sanggar Melati Suci (SMS) yang didirikan oleh Hari Santosa. Berbeda dengan Sanggar Karta Pustaka, SMS banyak mengadakan lomba dan menerapkan unsur manajemen bisnis dengan terlalu kuat. Muncul juga praktik Pendidikan Seni dari Tino Sidin pada 1976-1977. Namun, menurut Hadjar Pamadhi apa yang diajarkan Tino Sidin terlalu terpatok pada model pengajaran seni untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang mana itu tidak sesuai untuk perkembangan anak. Ada lagi sanggar lain seperti BPLSAR milik Kantor Kebudayaan Provinsi dan Narwastu. Setelah masalah konsep Pendidikan Seni yang tidak kontekstual, bagi Hadjar Pamadhi muncul lagi dua masalah justru setelah keberadaan sanggar yang menjamur: komersialitas dan penyeragaman (titik ekstremnya adalah dogmatisme).
Setelah 1980-an sanggar-sanggar mulai memasuki masa kejenuhan, karena gambar yang monoton dan penekanan elemen komersialitas yang terlalu kuat. Satu hal yang luput dari para pengajar dan juri seni anak adalah bahwa anak memiliki apersepsi dalam berkesenian:
“Seni rupa itu adalah bahasa kedua anak. Kalau anak-anak tidak bisa bicara, lalu digambarkan. … Anak-anak itu menggambar bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia ketahui. Anak-anak itu punya apersepsi. Seorang guru harus bisa menumbuhkan apersepsi anak dalam artian yang kontekstual. …. Anak-anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil.”
Lalu, mau Bagaimana?
Sudah bukan jamannya lagi untuk membagi kesenian ke dalam beberapa bentuk. Dengan tajuk ‘kontemporer’, batasan-batasan aliran dan medium telah hilang. Semua menjadi campur, total art atau integrated art. Paradigma substansial agaknya menjadi cukup relevan untuk berjalan bersama kesenian dalam konteks masyarakat urban saat ini. Juga tentu saja, situasi semacam itu turut mempengaruhi dinamika Pendidikan Seni.
Hadjar Pamadhi melalui disertasinya telah mengkaji dimensi estetik seni rupa publik di Yogyakarta dalam relevansinya bagi pengembangan pendidikan seni di Indonesia. Salah satu temuannya adalah bahwa ruang publik adalah persoalan kesempatan (the opportunity of space). Jarak untuk penikmat menikmati karya adalah ruang publik yang bersifat imajiner. Subjek seni bukan lagi terletak pada objek melainkan pada orang; keindahan karya ditentukan oleh subjek manusia. Maka, seniman (atau pengajar seni anak) yang hebat adalah seniman yang mampu memberi kesempatan bagi publik untuk melakukan proses dialog.
Begitu juga dengan Pendidikan Seni. Bukan mediumnya yang terpenting, tetapi kesempatan dialog yang mampu dihadirkan untuk anak melalui ekspresi estetisnya. Tidak hanya menggambar, menyanyi, dan menari, tetapi STEM (science, technology, engineering, mathematic) telah menjadi tuntutan jaman yang harus diakomodasi dalam Pendidikan Seni kita, jika memang mau mengikuti arus urban beserta nilai kosmopolitanisme yang ada di dalamnya.
Dengan demikian, menggambar (atau bentuk seni lainnya) bukan menjadi tujuan dari Pendidikan Seni, melainkan dialog dalam rangka mengolah kreativitas untuk kehidupan yang terus berubah.
———-
Anak dari wanita Kanada dan pria Jawa itu kembali mendapat tugas menggambar di sanggarnya. Temanya adalah “Ibuku yang Cantik”. Anak ini tidak menggambar ibunya. Ia justru menggambar pembantunya yang memakai jarik dan membawa sapu. Setelah ditanya Pak Guru mengapa ia menggambar pembantunya, anak itu menjelaskan bahwa ibunya selalu marah kepadanya dan memukulnya dengan sapu. Ibu pasti akan marah kalau digambar. Jadi, ia menggambar pembantunya saja.
Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Mei-Juni 2019.