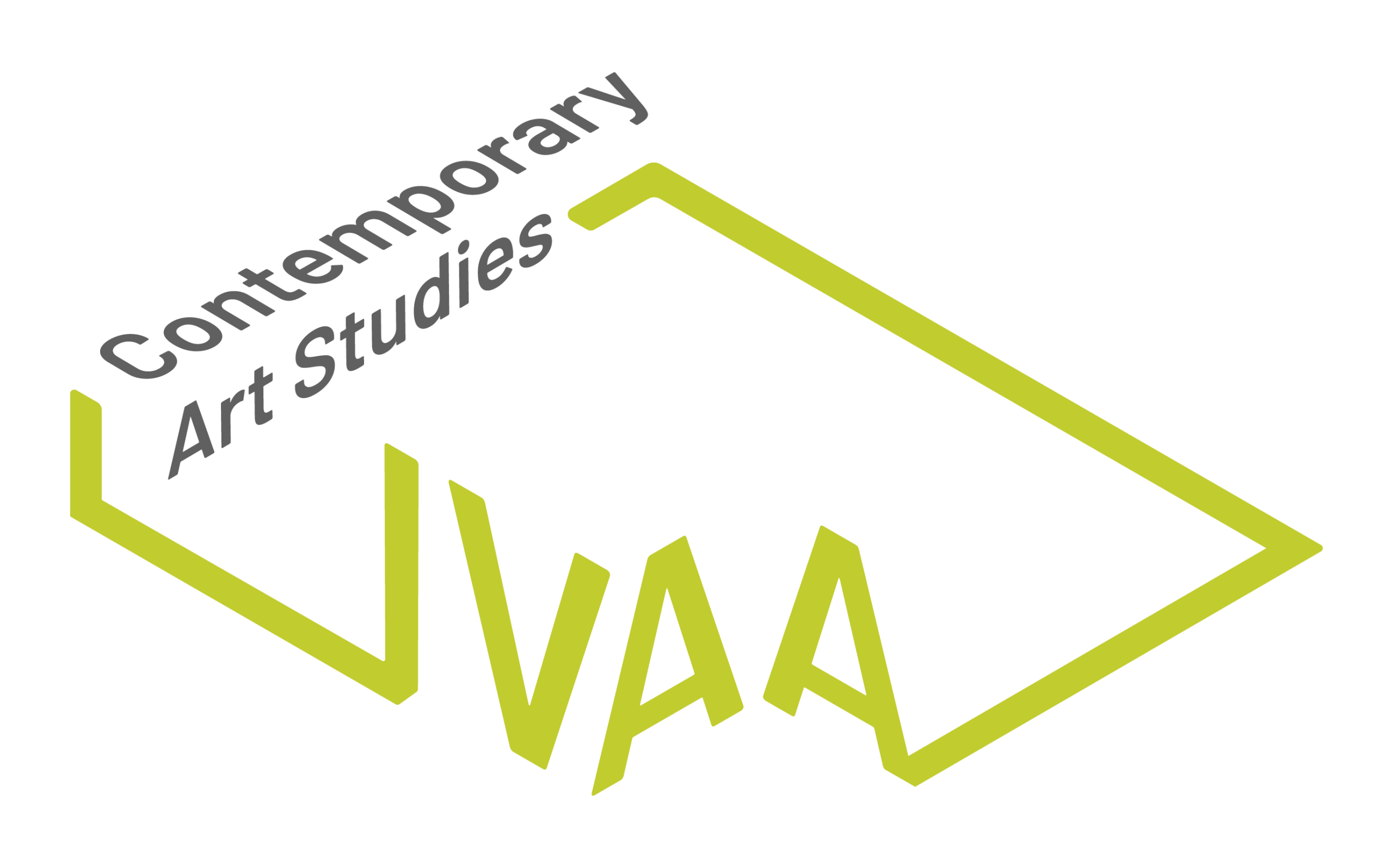Oleh Krisnawan Wisnu Adi
….. “surealisme etnografis” adalah gagasan utopis, sebuah pernyataan tentang kemungkinan masa lalu dan sekaligus kemungkinan masa depan untuk analisis budaya.
(James Clifford dalam On Ethnographic Surrealism, 1981: 540)
Ketika saya membaca arsip IVAA mengenai Ivan Sagita, entah itu dari liputan media massa, catatan kuratorial, dan buku, surealisme menjadi atribut yang paling banyak dilekatkan pada seniman asal Lawang, Jawa Timur ini. Dwi Marianto (2001) dalam “Surealisme Yogyakarta”, Sanento Yuliman (2001) dalam “Surealisme Yogya” di “Dua Seni Rupa: Sepilihan Tulisan Sanento Yuliman”, dan M. Agus Burhan (2015) dalam penelitiannya mengenai lukisan “Makasih Kollwitz” meletakkan sosok Ivan Sagita sebagai bagian dari seniman surealis Yogyakarta era 1980-an bersama Agus Kamal, Effendi, Lucia Hartini, Totok Buchori, dan Kubu Surawan. Untuk era ini, secara spesifik, Sanento Yuliman menyebutkan bahwa ‘surealisme Yogya’ telah menjadi arus yang nyata.
Selain surealisme, atribut lain yang kerap muncul adalah asosiasi karya Ivan Sagita dengan idiom-idiom kefanaan, kematian, dan hal-hal liris lainnya. Tony Godfrey, melalui tulisan kuratorialnya untuk pameran “they lay their heads on a soft place” di Equator Art Project pada 2014 di Singapura, berpendapat bahwa Ivan sering mengangkat tema kematian, karena baginya hidup dan mati adalah dua sisi yang selalu berhubungan. Memang, idiom-idiom tersebut begitu nampak ketika kita melihat karya-karyanya, seperti Women and Mask, Kefanaan, Makasih Kollwitz, Letakkan Kepala di Tubuh, dll, yang kerap memakai ikon wayang, wanita, dan nenek-nenek. Meski terkesan sangat personal dan seolah hanya bermain di ruang imajinasi, seperti yang Jumaldi Alfi katakan, karya Ivan memberi penekanan berbeda dari surealisme (barat); bukan hanya seni yang surealis, tetapi juga situasi lokalnya.
Kedekatan antara pribadi Ivan dengan situasi lokal (atau barangkali saya sebut basis empiris) sudah muncul sejak ia memulai meniti karir sebagai seniman di Lawang. Sebuah catatan penting ada pada wawancaranya dengan Naima Morelli di cobosocial pada 2016. Dalam wawancara itu Ivan mengatakan bahwa ia bertemu dengan Bambang Soegeng, seorang pelukis yang pindah ke Lawang karena gejolak politik ’65 di Bali. Ada satu nilai penting yang Ivan peroleh dari pelukis yang cukup dekat dengan Affandi ini (ada dalam catatan Oei Hong Djien, 2012, di “Seni dan Mengoleksi Seni: Kumpulan Tulisan”), yakni seniman harus dekat dengan orang-orang dan masyarakat; seni seharusnya tidak hanya tentang estetika. Dalam wawancara tim IVAA (saya, Yoga dan Zaki) dengan Ivan Sagita pada 16 April 2019, ia mengatakan,
“Kami tinggal di Kota Lawang. Beliau tinggal sebagai seorang seniman dari Bali. Saya saat itu masih SMP. … Kemudian saya dekat dan cukup banyak belajar masalah kesenimanan, tidak di dalam masalah aliran tetapi melihat pola hidup. … Bahwa jalan satu-satunya adalah kesenimanan. … Suara seniman masih bisa dipakai dengan efektif.”
Kedekatan antara dirinya dengan situasi sekitar semakin kental ketika ia pindah ke Yogyakarta. Pada waktu ia mengenyam pendidikan di ISI Yogyakarta, 1980-an, ia gemar membaca novel-novel bernada eksistensialis, seperti “Khotbah di Atas Bukit” karangan Kuntowijoyo, serta novel-novel karangan Iwan Simatupang dan Sartre. Di samping itu, ia tinggal di sekitaran Gondolayu yang dekat dengan kehidupan masyarakat kolong jembatan. Hal ini membuat Ivan merasakan suatu kesadaran baru, kesadaran atas dunia ‘atas dan bawah’; bahwa ada situasi yang kering dan merah yang ingin diungkapkan. Sementara itu, gaya kesenian yang diterapkan di ISI Yogyakarta pada waktu itu adalah abstrak; form sebagai form tanpa menginterpretasikan hal lain. Barangkali, kecenderungan ke surealisme adalah hasil dari negosiasi Ivan dengan hasrat mengungkapkan keadaan sekitar.
Pulung Gantung dan Surealisme Etnografis: Sebuah Riset Artistik
Selama 5-6 tahun terakhir Ivan Sagita menggeluti sebuah fenomena ‘pulung gantung’ sebagai bagian dari kekaryaannya. ‘Pulung gantung’ merupakan sebuah mitos masyarakat Gunungkidul yang erat kaitannya dengan fenomena bunuh diri. Belum ada yang tahu pasti kebenaran apa yang mendasari fenomena tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan mitos, faktor sosial-ekonomi, bahkan depresi. Alih-alih mengungkapkan kebenaran objektif, Ivan justru ingin mengungkapkan kerumitan realitas ini secara artistik.
Layaknya narasi-narasi di seputar surealisme, Ivan tertarik dengan alam bawah sadar. Namun, dalam konteks ini ia tidak sedang mengelaborasi alam bawah sadar psikologis yang personal, tetapi sosial.
“Surealisme di dalam konteks yang bawah sadar …. Saat itu saya mencari-cari di mana sebetulnya yang disebut dengan bawah sadar. Bawah sadar yang faktual betul. Kita tidak mengatakan di dalam sebuah gagasan secara person, yang tentunya ada di dalam psikologi. Dalam secara etnografi, bawah sadar yang sosial itu bagaimana? Karena itu juga menjadi salah satu basic, basic yang disebut sebagai suatu genre kesenian.” (wawancara pada 16 April 2019)
Ivan mempersoalkan serangkaian asumsi yang dilontarkan oleh publik terhadap fenomena ‘pulung gantung’. Bagi dia tidak cukup jika fenomena ini disebut sebagai mitos, karena ada fakta yang memang benar-benar terjadi. Untuk asumsi-asumsi lain, ia berpendapat demikian:
“Fatalisme? Gak bisa juga. Kita ini bukan suatu masyarakat yang terbentuk di dalam pola yang fatalisme. Di dalam pola komunikasi secara tradisional seperti itu masalah adaptasi sangat kuat. Masalah harmoni juga kuat. Terus nihilisme? Ah, gak juga, karena landasan religiusitas sangat tinggi. Faktor ekonomi sosial? Gak juga, apalagi itu. Banyak akademisi yang mengatakan alasan sosial ekonomi, sehingga sebuah sikap untuk mengakhiri hidupnya di masa muda.”
Pameran tunggalnya dengan tajuk “they lay their heads on a soft place” di Equator Art Project pada 2014 di Singapura menjadi satu titik penanda proses elaborasi ini. Bolehlah saya mengatakan bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Ivan adalah sebuah proses riset artistik. Argumen saya: apa yang dilakukan oleh Ivan saya maknai sebagai sebuah upaya mengeksplisitkan kerumitan fenomena dengan melibatkan cara kerja disiplin ilmu lain, yakni etnografi.
Saya tidak mengatakan bahwa riset yang dilakukan oleh Ivan adalah sebuah riset ilmiah yang memperhitungkan objektivitas dan validitas. Justru, poin yang ingin saya tekankan adalah adanya upaya untuk menghadirkan kemungkinan pendekatan lain untuk mengungkap suatu fenomena; sebentuk upaya yang berusaha keluar dari pagar besi rationale.
Surealisme dan etnografi sepertinya menjadi kesatuan penting yang hadir di sini. Seorang Ivan yang selalu diidentifikasi sebagai pelukis surealis, dan praktik riset artistiknya mengenai ‘pulung gantung’ dengan pendekatan etnografis. Dalam melakukan riset artistiknya tentang ‘pulung gantung’, ia telah menghabiskan waktu 5-6 tahun. Ia mengatakan bahwa pernah 2-3 kali dalam seminggu pergi ke lokasi untuk melayat. Ketika ada kasus penculikan anak di Gunungkidul, ia sempat dituduh sebagai penculik. Barangkali, sebutan ‘surealisme etnografis’ bisa mewakili metode yang Ivan lakukan.
Surealisme etnografis sebenarnya bukan barang baru. Secara khusus, gagasan mengenai ini sudah ditulis oleh James Clifford (1981) melalui tulisannya yang berjudul On Ethnographic Surrealism. Ia menjelaskan bahwa surealisme etnografis sebagai gagasan dan praktik muncul pada 1920-1930an di Perancis. Awalnya, ia hadir sebagai respon atas hasrat untuk menyelidiki ‘yang lain (other)’ di luar hirarki pemikiran rasional. Koleksi artefak yang berkembang dari Afrika dan Oseania di Museum Trocadéro mewakili awal yang sederhana dari penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap budaya lain, melalui Misi Dakar-Djibouti (ekspedisi etnografi terkenal yang dilakukan di Afrika, di bawah arahan Marcel Griaule, dari 1931 hingga 1933).
Clifford meneruskan bahwa surealisme, dalam praktek etnografi, berfungsi untuk memprovokasi manifestasi realitas ‘yang lain’ yang diambil dari domain erotis, eksotis, dan ketidaksadaran. Pernyataan ini diamini sekaligus ditekankan oleh DeBouzek (1989) dalam The “ethnographic surrealism” of Jean Rouch, bahwa manifestasi ‘para-artistik’ dari era ekspedisi etnografis, dalam meruntuhkan sistem hirarki pemikiran rasional melalui penyajian estetika yang berbeda, dengan mudah digolongkan di bawah mentalitas surealisme.
Poin penting yang saya tangkap dari gagasan ‘surealisme etnografis’ adalah bahwa ada realitas ‘lain (other/ surreality)’ yang tidak bisa disentuh oleh rationale. Etnografi dengan menempatkan surealisme dalam posisi yang istimewa memberikan sumbangan alternatif untuk memahami partisipan dan realitas ‘lain’ dalam kehidupan kolektifnya. Bagi saya, poin ini sesuai dengan spirit dan praktik yang sedang digeluti oleh Ivan terhadap fenomena ‘pulung gantung’.
Lantas, bagaimana teknik yang dilakukan oleh Ivan? Secara detail dan spesifik, bahasa tubuh menjadi pintu masuk bagi Ivan untuk memaknai ‘pulung gantung’. Ia menjelaskan demikian:
“Bahasa tubuh yang saya baca dari sekelompok masyarakat itu. Tipikal bahasa tubuh yang bagaimana yang akan membedakan? Adakah tipikal bahasa tubuh tertentu yang membuat sebuah sikap yang berbeda? Atau sikap yang berbeda terwujud dalam bahasa tubuh? Di Gunungkidul itu bahasa tubuh yang banyak dilakukan entah itu secara otomatis itu ya semacam begini, sehingga di karya saya ada gambar kepala, dan lain-lain.” (wawancara pada 16 April 2019)
Pendekatan surealisme etnografis tidak hadir tanpa kritik. Hal Foster (1996) melalui tulisannya yang berjudul The Artist as Ethnographer menyebutkan implikasi lain dari pendekatan ini. Bahaya self-fashioning yang berkaitan dengan fantasi primitifisme dapat muncul ketika peneliti atau seniman cenderung merasa ahli atas suatu kebudayaan tertentu; ketika kebudayaan hanya dibaca sebagai otentisitas pribumi (asli). Lebih ironis, ketika praktik surealisme etnografis masuk ke dalam mekanisme institusional, kebudayaan ‘yang lain (other/ surreality)’ akan dipandang sebagai sesuatu yang inovatif secara politis. Yang terakhir ini akan lebih nampak ketika praktik surealisme etnografis pada titik tertentu bekerja dalam sistem pasar.
Fantasi primitifisme mungkin membayangi praktik yang Ivan lakukan. Ia sempat mengatakan, “Saya ingin yang purba, untuk mengetahui clue-clue ini”. Meski demikian, saya juga melihat suatu refleksi lain yang muncul, yakni kesadaran atas batas antara Ivan dan masyarakat yang sedang ia pahami. Ia menjelaskan, “Meskipun kita sudah masuk di dalam, tetap ada layer yang mengatakan, ah, kamu orang luar, kamu orang berbeda. …. Paling-paling kita melihat selubang kecil saja dari permasalahan yang di dalam”. Mungkin saja, kesadaran atas batas ini adalah bentuk kesadaran estetis -persepsi atas ‘yang lain’- yang mampu menjadi alarm dalam praktik riset artistik, terutama yang berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat.
Apa yang dilakukan Ivan adalah satu contoh dari praktek riset artistik yang mungkin memiliki ragam bentuk lain. Alih-alih berjalan dalam koridor ilmiah, riset artistik justru menjadi ruang bagi seniman untuk berkarya di luar hirarki rasionalitas. Seperti halnya surealisme etnografis, sejauh-jauhnya menyentuh kemungkinan masa lalu dan masa depan untuk sebuah analisis budaya, ia adalah pernyataan utopis.
Sumber bacaan:
Clifford, James. 1981. On Ethnographic Surrealism. James Clifford. Comparative Studies in Society and History, 23(4): 539-564
DeBouzek, Jeanette. 1989. The “ethnographic surrealism” of Jean Rouch. Visual Anthropology, 2(3-4): 301-315
Foster, Hal. 1996. The Artist as Ethnographer. The Return of the Real. Cambridge: The MIT Press.
Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2019.