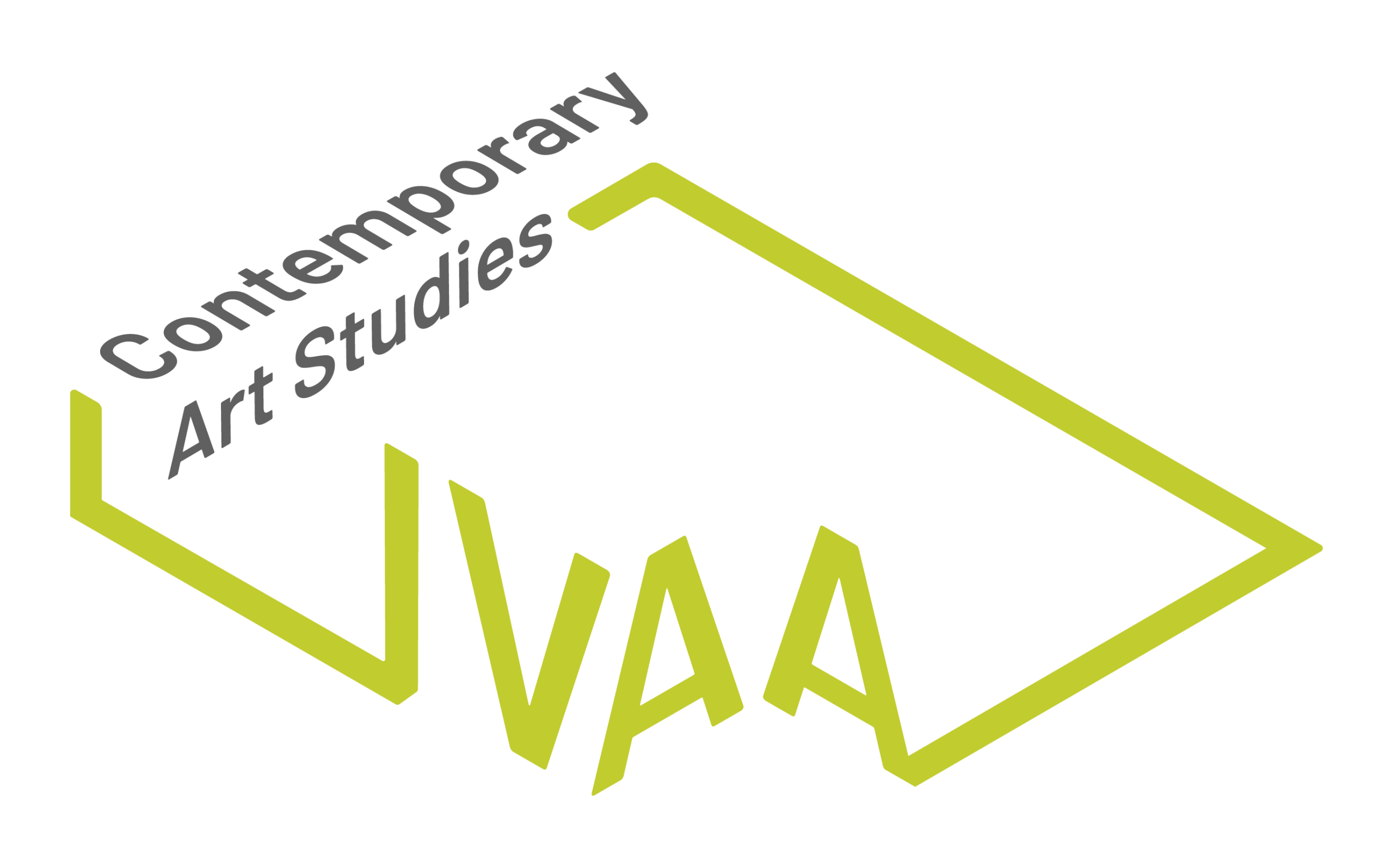Oleh Hardiwan Prayogo
Kita tentu lebih familiar bahwa monumen selalu berbentuk patung. Lantas bagaimana dengan pillory? Ini adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Hans Van Houwelingen, seniman Belanda yang fokus dengan gagasan seni di ruang publik. Dalam diskusi di Rumah IVAA yang berlangsung Sabtu, 11 Mei 2019, dia mempresentasikan proyek pembuatan pillory di Belanda. Pillory secara umum dapat diartikan sebagai counter-monument, meski secara detail ia cukup berbeda karena bukan hanya menghapus monumen (ingatan buruk) tetapi justru menghadirkan pembandingnya. Itu pula kenapa diskusi ini bertajuk From Statue to Pillory ini, mempersoalkan makna monumen sebagai artefak pengetahuan dan ingatan masyarakat akan sejarah penjajahan.
Gagasannya berangkat dari kegelisahan atas monumen yang dibangun untuk mengingat Benedictus Van Heutsz, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang membantai ribuan orang dalam Perang Aceh (1873-1914). Keberadaan monumen itu dianggap bermasalah karena tidak menggarisbawahi kekejaman yang telah dilakukannya. Serta masih menganggap Van Heutsz sebagai salah satu pahlawan nasional. Hans Van Houwelingen mengajak kita untuk menilai bagaimana bangsa Belanda memaknai monumen dan sejarahnya dengan Indonesia.
Hans memulai presentasinya dengan menunjukan video orang-orang merusak monumen dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai penjahat kolonial. Dia merasa masyarakat perlu mengingat memori buruk dan perlu melakukan tindakan nyata seperti melempari monumen dengan kentang hingga kotoran. Semacam menjadi pengingat supaya kejahatan-kejahatan masa lalu tidak terulang.
Diskusi yang digelar atas kerjasama dengan Brikolase ini sengaja untuk mendengar perspektif dari orang Indonesia, sebagai pihak yang menjadi wilayah koloni. Maka diskusi yang berlangsung hampir 2 jam ini, lebih banyak mendengarkan opini dari audiens. Di antara mereka ada yang aktif sebagai aktor kesenian, seperti Agung Kurniawan, Iwan Wijono, Nindityo Adipurnomo, Sanne Oorthuizen, dan beberapa akademisi.
Beberapa feedback menarik terlontar dari forum tersebut. Dikatakan bahwa kehadiran pillory bisa jadi akan dimaknai berbeda oleh orang Indonesia. Ini disebabkan oleh setiap masyarakat memiliki kultur tersendiri untuk mengingat peristiwa-peristiwa traumatiknya. Tidak semua lapisan masyarakat berani untuk menunjukkan kemarahan dan kebenciannya, bahkan terhadap orang-orang yang sudah jelas telah melakukan kejahatan terhadap mereka. Dengan kata lain, kita memiliki cara tersendiri untuk “berdamai” dengan ingatan. Persoalan lain yang menghinggapi adalah bagaimana cara dan untuk apa masyarakat kita memaknai sejarah dan mental serta perilaku macam apa yang perlu dirubah untuk memaknai kolonialitas.
Pada akhirnya diskusi ini memang tidak disimpulkan secara eksplisit. Namun rasanya satu hal yang dipelajari Hans dari diskusi ini adalah kita harus awas terhadap kehadiran monumen dan pemaknaan atas sejarah dan cara pandang siapa yang diwakili oleh kehadiran monumen di ruang publik. Sudah barang tentu bahwa cara masyarakat Eropa memaknai sejarah dan masa lalunya tidak akan bisa semudah itu diterapkan pada konteks masyarakat yang pernah menjadi wilayah koloni.
https://www.instagram.com/p/BxY947ngPRZ/
Artikel ini merupakan rubrik Agenda RumahIVAA dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Mei-Juni 2019.