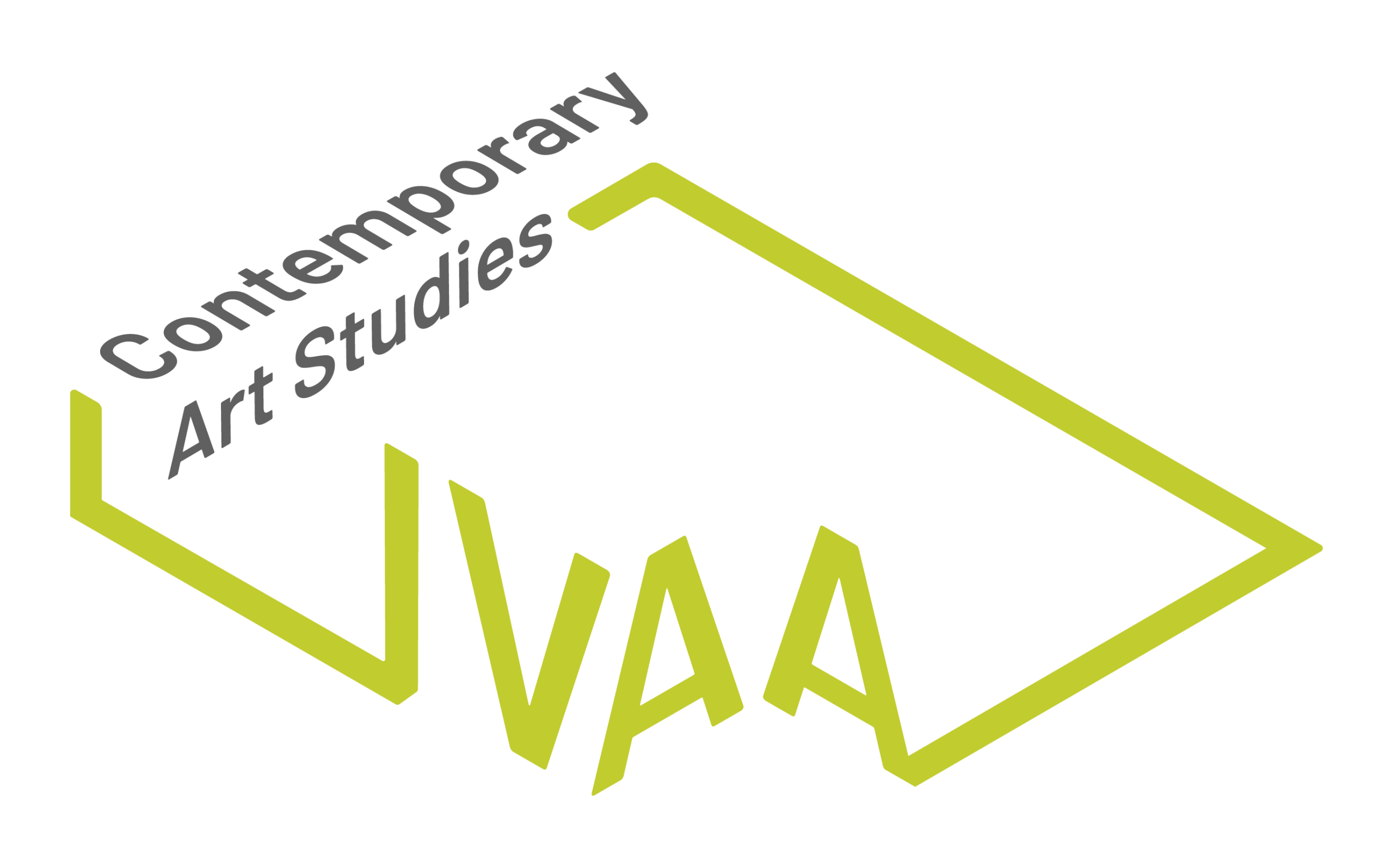Judul : Jejak Jejak Manusia Merah-Siasat Politik Kebudayaan Bali
Judul : Jejak Jejak Manusia Merah-Siasat Politik Kebudayaan Bali
Pengarang : I Ngurah Suryawan
Penerbit : BukuBaik
Tahun Terbit : 2005
Halaman : 276
ISBN : 979-3239-29-8
Resensi oleh : Santoso Werdoyo
Warna merah untuk font judul buku dan foto seorang remaja berambut mohawk yang sedang menata sesaji di jalan. Entah kesan apa yang coba dibangun oleh penulis, barangkali minor nadanya. Jejak Jejak Manusia Merah mengurai catatan mengenai jejak-jejak kuburan massal pembantaian PKI 1965-1966, khususnya di Kabupaten Jembrana ujung barat Pulau Bali.
Catatan-catatan sejarah menyebutkan: sebelum menjadi tujuan wisata, Bali terkenal sebagai wilayah yang mengekspor budak belian. Bali juga dikenal sebagai daerah yang sangat ‘barbar’. Penuh peperangan dan pembantaian pada sesama. Semua label itu segera berubah ketika eksotisme manusia Bali dengan perempuannya yang bertelanjang dada, pemandangan alam, seni dan tradisinya yang membuat para pelancong serta sarjana berlibur di Bali mulai dimunculkan.
Pada 1930 unsur modernitas dibawa oleh para pelancong, pedagang, seniman, dan sarjana asing ke Bali melalui pariwisata. Lalu ia sempat tersendat ketika gejolak revolusi kemerdekaan berlangsung pada 1945-1949. Semakin parah ketika masuk ke ketegangan politik pada 1950-an hingga 1960-an. PNI dan PKI sedang dalam pertarungan politik, memperebutkan kekuasaan, yang akhirnya membuat Bali menjadi ikut panas. Para ‘manusia merah’, mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI, dibantai habis-habisan. Jejak kelam ini kemudian dikubur rapi dalam selimut tebal politik pariwisata budaya, sebuah ideologi pembangunan dan stabilitas keamanan ala orde baru. Perlahan tapi pasti, pembangunan infrastruktur pariwisata kembali menunjukkan giginya. Hotel, cafe, diskotik, dan tempat hiburan lainnya mulai bermunculan. Belum lagi bisnis prostitusi, narkoba hingga rantai kriminalitas yang seolah tak terelakkan. Kehidupan politik pascakolonial di Bali ditandai dengan politik siyu (bersorak dan mendukung yang dominan), untuk kemenangan Golkar.
Sederetan peristiwa konflik dihadirkan melalui buku ini: sengketa pembagian sentra (kuburan) di lingkungan Banjar pada 10-11 Maret 2005, perselisihan anak muda Desa Pakraman Ulakan dan Angan Telu pada 13 Maret 2005, serta perselisihan di Desa Kejula pada 12 April 2005. Ada keyakinan dari penulis bahwa serangkaian konflik ‘etnis’ tersebut disebabkan oleh situasi keterhimpitan orang Bali di daerah kelahirannya sendiri yang membuat mereka saling klaim tanah dengan saudaranya. Sayangnya potret beringas Bali tidak dilihat sebagai persoalan yang berkaitan dengan konstruksi pariwisata. Olah karena itu yang terjadi justru penguatan identitas ke-Bali-an, ekstremnya gerakan politik identitas etnis.
Keamanan dari pengaruh luar akhirnya menjadi perhatian pemerintah Bali. Gubernur Mangku Pastika menekankan keberadaan adat, budaya, dan agama yang satu, yakni Hindu. ‘Ajeg Bali’ menjadi jargon untuk menawarkan jalan baru ke arah keutuhan dan kesolidan. Sweeping pendatang menjadi salah satu agenda turunan dari jargon ini, apalagi pasca bom Bali.
‘Nak Jawa’ menjadi sebutan untuk para pendatang yang datang ke Bali. Gaung sebutan ini hampir ada di setiap sudut kota ketika terjadi pencurian di Bali pada 1980-an. Sentimen negatif terhadap pendatang diperkuat oleh pemberitaan media massa. Sampai akhirnya terjadi bom Bali dengan Amrozi sebagai simbol ‘Nak Jawa’ yang telah menghancurkan Bali. ‘Nak Jawa’ juga diam-diam dimanfaatkan dalam skena perebutan kekuasaan politik di sana. Mereka kerap didekati untuk mendapat dukungan suara. Selain itu, kehadiran mereka juga menjadi harapan bagi para pemilik kos-kosan untuk menambah penghasilan. Ajeg Bali sebagai jargon menuju keutuhan, juga menyimpan dilema.
Ada juga gambaran jejak-jejak kekerasan yang terjadi pada 1965-1969. Ada sebuah tegalan di tengah hutan bambu terdapat pelinggih (pura kecil sebagai tempat pemujaan). Pelinggih itu beratap kayu dan sudah lapuk. Orang-orang Melaya menyebutnya sebagai daerah Lubang Buaya. Berbeda dengan Lubang Buaya yang ada di Jakarta, Lubang Buaya yang ini tidak dilengkapi dengan monumen fisik. Monumen yang menjadi penanda adalah cerita dari para tetua. Mereka menyebutkan bahwa di sini dulu ada kurang lebih 50 mayat ‘manusia merah’ yang dikuburkan. Tidak semua mayat dikubur di situ. Dengan menggunakan truk, selebihnya dibuang di Pantai Candikusuma.
Cerita atau malah sejarah tentang kekerasan yang berhubungan dengan para ‘manusia merah’ juga ada di Desa Tegalbadeng. Di desa ini, keutuhan Ajeg Bali agaknya terganggu dengan ragam versi mengenai peristiwa kelam yang melibatkan PKI, Front Pancasila serta Anshor. Ketidakpastian versi ini barangkali mirip dengan peristiwa G30S yang sudah sering kita dengar. Bedanya, peristiwa di Desa Tegalbadeng terjadi pada November.
Selain di wilayah gerakan politik, kekerasan dan kekuasaan juga hidup di seni rupa. Jejak seni rupa Bali yang dipengaruhi politik kolonial dan kuasa elit lokal menciptakan desain seni yang diwariskan hingga kini. Semula gaya seni rupa Bali adalah untuk ritual, lalu bergeser menjadi modern sejak kehadiran Walter Spies dan Rudolf Bonnet pada 1927 dan 1929. Pitamaha pun lahir karena pengaruh paradigma barat pada 1939. Berlanjut pada terbentuknya Young Artist dan Sanggar Dewata Indonesia pada 1970-an. Dari rentetan perkembangan tersebut, sayang sekali narasi seniman generasi 1960-an telah dihapus oleh rezim orde baru karena asosiasi mereka dengan gerakan komunisme. Itu adalah kekerasan. Tidak hanya itu, kekerasan sebenarnya sudah berubah bentuk. Penghapusan narasi sejarah telah berganti menjadi pelestarian logika industrialisme di dunia seni rupa yang menempatkan seniman sebagai mesin produksi. Kekerasan yang terakhir ini jelas adalah warisan paling konkret dari perkembangan seni rupa sebelum-sebelumnya.
Buku ini mencoba menghadirkan konstruksi sejarah yang tidak solid. Bukti dokumen berhadap-hadapan dengan ingatan. Dokumen sebagai representasi arus atas yang formal berbenturan dengan ingatan sebagai narasi dari arus bawah. Berbagai kekerasan yang terjadi di domain gerakan politik, kesenian, dan juga pendidikan telah menyisakan jejak-jejak kabur.
Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Mei-Juni 2019.