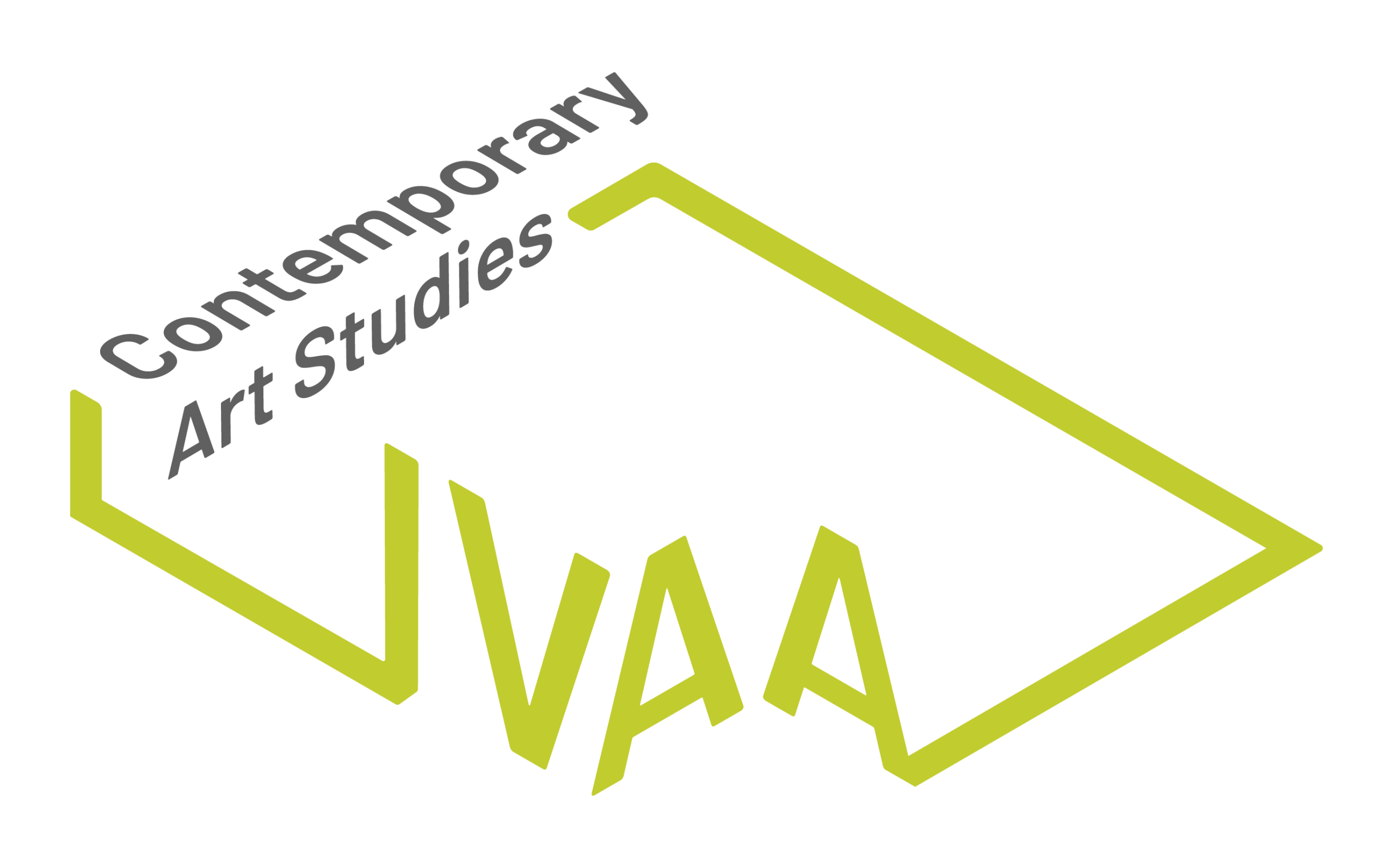Oleh: Anne Shakka
Saya ini belum genap satu tahun bergelut dengan dunia seni-senian. Dengan sekolah formal yang berlatar belakang psikologi yang begitu scientific dan positivis, dunia seni, seni rupa pada khususnya, adalah hal yang sangat jauh dari diri saya. Sebelum masa hampir satu tahun ini, saya tidak pernah tahu aktivitas seni di Yogyakarta selain yang begitu populernya seperti ArtJog, itu saja belum tentu saya datangi. Jadi ketika karena satu dan lain hal saya nyemplung begitu saja pada dunia seni ini, saya jadi menyadari bahwa saya begitu buta dengan apa yang ada di dunia seni ini, baik secara umum, maupun dunia seni di Yogyakarta secara khusus, yang ternyata begitu hidup dan meriah.
Diawali dengan tugas untuk membaca catatan kuratorial suatu pameran seni dan bagaimana posisi pameran tersebut dalam konteks pascakolonial, yang ternyata sampai habis tenggat saya tidak bisa memproduksi apapun. Akhirnya setelah dengan permakluman yang begitu baik hati, saya diizinkan untuk menuliskan bagaimana pengalaman saya dalam membaca bahan-bahan bacaan tersebut yang tentu saja masih belum seberapa ini. Ya bisa dibilang pengantar ini adalah permintaan maaf dan sebuah alasan untuk tulisan saya yang entah bagaimana jadinya nanti.
Saya mengawali pembacaan saya dengan catatan kuratorial dari pameran yang bertajuk Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southest Asia. Pameran ini diadakan di Bangkok Art and Culture Centre pada 13 Desember 2013 sampai dengan 2 Maret 2014. Pameran seni rupa yang melibatkan empatpuluh satu seniman Asia Tenggara kelas satu dan menghadirkan lebih dari limapuluh karya seni, sebagaimana yang dikatakan oleh Luckana Kunavichayanont—Direktur dari Bangkok Art and Culture Centre dalam pengantarnya di buku yang sama. Pameran ini juga melibatkan tiga orang kurator dari tiga negara yaitu Iola Lenzi dari Singapura, Agung Hujatnikajennong dari Indonesia dan Vipash Purichanont dari Thailand. Catatan kuratorial pertama dalam hidup yang saya baca.
Iola Lenzi mengawali tulisannya dalam katalog tersebut dengan menelusuri perkembangan seni kontemporer di Asia Tenggara. Sebagaimana yang saya tangkap, seni rupa di Asia Tenggara ini masih terasa gagap untuk untuk membicarakan kekontemporeran dirinya, tentu saja ketika hal itu dihadapkan pada linimasa perkembangan seni rupa barat yang dianggap lebih mapan dengan sejarahnya yang begitu panjang. Pemahaman atau definisi kontemporer di sini pastinya tidak bisa dikotakkan dengan bingkai yang sama dengan apa yang tumbuh dan dipahami oleh seni rupa barat. Bahan lain yang bisa kita perdebatkan lagi lain waktu.
Asia Tenggara sendiri sebagai suatu kawasan, dianggap tidak memiliki sejarahnya sendiri apalagi jika dibandingkan dengan peradaban-peradaban tetangga seperti Cina dan India yang dianggap sudah lebih mapan.[1] Ia seakan-akan muncul begitu saja sebagai suatu konsep pada tahun 1967 yang merupakan respon terhadap perang dingin antara blok Barat dan Timur pada masa itu. Kawasan yang terdiri dari negara-negara yang belum genap satu abad mengenyam kemerdekaannya dan bukan suatu kawasan yang homogen. Asia Tenggara terdiri dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan kebudayaan yang membuatnya begitu beragam, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa kawasan ini juga memiliki ciri khas dan kesamaan budayanya sendiri.[2]
Kondisi dari kawasan ini menjadi salah satu titik pijak dalam pembuatan karya di dalam pameran CCC. Karya-karya seni yang dihadirkan merupakan suatu ekspresi sosial yang menghadirkan realitas masyarakat dalam ruang pamer. Narasi-narasi yang dibawa oleh para seniman di sini banyak berangkat dari apa yang menjadi keprihatinan dan kritik mereka terhadap pemerintahan di negaranya masing-masing. Karya yang juga menemukan konteksnya ketika didialogkan atau mengajak keterlibatan dari penontonnya.
Salah satu yang menarik perhatian saya adalah karya dari FX. Harsono yang berjudul “Apa yang Anda Lakukan jika Krupuk ini adalah Pistol Beneran?” Karyanya berupa setumpuk krupuk berbentuk pistol dengan bahan yang tampaknya sama seperti cone es dung-dung yang biasa kita temui berkeliling di kampung-kampung. Di situ dia juga menempatkan sebuah buku catatan sebagai tempat memberikan jawaban-jawaban dari pengunjung yang mau merespon karya tersebut. Beberapa jawaban yang diberikan seperti, “menembakkannya pada Thaksin Sinawatra,”[3] Perdana Menteri Thailand yang digulingkan dengan kudeta pada 19 September 2006.
Kritik terhadap negara dan ketidakadilan dalam masyarakat juga muncul dalam karya dari Manit Sriwanichpoom yang berjudul The Election of Haterd. Manit menampilkan poster para peserta pemilihan umum tahun 2011 yang dirusak. Karya ini berhasil memprovokasi para penontonnya untuk menyadari realitas sosial yang ada di sekitar mereka dan pada saat itu, karya ini juga menjadi kontekstual karena Thailand sendiri juga akan mengadakan pemilu lagi pada tahun 2014 tersebut. Menarasikan atau menghasilkan karya dari apa yang menjadi temuan dan keprihatinan dalam masyarakat menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk memunculkan ke-Asia Tenggara-an yang membedakan diri dari yang lain.
Membaca catatan tersebut dan beberapa artikel lain yang diharapkan bisa membantu untuk bersuara. Saya melihat bahwa sebagai suatu pameran seni yang berasal dari pinggiran (periphery), suatu negara dunia ketiga jika kita perbandingkan dari spektrum Barat dan Timur, seni di Asia Tenggara ataupun di Indonesia selalu dihadapkan dengan liyan besar yaitu dunia seni barat. Dunia seni yang menjadi patron dan memberikan standar bagi sepertinya seluruh kesenian yang ada di dunia ini. Dan strategi untuk mencari identitas atau seni yang asli timur, asli Asia tenggara, atau asli Indonesia, sering kali, jika tidak mau dikatakan selalu, menjadi permasalahan yang banyak diangkat.
Hal yang senada juga saya temukan dalam membaca dua artikel dari Arham Rahman. Satu berjudul Seni Zaman Now artikel yang saya dapatkan dari orangnya langsung, jadi saya tidak tahu itu diterbitkan di mana, dan artikel yang lain adalah Dari “Kritik Seni” ke “Kritik Kuratorial”[4] Kedua tulisan tersebut berbicara mengenai dominasi dari sejarah dan standar barat yang di satu sisi menjadi panduan dalam melakukan sesuatu, seperti di bidang kuratorial yang dianggap lebih terstandar dengan sistem yang lebih terlembaga.
Hal yang senada juga saya tangkap dari S. Sudjojono ketika dia mengkritisi seni yang bercorak mooi Indie yang mengeksotiskan diri sendiri. Di satu sisi Sudjojono menyadari akan adanya orientalisme yang terjadi terhadap Indonesia, tetapi dia juga berusaha untuk mencari ciri khas atau identitas dari seni Indonesia itu sendiri.
Dominasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam dunia seni rupa, selalu memunculkan sempalan-sempalan yang membuat subjek di luar kelompok tersebut mencari identitasnya sendiri. Jika ditarik dalam konteks pascakolonial, kecenderungan atau keinginan untuk mencari yang asli, yang pribumi, yang ada sebelum terjadinya kolonialisme, merupakan sesuatu yang banyak terjadi. Ketika identifikasi terhadap liyan yang menjajah itu gagal, dan pasti akan terus gagal. Orang-orang yang terjajah akan mencari kembali akar aslinya, sesuatu yang dianggap masih murni sebelum kedatangan penjajah atau yang biasa dikenal dengan nativisme.
Nativisme sendiri adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya keinginan atau gerakan untuk menemukan atau memunculkan kembali kebudayaan asli atau kebudayaan sebelum kolonialisme terjadi.[5] Pandangan ini berangkat dari pandangan bahwa memang ada sebuah budaya yang asli yang ada sebelum kolonialisme terjadi, dan bahwa budaya yang “asli” tersebut bisa diraih kembali. Hal ini dimunculkan untuk mengatasi atau melampaui kolonialisme yang seringkali mendiskriminasikan atau merendahkan orang-orang yang dikoloni, sebagai contohnya yang terjadi pada orang-orang kulit hitam.
Salah satu gerakan yang muncul untuk melawan kolonialisme yang terjadi pada orang kulit hitam adalah gerakan yang dikenal dengan Négritude. Gerakan ini pada awalnya dimunculkan oleh para intelektual Afrika dan Caribia yang berada di Paris seperti Leopold Sedar Senghor dan Aime Césaire pada sekitar era perang dunia kedua.[6] Négritude sendiri adalah suatu gerakan orang-orang kulit hitam yang muncul melalui tulisannya yang membawa semangat untuk memperbaiki gambaran orang kulit hitam dengan mengekspresikan atau mengafirmasi kehitaman.[7] Dalam gerakan ini muncul kecenderungan untuk merayakan kehitaman yang selama ini berada dalam posisi inferior dibandingkan dengan kulit putih. Négritude, sebagai suatu gerakan, bisa dianggap malah menjadi gerakan yang “rasis” karena mengafirmasi superioritas atas kulit putih.[8] Pandangan esensialis akan adanya suatu identitas hitam juga menjadi dasar dari munculnya gerakan ini, walaupun dalam retorika yang diajukan identitas kehitaman tersebut dibicarakan secara positif dan dirayakan.
Saya tidak tahu apakah permasalahan mengenai mencari identitas asli ini sudah terjawab atau belum dalam dunia seni rupa. Atau sudah ada yang menjawab dan saya belum menemukan orang yang menjawab permasalahan tersebut, juga bisa jadi. Saya masih belajar. Tetapi apakah memang ada yang bisa disebut sebagai sesuatu yang asli? Asli Indonesia saja lah. Tidak perlu membahas yang seluas Asia Tenggara.
Menelusur kembali pada kesejarahan kawasan nusantara, kawasan ini sendiri sudah menjadi kawasan yang kosmopolit dengan adanya perdagangan dengan berbagai negara sejak abad ke-13. Hubungan perdagangan yang baik ini terjadi karena kepulauan Nusantara sudah terkenal sebagai daerah yang kaya dan merupakan penghasil berbagai hasil bumi. Suasana yang kosmopolit ini juga yang membuat orang dari berbagai tempat asing dapat tinggal dan membaur dengan penduduk setempat.[9] Di sini dapat diartikan bahwa sudah terjadi percampuran antara orang setempat dengan berbagai budaya yang datang dan masuk ke Nusantara. Dalam dunia seni, sebagaimana yang diceritakan oleh Claire Holt bahwa sejak awal kedatangannya, bangsa barat dan para raja di Nusantara sudah saling bertukar artefak dan karya seni, yang di sini pasti terjadi pertukaran juga pengetahuan yang pastinya akan saling memengaruhi. “Pengaruh-pengaruh Barat pada seni di Indonesia mungkin telah mulai dengan sedikit gambar-gambar yang dibawa oleh para agen Kompani India Timur Belanda (VOC) sebagai hadiah-hadiah kepada para penguasa lokal…”[10]
Mempertahankan binaritas dan dikotomi antara Barat dan Timur, atau antara negara maju dan kita yang dianggap sebagai negara dunia ketiga, rasanya sama saja dengan tetap mempertahankan diri kita dalam kotak kolonialisme. Dengan semua pertemuan dan percampuran yang terjadi dari abad ke-13 sampai saat ini, mencari yang menyatakan diri sebagai Indonesia atau Asia Tenggara, apakah sesuatu yang masih bisa dilakukan? Bukankah negara ini sendiri juga adalah sebuah konsep yang bahkan belum sampai satu abad adanya?
Menyatakan diri dengan mengangkat dan menarasikan isu lokal, isu dalam masyarakat di mana seniman itu bergumul dengan permasalahan sosial di dalamnya, bisa jadi itu malahan menjadi seni yang menjadi identitas suatu kawasan. Seni yang bisa menyelamatkan atau minimal mewakili masyarakatnya untuk menyatakan diri dari berbagai ketidakadilan yang dialami. Bisa jadi demikian.
Sumber:
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (1998). Key Concepts in Post-Colonial Studies. London, Routledge.
Bujono, Bambang & Wicaksono, Adi (ed). (2012). Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta
Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southest Asia. 13 Desember 2013-16 Maret 2014. Ed. Iola Lenzi. katalog Pameran
Gordon, Lewis R. (2015). What Fanon Said. New York, Fordham University Press.
Holt, Claire. (2000) Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. Bandung: arti.line
Lombard, Denys (1996b). Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
Taylor, Nora. A. Art Without History? Southeast Asian Artist and Their Communities in tha Face of Geography, dalam Art Journal, Vol. 70, No. 2 (Summer 2011), pp. 6-23. Diunduh dari http://www.jstor.org/stable/41430719 pada 20 Maret 2018
Rahman, Arham. Seni Zaman Now. Artikel
Jurnal SKripta Volume 04/Semester 2/2016
[1] Taylor, Nora. A. Art Without History? Southeast Asian Artist and Their Communities in the Face of Geography, dalam Art Journal, Vol. 70, No. 2 (Summer 2011), pp. 6-23.
[2] Agung Hujatnikajennong, Trajectories/Contingencies, Indonesia contemporary art and the regional context dalam Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southeast Asia. Hal 26
[3] Vipash Purichanont, Contesting Communities dalam Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southeast Asia. Hal 34
[4] Arham Rahman, Dari “Kritik Seni” ke “Kritik Kuratorial” dalam SKripta Volume 04/Semester 2/2016 hlm.2-21
[5] Ashcroft, Griffiths et al, 1998: 161
[6] Ibid, p 161
[7] Gordon, Lewis R. (2015). What Fanon Said. New York, Fordham University Press. p. 53
[8] Ibid. p. 52
[9] Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia (1996). Hlm 45
[10] Claire Holt. (2000) Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. Bandung: arti.line
Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2018.