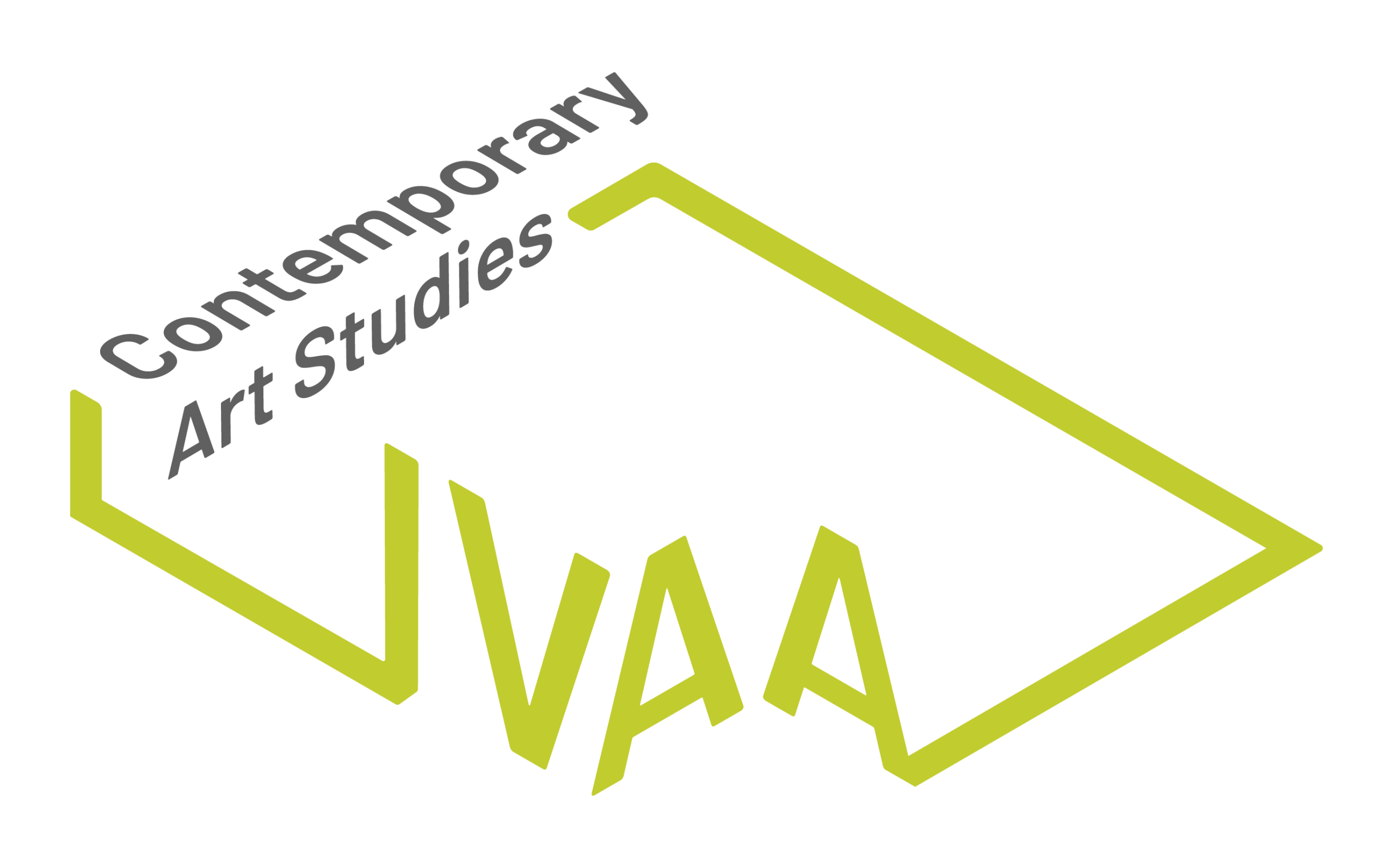Oleh: Tiatira Saputri
Di tahun 1990-an, publik seni gelisah dengan rencana pembongkaran gedung Senisono. Gedung yang berdiri sejak tahun 1915 tersebut sudah menjadi rumah bagi beragam kegiatan seni sejak tahun 1968. Sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 1945 gedung ini menjadi lokasi Kongres Pemuda. Selain bersejarah, keberadaan gedung ini juga mencatat berbagai dinamika seni budaya serta menjadi saksi dari berbagai peristiwa bernilai. Oleh sebab itu, banyak seniman berupaya menegosiasikan pembatalannya ketika pemda berencana membongkar Senisono. Sebut saja peristiwa happening art bertema “Aksi Cinta Kasih” yang digelar di Malioboro, pembuatan instalasi patung di titik nol kilometer, dan Panggung Solidaritas Senisono oleh Teater Jiwa. Meskipun pada akhirnya, di tahun 1995 Senisono tetap saja dibongkar.

Sumber: koleksi IVAA http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/3085
Jauh sebelum Senisono dibongkar, ada baiknya jika kita menilik ke belakang untuk melihat sejauh apa Senisono dihidupi dan menghidupi dinamika kesenian di Yogyakarta. Menilik lokasi Senisono yang berada di penghujung ruas Malioboro, maka ketika membicarakannya berarti kita juga membicarakan Malioboro. Sebagai jantung dari sebuah kota, Malioboro sudah punya sejarah panjang sebagai ruang diplomasi. Di abad ke-10, Malioboro yang diposisikan sebagai jalan utama kerajaan atau yang dalam bahasa Sansekerta disebut rajamarga, jalan ini juga sekaligus menjadi ruang pertemuan raja dengan rakyatnya. Ia dimaknai sebagai ruang penghubung antara manusia dengan kosmosnya serta menjadi pusat kegiatan seremonial kerajaan yang dibuka untuk publik. Pada masa kolonial, Malioboro yang tadinya meliputi seluruh wilayah dari Keraton hingga Tugu Jogja, kemudian terbagi menjadi dua setelah pemerintahan Belanda membuka jalur kereta dan mendirikan Stasiun Tugu. Kendati demikian, Malioboro justru semakin hidup sebagai ruang diplomasi. Malioboro yang menjadi sebatas Keraton Ngayogyakarta hingga Stasiun tugu itu, akhirnya menjadi ruang untuk pertemuan yang diselenggarakan kerajaan, baik dengan warga maupun pejabat-pejabat tinggi Eropa.
Di tahun 70-an sampai 80-an, ketika kita bicara tentang seni di Yogyakarta, beberapa kali nama Malioboro dan Senisono disebut. Mungkin ini ada kaitannya dengan kehadiran Senisono sebagai ruang yang memfasilitasi kegiatan seni, baik dari diskursus sampai proses kreatif seni itu sendiri. Salah satu yang pernah menjadi sorotan di tahun 70-an adalah ketika Kelompok Kepribadian Apa, yang kemudian menjadi PIPA, gagal mengadakan pameran di Senisono, dikarenakan tampilan serta konten pameran dianggap terlalu vulgar atau bisa dikatakan frontal mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Namun, bentuk kesenian yang dibawakan oleh kelompok PIPA ini justru menjadi oase segar untuk seni rupa saat itu. Dari sana PIPA kemudian dipandang sebagai salah satu percikan awal hidupnya seni kontemporer di Yogyakarta. Sama halnya ketika di tahun 1980-an Eddi Hara menampilkan performance art di Malioboro, dari situlah seni rupa mulai hadir di titik keramaian ruang terbuka, yang kemudian kita kenal dengan sebutan seni ruang publik.

Gambar: Pameran Seni Kepribadian Apa tahun 1977 Sumber: koleksi IVAA
Sebagai rumah dari beragam bentuk kesenian beserta komunitas yang menghidupi, beberapa nama besar yang kita kenal sekarang, juga sempat tercatat telah menjadikan Malioboro sebagai rumahnya, diantaranya ialah Sawung Jabo di tahun 1970-an dan Ugo Untoro di tahun 1990-an.
Pada tahun 1990-an Apotik Komik juga membuat mural bertema “Sakit Berlanjut”di sekitar Maliboro, sebagai bagian dari Festival Kesenian Yogyakarta. Sejak saat itu mural menjadi lebih populer digunakan sebagai medium komunikasi, yang masih berlangsung hingga kini. Tidak hanya mural, berbagai kegiatan berbasis komunitas yang juga merupakan suara warga atas perubahan kotanya juga bisa kita temui di sekitar Malioboro. Seperti misalnya Apeman yang diselenggarakan Komunitas Malioboro (COMA) atau Gelar Kreativitas Girli setiap tahunnya.

Sumber: koleksi IVAA http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/138
Di tahun 2000-an perbincangan mengenai Malioboro banyak mengarah pada pembahasan mengenai perebutan kepentingan atas ruang publik. Sejak Walikota Soejono AJ di tahun 1970-an membuat kebijakan untuk membangun trotoar di kawasan Malioboro sebagai fasilitas pejalan kaki, pada saat itulah kawasan Malioboro justru penuh pedagang kaki lima. Sampai akhirnya di tahun 1987 muncul kebijakan mengenai penggunaan lahan Malioboro. Salah satu kebijakannya adalah dengan mengalih fungsikan trotoar bagian timur Malioboro sebagai lahan parkir, sebagai respon atas padatnya pengunjung berkendara di wilayah Malioboro. Itu artinya, di tahun 1980-an, pemerintah mulai menyetujui dan memaksimalkan pertumbuhan wilayah Malioboro sebagai ruang niaga. Malioboro dinilai perkapling, setiap jengkalnya memiliki nilai investasi. Ini menjadikan wilayah yang seharusnya milik publik kini menjadi ruang personal. Orang menjadi sangat perhatian dengan wilayahnya masing-masing, sehingga tidak heran, jika di tahun 1990-an masyarakat mulai banyak mengeluhkan kondisi Malioboro yang tidak nyaman. Jangankan untuk berinteraksi, berjalan menyusuri trotoar pun membuat kita harus sering beradu bahu lantaran sempit dan banyaknya wisatawan berbelanja. Lahirnya komunitas di Malioboro seperti komunitas Pinggir Kali (Girli) atau pun COMA bisa jadi merupakan bagian dari respon terhadap perubahan tersebut.
Girli misalnya, yang ada sejak tahun 1981 dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, seniman, aktivis, sampai warga kampung setempat ini selalu berupaya merangkul masyarakat Malioboro. Karena bukan saja warga lokal dan wisatawan, tapi juga anak-anak jalanan banyak menjadi korban kekerasan di Malioboro, seperti misalnya copet, mafia asuransi, mafia pengemis, atau korban pertengkaran antar kelompok di area Malioboro. Melihat kasus-kasus seperti itu seakan kita sudah tidak bisa lagi berkompromi di ruang Malioboro. Untuk itulah komunitas seperti COMA rutin mengadakan Apeman di wilayah Malioboro. Karena selain melestarikan tradisi, Apeman juga salah satu cara untuk bernegosiasi dengan warga sekitar tentang bagaimana mengupayakan ruang hidup yang lebih cair di Malioboro melalui kesenian dan kegiatan berbagi. Sehingga jika kita lihat kembali, kesenian hari ini di Malioboro tidak melulu dari seniman, tapi juga dari warga yang memiliki kepentingan untuk berdialog dengan rakyat banyak.
Di tahun 1980-an, ketika seni eksperimental masih sangat baru dan menjadi materi eksplorasi yang sangat segar bagi perupa, muncul beberapa praktik seni, seperti yang pernah dilakukan Eddi Hara di tahun 1987 dengan menelusuri wilayah Malioboro, dari stasiun Tugu, Sosrowijayan, sampai Senisono Art Gallery dalam waktu 24 jam. Kerja seni yang idenya diambil dari “Hardship Art” dalam buku Art in America ini sesungguhnya merupakan cara lain Eddi Hara untuk merasakan sensasi tradisi mati raga, puasa membisu, atau puasa mati geni melalui kesenian.
Dari berbagai ragam peristiwa yang terjadi, terutama di Malioboro, mulai dari aktivitas niaga, diplomasi hingga kebudayaan dalam berbagai pemaknaannya, terdapat satu nilai dominan yang tidak bisa dilepaskan dari Malioboro, yakni ruang dialog karena keberadaannya sebagai pusat kota dan kerumunan.
Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.