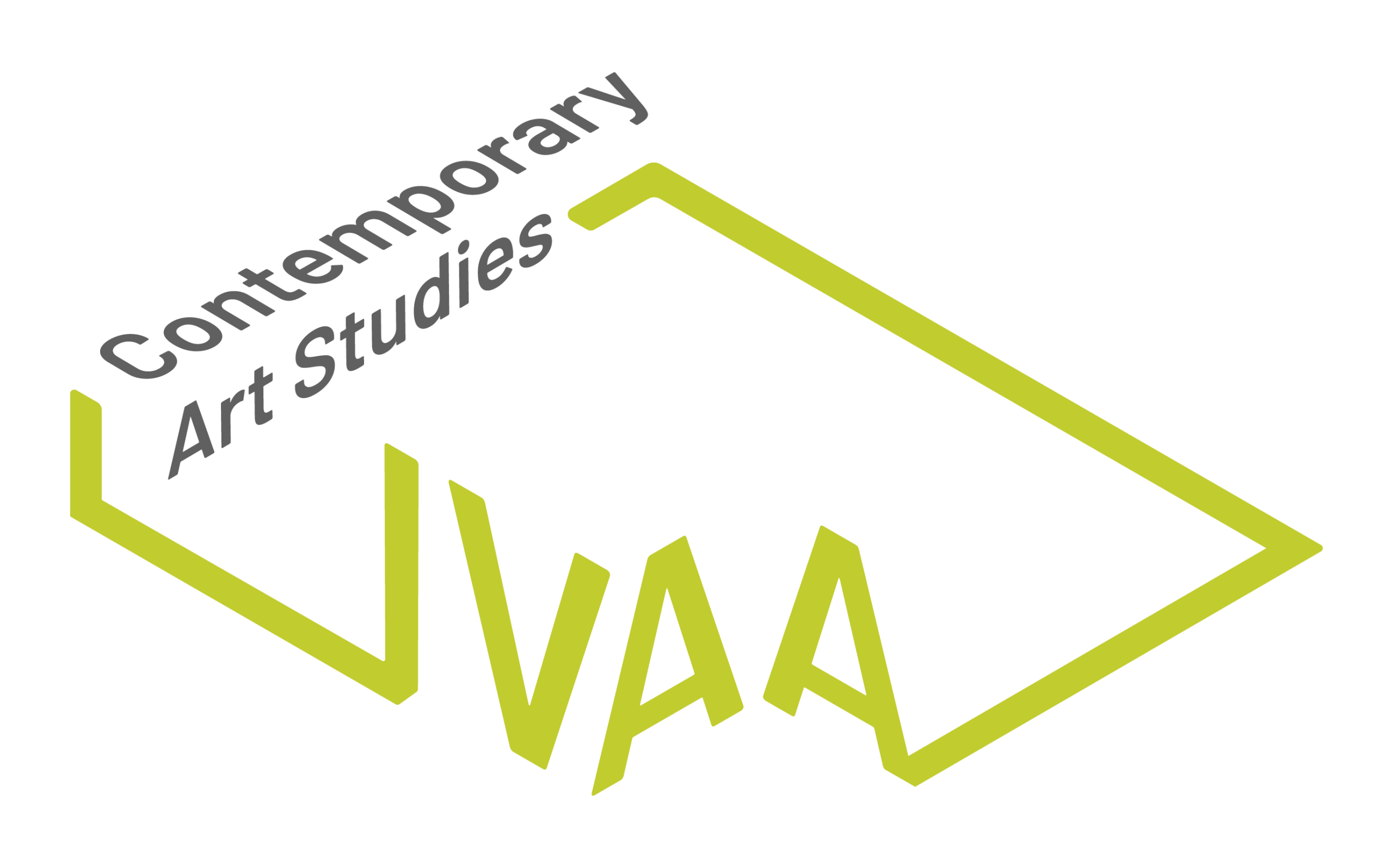Judul Buku : Omong Kosong di Rumah Seni Cemeti
Judul Buku : Omong Kosong di Rumah Seni Cemeti
Penulis : Wahyudin
Penyunting : Zulkarnaen Ishak
Pemeriksa Aksara : Reza Nufa
ISBN/ISSN : 978-602-5783-66-1
Resensi oleh : Sukma Smita Brillianesti
Suatu sore sebuah pesan singkat muncul dari notifikasi hape, “Ada pembukaan pameran nanti malam. Mau berangkat nggak?” Bagi saya, pesan tersebut terbaca tidak sebagai pertanyaan namun ajakan. Saya sudah sangat tahu bahwa kawan yang mengirim pesan itu ingin datang namun enggan datang sendiri. Sedetik kemudian terbayang oleh saya situasi pembukaan pameran. Mungkin akan ada performance art sebagai tanda dibukanya pameran, karya seni yang memenuhi ruang pajang beserta teks kuratorialnya, bertemu teman-teman pecinta seni tua-muda yang mungkin sebagian besar saya tidak kenal dan obrolan yang menyertainya, membuat saya ragu mengiyakan ajakan kawan tadi. Bukan apa-apa, namun bayangan suasana pembukaan pameran memang terkadang membuat saya canggung. Pengalaman rasa canggung itu saya kira cukup relate dengan judul buku berisi kumpulan tulisan Wahyudin ini. Paling tidak karena saya juga merasa cukup canggung pada nama besar dan karisma Cemeti, karya seni yang ditampilkan komplit dengan tulisan kuratorialnya serta rentetan obrolan dengan orang-orang yang akan saya temui pada saat hadir dalam semua perhelatannya.
Judul ‘Omong Kosong di Rumah Seni Cemeti’ untuk sesaat mampu mewakili keraguan saya atas ajakan kawan untuk berkunjung ke pembukaan pameran, bertemu banyak orang dan membicarakan seni rupa dengan berbagai versi pandangan. Pengertian omong kosong merujuk pada sesuatu yang kurang bermakna, dianggap tidak serius dan sambil lalu saja. Namun di Rumah Seni Cemeti. Masa sih? Bagaimana mungkin di Rumah Seni Cemeti yang memiliki reputasi, sejarah panjang dan peran besar dalam perkembangan seni rupa kontemporer ada hal tidak bermakna dan kurang serius? Saya tahu jika judul buku ini diambil dari salah satu judul tulisan Wahyudin yang mengulas rangkaian Pameran Omong Kosong di Cemeti tahun 2005. Namun, menjadikannya sebuah judul buku pasti merupakan hal lain. Pertanyaan dan penasaran saya lalu muncul, mendorong untuk memilih membaca kemudian mengulas buku ini.
Buku setebal 251 halaman ini berisi 30 tulisan Wahyudin, yang dituliskan dalam rentang 2003-2017 dan dimuat di berbagai media baik daring maupun luring. Dalam pengantar tulisannya, Wahyudin menyebut bahwa buku ini merampai catatan-catatan polemis tentang peristiwa, pameran dan buku seni rupa. Tiga puluh tulisan dalam buku ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama, “Di Rumah Seni Cemeti”, bersisi 14 esai ulasan pameran yang berlangsung di Rumah Seni Cemeti pada 2003-2006. Bagian kedua, “Di Sekitar Rumah Seni Cemeti”, terdiri atas 11 esai yang seperti judul bagian ini, berisi ulasan pameran dan proyek seni di ruang-ruang seni sekitar Rumah Seni Cemeti. Bagian ketiga, “Kecap Jauhari”, diisi dengan 5 esai yang mengulas empat buah buku seni rupa.
———-
Beberapa kali, ketika membaca buku yang berisi kumpulan esai, saya dengan tidak sabar langsung menuju halaman daftar isi. Rentetan judul beserta nomor halaman dalam daftar isi menjadi panduan saya untuk langsung menuju tulisan atau penulis yang saya anggap menarik. Kebiasaan ini tidak berlaku ketika saya membaca buku ini, atau paling tidak di awal saya mulai membaca buku ini.
Melalui pengantarnya, Wahyudin menuliskan bahwa bagian pertama dari buku ini merupakan ulasan yang dibuat dengan kesadaran kritis bahwa karya seni rupa kontemporer bukan hanya produk artistik yang perlu dikademati dalam permenungan sunyi insani, melainkan juga produk pengetahuan yang harus dicermati, diinterpretasi dan dievaluasi secara saksama dalam tempo secukup-cukupnya. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut yang membuatnya, setiap kali bertandang ke Rumah Seni Cemeti untuk suatu pameran seni rupa, meniatkan untuk tak sekedar menikmati setiap karya yang tersaji, namun juga berikhtiar penuh untuk memahami dengan nalar kritis. Yaitu dengan memeriksa secara saksama pilar artistik karya, menguji gagasan kuratorial dan mencermati pernyataan perupa terkait.
Hal-hal itulah yang kemudian menjadi kunci, yang digunakan Wahyudin, yang bermanfaat untuk lebih dari menikmati dan memahami seni rupa kontemporer, melainkan juga untuk memproduksi pengetahuan kritis yang beredar sebagai wacana publik. Kunci itu pula yang digunakan Wahyudin untuk meresepsi peristiwa seni rupa yang berlangsung di galeri-galeri partikelir, ruang seni rupa atau ruang gagas perupa di sekitar Rumah Seni Cemeti, yang terulas dalam kumpulan esai di bagian kedua dari buku ini. Disebutkan pula bahwa bagian kedua dalam buku ini merupakan refleksi pergeseran perhatian kritisnya dari Rumah Seni Cemeti, yang dianggap involutif dan letih menjaga api ‘revolusi dari ruang tamu’, ke inisiatif ruang-ruang seni di sekitar Rumah Seni Cemeti.
Dari refleksi pergeseran perhatian Wahyudin serta asumsi keterkaitan bagian pertama dan bagian kedua, saya mulai membaca buku ini secara runtut, dari awal. Beberapa tulisan awal pada bagian satu buku ini sudah pernah saya baca dari kliping yang dikumpulkan dan bisa diakses melalui online archive IVAA. Adalah ulasan kritis Wahyudin tentang perhelatan pameran di Rumah Seni Cemeti.
Wahyudin menepati janjinya, ia menggunakan kunci-kunci ajaibnya untuk membuka dan melakukan pembacaan kritis pada perhelatan pameran di Rumah Seni Cemeti, atau setidaknya beberapa. Misal, dalam ulasannya yang berjudul “Ada Dinosaurus…”, Wahyudin dengan gamblang memblejeti secara detail elemen artistik dalam pameran ini kemudian menawarkan pembacaan baru, hingga mengkritisi kegagalan kurator yang tidak mampu membangun ulang nilai atau makna karya yang kontekstual. Melalui kritiknya, Wahyudin menyangsikan bahwa penonton belum tentu bisa menarasikan ulang jajaran instalasi visual yang dipajang di ruang pamer. Ia bahkan menyebut bahwa teks kuratorial yang naratif dalam pameran itu terlihat mengabaikan dan tak memberi ruang pada penonton untuk melakukan interpretasi. Beberapa perspektif kritisnya dalam ulasan pameran tersebut bagi saya seolah menyiratkan bahwa Wahyudin merasa lebih mampu menarasikan ulang instalasi-instalasi tersebut, lebih baik dari sang kurator.
Berbeda dengan “Naif dan Sia-sia”, dalam ulasan pameran Counter Attract dan Playground di Rumah Seni Cemeti ini, ulasan Wahyudin di sini tak se-elaboratif “Ada Dinosaurus…”. Ia tak menggunakan kuncinya secara maksimal. Sebagai ulasan pameran, alih-alih mengupas elemen artistik karya ataupun bingkai kuratorial pameran, Wahyudin malah banyak menebarkan asumsi atas tingginya ekspektasi penonton pada pameran ini melalui premis grundelan sinis penonton yang menganggap kedua pameran ini naif dan sia-sia. Selain tidak banyak gambaran detail tentang elemen artistik karya, tulisan ini juga tidak disertai foto karya, sehingga saya sulit untuk merelasikan atau bahkan membayangkan grundelan penonton seperti yang dibicarakan Wahyudin. Mengutip kalimat paling pertama dalam tulisan ini, “Barangkali terlalu gegabah untuk meringkus rampung suatu proyek seni rupa yang belum sudah ke dalam prasangka: naif dan sia-sia”, saya sangat sepakat dengan ini, bahwa Wahyudin terlihat cukup gegabah dan terburu-buru dalam mengomentari kedua pameran tersebut.
———-
Setelah sekitar 6 atau 7 ulasan di bagian pertama buku ini tandas saya baca, saya mulai penasaran dengan bagaimana pergeseran perhatian yang dimaksud Wahyudin dalam pengantarnya. Akhirnya saya mengkhianati niat awal untuk membaca satu per satu dari awal hingga akhir dan langsung melompat ke esai pertama pada bagian kedua. Dalam ulasan pameran When I think about the death of painting, I play, saya lumayan kaget karena periode dalam pameran ini lumayan loncat jauh dari periode ulasan Wahyudin pada pameran-pameran di Rumah Seni Cemeti, lebih dari 10 tahun jaraknya. Meski demikian, kritik dalam ulasan pertama bagian kedua buku ini cukup jelas. Wahyudin banyak melontarkan data untuk memperkuat perspektif pembacaannya. Secara terang ia mengemukakan bahwa pameran ini lebih besar wacana ketimbang karya, bahwa pencapaian artistik para seniman tak sepadan dengan canggihnya wacana yang diusung sang kurator.
Masuk dalam esai kedua di bagian kedua buku. Adalah cerita naratif rencana perjalanan pameran sebuah kelompok seniman fotografi, Mes 56 ke Seoul, Korea Selatan. Berjudul “Keren dan Beken di Negeri Gingseng”, yang ditulisnya pada 2016. Paragraf demi paragraf saya jelajahi dengan seksama, sambil menahan rasa penasaran tentang bagaimana atau di sebelah mana Wahyudin akan menancapkan kunci kritis nan tajamnya. Hingga masuk ke beberapa paragraf akhir, dalam sebuah kutipan obrolan dengan salah satu anggota Mes 56, Angki Purbandono, saya menyadari bahwa tidak ada yang akan diblejeti. Tidak ada kunci yang akan digunakan. Dalam paragraf itu Angki menyebut bahwa kesempatan untuk memamerkan proyek Keren dan Beken di Korea Selatan tersebut merupakan suatu kehormatan untuk Mes 56. Dan atas dasar pernyataan ‘kehormatan’ tersebut Wahyudin urung menggunakan kuncinya.
Pertanyaan tentang bagaimana proses ‘refleksi pergeseran perhatian’ yang ditulis oleh Wahyudin dalam pengantar buku ini membuat saya mengubah cara membaca buku ini. Yakni dengan secara bergantian membaca bagian satu dan bagian dua buku berdasar tahun tulisan dibuat. Pada bagian kedua buku saya menemukan satu ulasan pameran yang isinya hampir mirip dengan ulasan pameran di bagian pertama, pameran di Rumah Seni Cemeti. Dalam pameran berjudul Mudah-mudahan Pameran (2004), dengan sindiran yang halus, Wahyudin menuruti disclaimer awal peserta pameran untuk memaklumi bagaimana kedangkalan gagasan yang hendak disampaikan melalui karya. Wahyudin juga menyebut bahwa meski benda-benda di dalam ruang tersebut telah dilegitimasi dengan nilai estetik oleh sang kurator, para peserta pameran toh gagal untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan karya tersebut secara estetik.
Melalui esai-esai yang ada di bagian kedua buku ini, Wahyudin tidak hanya mengulas perhelatan pameran, namun juga sebuah diskusi tentang polemik imitasi karya antara Arahmaiani Feisal dengan Syagini Ratna Wulan.
Perbedaan rentang waktu antara tulisan-tulisan di bagian pertama dan kedua buku menandai pergeseran perhatian Wahyudin dalam perhelatan seni rupa di Cemeti dan sekitarnya. Lebih dari itu, meski tetap memeriksa elemen artistik, bingkai kuratorial dan pernyataan seniman sebagai kunci pembacaan kritisnya, saya melihat bahwa cara pandang Wahyudin mengulas karya pun sedikit banyak juga bergeser. Pergeseran ini nampak dari cara dia mengulas pameran pada kurun waktu 2015 ke atas lebih menggunakan teori-teori sosial-humaniora secara dominan; tidak lagi berat di elemen formalisnya. Hal ini menurut saya tidak lepas dari perkembangan praktik seni rupa kala itu.
Membaca puluhan ulasan pameran dan peristiwa dalam buku ini sedikit banyak membuat saya kesulitan untuk memaknai dan lebih banyak berusaha membayang-bayangkan situasi pameran, bentuk karya dan situasi perkembangan seni rupa era itu. Minimnya foto dokumentasi dalam ulasan-ulasan di buku ini yang membawa saya pada situasi itu. Mungkin saya terlanjur menjadi milenial tulen yang tumbuh besar bersama budaya digital yang memuja jargon no pic hoax.
———-
Seusai rampung membaca dua bagian dari buku ini, saya kembali teringat penasaran awal saya atas isi buku ini, berdasar judul buku yang tersemat. Asumsi saya bahwa ada hal lain tentang dasar pemilihan judul dalam buku ini juga tidak terjawab ketika jari saya mulai membalik halaman bagian ketiga buku ini. Seperti yang ditulis Wahyudin dalam pengantarnya, bagian ketiga buku ini berisi telaah saksama yang dilakukannya dalam membedah 4 buku seni rupa. Yang saya rasa, perspektif Wahyudin dalam mengulas buku ini sangat tajam, cermat dan detail, meskipun diakuinya bahwa kedetailan serta ketajamannya melukai hati tim penyusun hingga pemuja buku-buku tersebut.
Ketiga pembabakan dalam buku telah beres saya baca. Dan saya tetap belum bisa menemukan benang merah yang mampu mengaitkan ketiga puluh tulisan ini dalam satu judul ‘Omong Kosong di Rumah Seni Cemeti’. Apakah saya terlalu naif karena mengamini sebuah petikan masyhur “don’t judge book by its cover”, di mana saya memahami bahwa judul adalah elemen tak terpisahkan dari cover? Hal ini membawa saya pada pertanyaan lain tentang apa dasar penentuan judul buku ini? Seperti apa pula pertimbangan penjudulan ketiga bagian dalam buku ini? Karena bagi saya, judul bagian pertama “Di Rumah Seni Cemeti” lalu bagian kedua “Di Sekitar Rumah Seni Cemeti” ini mengesankan hierarki Rumah Seni Cemeti sebagai pusat dan galeri atau ruang-ruang partikelir di sekitarnya yang tidak lebih dari penyangga.
Tentu saja pertanyaan dan kesan yang saya tangkap tersebut pasti terbaca sangat dangkal. Tapi bagaimanapun dangkalnya keingintahuan saya ini mungkin adalah wujud usaha saya untuk tidak hanya menikmati dan memahami tulisan demi tulisan dari buku ini, namun juga berusaha menelaahnya lebih jauh. Meski demikian, saya banyak menemukan cara pandang baru untuk melihat perhelatan, karya, buku hingga peristiwa seni di dalam buku ini. Saya juga memuji cara Wahyudin menggunakan kunci nalar kritisnya dengan penuh kedetailan dan ketajaman. Setidaknya, 30 catatan ini telah dengan baik dibekukan dalam sebuah buku untuk menjaga agar kritik pada masa lalu tidak luntur dan hilang begitu saja. Ulasan-ulasan dalam buku ini paling tidak mampu dijadikan kaca spion untuk sesekali menengok ke belakang demi menjaga laju dan merelasikannya dengan kerja hari ini.
Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2020.